Susahnya Berhenti Kepo Kehidupan Orang
Gue sedang menunggu Lola, Ayu dan suaminya, Awent, di suatu sore jelang buka puasa di sebuah hotel di Mataram. Kami hari ini berencana buat buka puasa bareng setelah beberapa tahun nggak ketemu dan melakukan ini. Sebenarnya ada dua orang lagi di geng ini tapi mereka berhalangan hadir jadilah kami hanya bertiga plus Awent sebagai penggembira. Mengatur sebuah acara buka puasa memang bukan perkara mudah, gue tahu. Tapi gue kira itu hanya terjadi buat orang-orang yang mengurus buka puasa buat 40 orang atau satu angkatan SMA atau kuliah. Tapi ternyata ngurus geng yang isinya lima orang ini aja ribet banget. Dan gue kira, dramanya sudah selesai sehabis dua orang tidak bisa datang dan hanya tiga orang yang konfirmasi. Ternyata sesampainya di lokasi, masih ada drama lain: meja kami nggak ada.
“Atas nama Lola?” kata gue ke petugas yang sedang membawa daftar tamu. Dia kemudian mengarahkan gue ke sebuah meja dengan enam kursi, yang mana nggak sesuai dengan pesanan dan jumlah rombongan kami. “Maaf tapi saya cuma berempat, ini kursinya berenam?” gue coba memastikan.
“Gak apa-apa mas nanti kalau lebih kursinya bisa kita angkat,” jawab dia.
Sebenarnya ada hal lain yang gue ingin komentari dari kursi itu tapi gue memutuskan untuk nggak mengeluarkan isi kepala dan hati gue. Gue laper, gue bisa marah-marah kalau itu gue lanjutkan. Udah hampir 24 jam dari gue minum obat anti-depresan gue dan gue rasanya agak susah menahan emosi. Trigger sekecil apapun bisa bikin mood gue rusak sampai sahur besok. Gue harus pandai-pandai menahan diri.
Seharusnya meja kami nggak di dalam, seharusnya di pinggir kolam. Soalnya Lola sebagai PIC lokasi sudah memesan meja di pinggir kolam. Tapi karena gue nggak sanggup lagi buat berkomunikasi lebih banyak, alhasil gue duduk di meja itu dan menunggu yang lain (sambil tetap ngomel-ngomel di grup chat WhatsApp kami lol).
Nggak lama setelah itu, berselang tiga atau empat menit, ada enam orang datang menghampiri meja gue. Gue seolah udah tahu ini akan terjadi karena dari jumlah kursi dan posisi meja aja ini tuh sebenarnya bukan meja gue. Tapi mas yang tadi meyakini bahwa meja itu dipesan atas nama Lola. Ada nama Lola juga di atas mejanya.
Serombongan orang-orang ini mendekat dan gue sudah siap-siap angkat kaki dari situ.
“Permisi mas, kami mau duduk di meja ini,” kata dia.
“Oh, maaf banget mbak. Tapi saya tadi sudah bicara sama petugasnya, meja ini atas nama Lola dan saya disuruh duduk di sini. Tapi mungkin saya yang salah, jadi saya tanya lagi aja sama petugasnya,” kata gue sambil berdiri dan kabur dari tempat itu. Untung banget gue pake masker jadi malunya nggak berasa-berasa banget.
Emosi gue udah mulai agak naik. Gue samperin lagi di mas-mas yang tadi dan gue bilang kalau meja yang dia kasih ke gue tadi bukan meja Lola teman gue tapi Lola yang lain. Ini kalo di drama Korea sebenarnya bisa jadi momen menarik dan menyenangkan yang berujung nanti gue ketemu dengan the love of my life. Tapi masalahnya ini real life, bukan drama Korea yang semuanya diromantisasi berlebihan itu. Yang ada malah mas-mas itu bingung karena dia bolak-balik lihat daftar tamu, nggak ada nama Lola yang lain di sana.
“Ini bukti reservasinya,” kata gue memberikan file PDF dari ponsel yang berisi detail reservasi dan bukti pembayaran. “Kemarin sih kami pesannya meja di pinggir kolam. Tapi saya tadi udah muter juga di pinggir kolam...” yang mana memang gue lakukan. “...tapi nggak ada juga meja atas nama Lola,” kata gue lagi.
Gue yakin mas-mas itu juga bingung dan dia juga bisa emosi lama-lama kalau gue terus ngerecokin pekerjaan dia kayak gini. Dia juga punya kerjaan lain ngurusin dan nyambut tamu yang baru dateng, bukan cuma ngurusin gue doang. Tapi beruntung dia punya kemampuan super dan pengalaman jadi instead of bolak-balik nyuruh gue ngecek reservasi, dia memberi solusi untuk pindahin satu meja lagi di sebuah ruang kosong di pinggir kolam dengan empat kursi seperti pesanan gue.
“Oke, nggak apa-apa mas, kayak gitu aja,” kata gue menutup pembicaraan dan menunggu mejanya selesai diberesin.
Beberapa menit berselang setelah gue duduk di meja yang baru, Ayu dan Awent datang. Lola seperti biasa, seperti yang selalu dia lakukan sejak SMA, datang sangat terlambat. Kita udah kenyang makan dia baru datang. Dan dalam perjalanan dia menuju ke lokasi, gue ngedumel terus ke dia soal reservasi yang salah nama itu.
Lola baru saja resign dari pekerjaannya di salah satu hotel (bukan tempat yang kita kunjungi itu) jadi dia menghubungi rekanannya yang bekerja di hotel tempat kita makan itu untuk melakukan reservasi. Ternyata, ada alasan kenapa tidak ada dua nama Lola yang ada di daftar tamu: karena dia pesan meja bukan atas nama Lola tapi atas nama hotel tempat dia bekerja dulu.
Kalau gue bawa baju ganti, gue nyebur ke kolam renang dah sore itu sekalian buka puasa.
“SAYA NGGAK MAU LAGI DATANG KE TEMPAT INI. MALU SAYA!” kata gue sambil jambak rambut Lola. Tapi moral of the story adalah dengan terjadinya kesalahan komunikasi tadi, kita bisa dapat meja di pinggir kolam (karena meja yang direservasi ternyata ada di dalam) dan gue bisa menyaksikan kejadian yang menginspirasi gue menulis blogpost ini.
Setelah meja yang di pinggir kolam beres dan bisa gue tempati, gue menunggu Ayu dan Awent sekitar 20 menit. Biasanya kalau lagi nunggu gini gue menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik lewat headset atau scrolling timeline media sosial. Tapi belakangan ini ngeliat timeline Instagram hanya nge-trigger rasa insecurity gue doang WKWKWKKW aneh banget deh, meski gue tahu bahwa media sosial memang isinya hanya konten sombong dan sesuatu yang dikurasi, orang-orang hanya menampilkan apa yang menurut mereka baik dan terbaik, tetep aja gue merasa iri dan membanding-bandingkan kehidupan gue sama kehidupan mereka. Asli ini mah GWS banget deh lu Ron.
Karena tadi sempat agak emosi soal meja, gue nggak mau mood gue jelek lagi gegara ngeliat update-an orang-orang di Instagram (bukan berarti semua update-an orang-orang bikin mood gue jelek, ya tapi lo tahu kan ada kalanya lo suka dengkian pas liat sosmed, ya kayak gitu deh lo ngerti deh kan maksud gue). Akhirnya gue taruh handphone dan memperhatikan sekitar. Di situlah gue baru sadar kalau tempat buka puasa gue dan geng SMA sore itu cukup hype dan eksis di kalangan influencer lokal. Hal yang menyadarkan gue adalah setiap meja diisi oleh orang-orang yang sejak tadi nggak lepas dari handphone, gue melihat busana yang mereka pakai semua serasi dan sangat-sangat fotogenik. Sementara gue hanya datang dengan kaus putih bergambar chibi Baekhyun dan kemeja flanel lengan pendek yang kancingnya dibuka semua.
Pakai baju putih itu ide Ayu sebenarnya.
“Sekarang bukber-bukber ini pake dresscode, kita juga dong biar kayak orang-orang!” gitu kata dia.
Tapi gue nggak nyangka kalau putih itu adalah pilihan warna semua orang karena hari itu rasanya seperti sedang ada outing kantor. Semua orang di restoran itu pake baju putih. Gue bisa aja nimbrung ke meja orang dan mereka nggak akan sadar kalo gue bukan salah satu dari geng mereka.
Dari semua orang, semua influencer yang ada di lokasi itu, ada satu meja yang benar-benar membuat gue nggak bisa fokus. Asli, gue mencoba untuk mengalihkan pandangan gue dari meja ini tapi sama sekali nggak bisa. Selain mata dan kepala gue nggak bisa berpaling dari sana, otak gue pun nggak bisa berhenti bergunjing. Beneran puasa gue 27 hari rasanya gak ada gunanya karena kok hati dan pikiran gue masih kotor aja.
Sejak gue duduk di kursi berlapis kain putih itu (ya kan, semua putih!), orang yang ada di depan gue ini sibuk banget sama handphone-nya. Sesibuk itu sampai setiap pergerakan dia selalu menghadap ke kamera depan. Selama gue menunggu meja sampai meja gue kelar, mungkin sudah ada lebih dari 30 foto selfie yang dia jepret. Selama gue nunggu Ayu dan Awent, mungkin sudah ada satu album Hits TikTok Terpopuler yang dia jogetin. Berkali-kali juga dia minta difotoin sama temannya di dekat meja, di dekat pohon, di dekat kolam. Dan dua menit sebelum azan, dia duduk santai dengan tentu saja mengunggah konten makanan buka puasa hari itu. Setelah azan dimulai, dia meletakkan ponselnya di atas meja, disandarkan ke gelas, lalu memulai Live Instagram sambil makan.
Jujur, gue bisa aja mengalihkan pandangan gue ke yang lain (dan gue sudah berusaha melakukannya!), tapi sudut mata gue selalu mengarah ke orang ini karena posisi mejanya bener-bener strategis di wilayah pandang gue. Setelah Ayu dan Awent datang, gue mengucap syukur dengan keras karena akhirnya perhatian gue bisa sembilanpuluh lima persen teralih dari orang itu ke dua temen gue ini.
“Saya udah nahan-nahan ini dari tadi, tapi beneran deh, orang yang di belakang kamu itu, dari setengah jam yang lalu, selfie terus, TikTok-an terus, dan sekarang dia buka puasa juga Live IG. Kenapa ya nggak bisa, yaudah, makan aja gitu? Orang lain kan juga buka puasa ya, emangnya ada yang nonton?” gue ngomel-ngomel sambil ngunyah kurma.
“Influencer itu, kelihatan dari gayanya,” kata Ayu.
“Iya kayaknya semua orang yang datang hari ini influencer deh. Kita doang yang kayaknya influenza.”
Nggak ada yang ketawa.
Kejadian itu kemudian membawa ingatan gue ke satu momen di sekitar tahun 2015. Tahun-tahun awal gue kerja setelah lulus kuliah dan masih sering banget nongkrong sampai malam hari sama temen-temen gue di Family Mart/Seven Eleven di seputaran Blok M/Pasar Santa. Di tahun-tahun ini juga kami bisa setiap dua hari sekali karaokean. Malam itu kami lagi ada di Inul Vizta yang nggak jauh dari Stasiun MRT Blok M sekarang. Seinget gue itu malam Jumat karena salah satu dari temen gue sempat nge-joke soal “harusnya kita ngaji ini malah karaoke”. Persis setelah dia ngomong gitu, pintu lift terbuka dan kita semua masuk satu-satu ke dalam lift, menyisakan ruang untuk paling nggak tiga orang. Pintu lift nyaris tertutup ketika seseorang memencet tombol pintu dari luar dan pintu lift terbuka lagi. Tiga orang masuk: dua Bapak Bapak dengan jas dan kemeja putih dan satu orang perempuan dengan tanktop hitam dan celana jins. Sebut saja dia Kembang.
Posisi gue sekarang persis di belakang salah satu dari dua Bapak Bapak itu dan di sebelahnya adalah Kembang. Gedung tempat karaoke itu nggak terlalu tinggi jadi nggak akan terlalu lama kami ada di dalam lift. Tapi apa yang terjadi selama beberapa detik di depan mata gue itu cukup bikin tidak nyaman dan membuat gue untuk ingin segera keluar dari sana. Belum lagi aroma rokok yang menguar di ruang sempit itu bener-bener membuat gue sesak (gue nggak merokok anyway dan di tahun itu toleransi gue terhadap asap rokok nggak sebaik sekarang; jadi itu kek sesek napas beneran). Beberapa kali gue dan temen gue bertukar pandang dan suasana jadi agak canggung lantaran tadi ketika kami masuk lift, kami masih berisik dan bawel banget, tapi ketika tiga orang itu menyusul kami jadi kalem dan diam. Mata gue kemudian menangkap sebuah pergerakan dari si Bapak Bapak. Tangannya bergerak dari posisi awal ke bagian tubuh belakang Kembang. Pelan-pelan tangan bapak itu naik masuk ke dalam baju dan mengelus-elus punggung Kembang.
Asli itu cuma dua atau tiga lantai deh tapi lift itu rasanya kayak naik ke lantai 30.
BISAKAH AKU KELUAR DARI SITUASI INI SESEGERA MUNGKIN YA ALLAH.
Setelah kami semua keluar dari lift, gue dan temen-temen gue bertukar pandang lagi. Nggak ada satu pun dari kami yang mencoba untuk membahas atau membicarakan apa yang tadi kami saksikan di dalam lift. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah biasa kami lihat, sudah tidak perlu dipertanyakan, atau sebenarnya kami hanya orang-orang canggung yang nggak pernah berani menyentuh ranah “itu”. Gue akui di tahun-tahun ini memang pergaulan gue masih sempit. Apa yang lo harapkan dari seorang fresh graduate yang barely even makes any friends in college. LOL. Temen-temen gue yang paling dekat sekarang adalah temen-temen kampus gue dan kita semua adalah orang-orang yang lingkarannya itu lagi itu lagi. Apalagi gue kan dari dulu orangnya emang agak “kolot” dalam artian hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang “luar biasa” buat gue. Tapi gue yakin salah satu dari teman-teman karaoke malam itu sudah jauh lebih terbiasa dengan apa yang kami sama-sama lihat tadi.
Mungkin kondisinya kalau gue sedang sama temen-temen SMA gue, kami akan membahas itu dari awal masuk ruang karaoke sampai kita keluar lagi. Mungkin bahkan kami nggak akan nyanyi tapi malah ngegosip. Tapi karaokean gue malam itu berjalan lancar tanpa ada satu pun dari kami yang membahas soal kejadian di lift.
Ketika gue mengingat lagi kejadian itu saat ini, gue nge-judge diri gue so hard.
Betapa malam itu gue sangat ke-trigger untuk membahas kejadian itu, untuk membicarakan apa yang gue lihat, gue adalah orang yang baru keluar dari goa dan baru lihat hal-hal seperti itu di Jakarta dengan mata kepala gue sendiri. Gue punya banyak pertanyaan dan gue ingin tahu lebih banyak soal itu.
Gue lantas bersyukur teman-teman gue malam itu memilih untuk tidak membicarakannya atau tidak meladeni wajah penasaran dan rasa ingin tahu gue yang tidak terkatakan. Dari situ gue pun belajar bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, dibahas, atau dibicarakan lebih lanjut. Terlebih kalau itu sudah menyangkut kehidupan orang lain yang nggak ada hubungannya sama sekali sama diri kita. Oke, gue mungkin terdengar munafik karena sampai sekarang pun gue masih tetap membicarakan orang lain dengan teman-teman terdekat gue. Apa gunanya kumpul-kumpul se-geng kalau nggak membahas gosip-gosip terkini seputar kehidupan selebriti, selebgram, dan seleb-seleb kehidupan nyata lainnya, kan? Tapi dalam konteks “anon” seperti tiga orang yang gue lihat malam itu, cukup dilihat lalu dilupakan. Meski tidak mudah, tapi sebaiknya dilihat dan dilupakan.
Tidak adanya respons dari teman-teman gue malam itu membuat gue berpikir bahwa kehidupan orang mungkin sesulit itu sampai mereka menempuh jalan tertentu yang berlawanan dengan moral atau nilai yang dianut oleh orang lain. Moral dan nilai-nilai kehidupan setiap manusia pun berbeda-beda. Apa yang lo anggap benar atau salah belum tentu dianggap salah atau benar oleh orang lain. Menyampaikan pendapat lo bukan berarti untuk memaksakan sebuah pola pikir ke seseorang tapi lebih ke penyampaian sudut pandang yang berbeda bahwa satu hal yang sama bisa dimaknai lain oleh masing-masing individu yang melihatnya.
Jujur sulit banget rasanya menjalani hidup tanpa memberikan penilaian terhadap semua hal yang kita lihat atau dengar. Dalam konteks film atau musik mungkin, memberikan pandangan atau judgement terhadap sebuah karya mungkin terasa lebih simpel—ya tapi kecuali lo berhadapan sama fans Marvel, fans Harry Potter, atau fans K-Pop, nggak ada yang simpel kayaknya WKKWKWWKKW—karena ini menyangkut soal selera. Tapi dalam hal bagaimana orang menjalani kehidupan mereka, itu levelnya udah sangat personal dan kita sebagai orang yang nggak berkontribusi apapun terhadap kehidupan seseorang nggak ada hak untuk memberikan penilaian atau judgment terhadap apa yang mereka lakukan, keputusan yang mereka ambil, atau jalan yang mereka pilih buat hidup mereka.
Gue nggak bilang kita harus selalu memaklumi keputusan atau cara orang lain menjalani hidupnya lalu kemudian kita menormalisasi hal tersebut. Tapi kalau pun ada cara hidup orang lain tidak sesuai dengan nilai hidup kita, kita juga nggak perlu terlalu menyalahkan. Ada bagian dari cerita yang kita nggak tahu di luar apa yang sudah kita lihat atau dengar sebelum akhirnya kita jatuh pada sebuah penilaian benar/salah. Cerita yang mungkin kalau kita tahu, pandangan kita akan jauh berubah.
Quote dari Dokter Jiemi Ardian ini mungkin di luar konteks yang dia maksudkan dari thread yang di abuat, tapi bagian yang tebal gue rasa masih cocok dengan apa yang gue sampaikan di kalimat-kalimat sebelumnya: Bukan sekedar siapa yang benar dan salah. Belajar melihat bahwa mungkin rasa sakit ini perlu dikenali dan dirawat, tanpa ngotot menyalahkan, juga tanpa permisif membenarkan yang keliru.
Gue pernah terlalu peduli pada kehidupan orang lain dan itu membuat gue merasa sangat berkonflik dengan diri gue sendiri sekarang. Betapa dulu gue merasa bahwa gue mampu untuk memberikan sebuah perasaan nyaman pada seseorang dengan hal-hal yang gue miliki dan tidak dia miliki. Sebuah konsep yang gue sendiri nggak paham, kenapa gue bisa menganutnya, atau gue belajar dari aliran sesat mana. Gue dulu adalah orang yang sangat posesif dan cenderung ingin bisa mengontrol semua hal. Ketika gue melihat ke belakang, betapa begitu banyak waktu yang gue habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan atau dilakukan.
Gue sedang belajar untuk tidak terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Sebenarnya cara paling gampang adalah tidak punya media sosial. Tapi gue belum bisa sampai di tahap itu. Cara yang bisa gue lakukan sekarang hanya memanfaatkan fitur mute post/story di Instagram sehingga gue nggak perlu tahu orang-orang sedang ngapain tanpa harus berhenti mengikuti akun media sosial mereka. Gue yakin orang juga nggak perlu tahu kok gue sedang di mana atau lagi makan apa, atau film terakhir apa yang gue tonton, atau sekarang apa yang lagi mengganggu pikiran gue saat ini, dan sebagainya. Saat ini gue hanya menggunakan media sosial seperti tujuan media sosial dibuat: untuk pamer.
Yah, well, walaupun sejatinya nggak gitu-gitu amat sih. Tapi silakan cek LinkedIn kalau mau tahu lebih lanjut. WKWKWKWKWKKW.
Dan gue cuma butuh meyakinkan diri gue bahwa gue pun tidak perlu tahu semua itu, kecuali mereka memutuskan untuk memberitahu gue dan berkomunikasi dengan gue sekarang langsung.
Susah memang berhenti kepo pada kehidupan orang lain. Tapi ada kalanya kita harus menahan diri dan berhenti paling nggak untuk kesehatan diri sendiri.









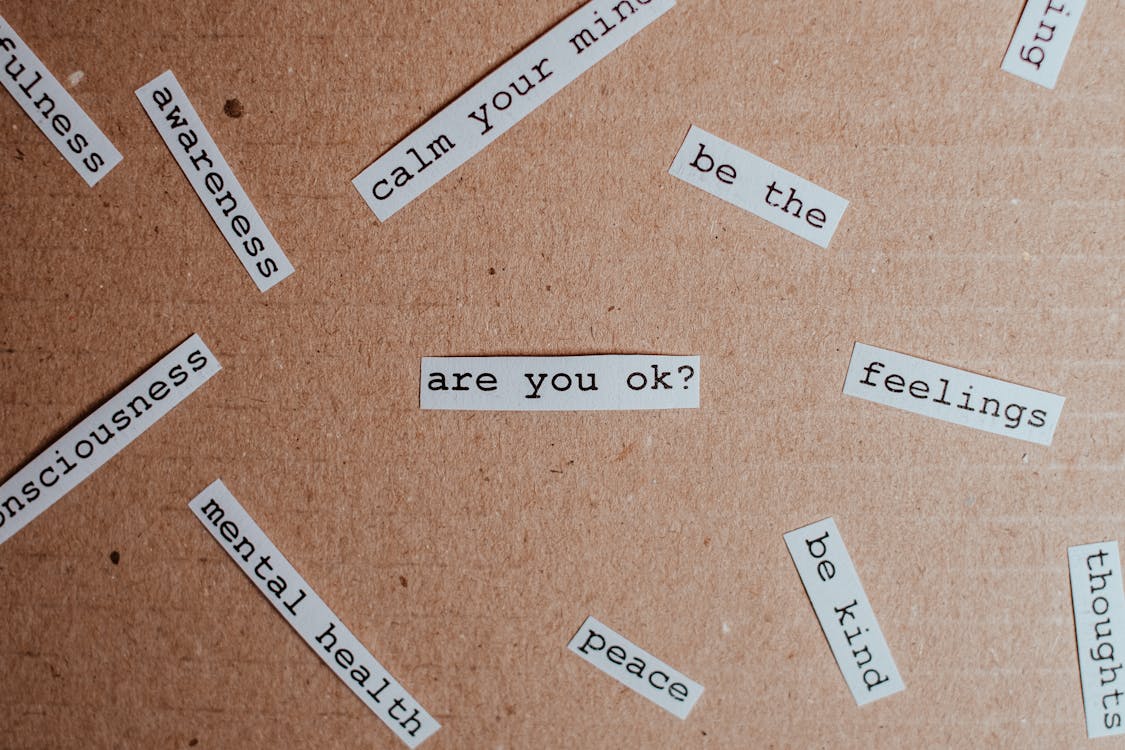









0 comments