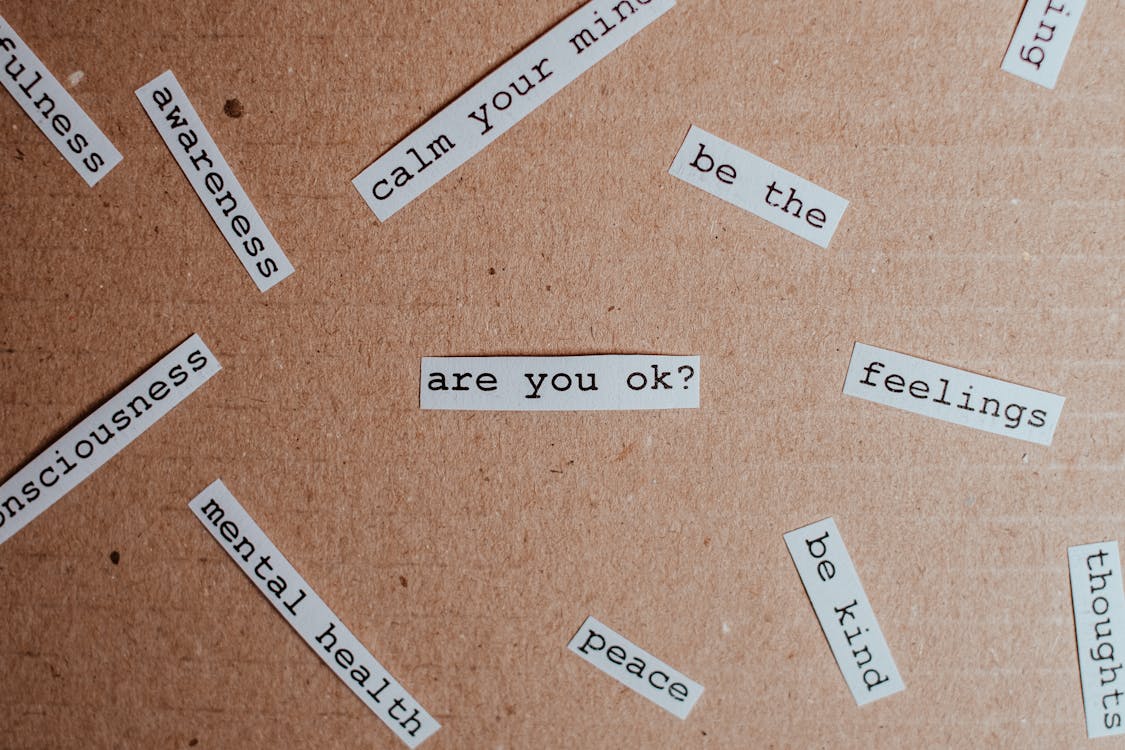Gue udah terlalu lama mengabaikan blog ini sampai akhirnya kemaren gue bikin satu konten di Instagram yang mengingatkan gue dari mana gue memulai semuanya: dari sini. Dari blog ini.
Gue sedang duduk di meja kerja ringkih dari besi ringan dan papan sederhana yang gue beli di masa pandemi COVID-19 (yang gak nyangka ternyata udah 5 tahun aja lo!). Pikiran gue sedikit berkecamuk karena banyak hal. Sejujurnya, depresi gue belakangan ini sedang dalam fase yang gak berat banget, tapi di saat yang sama gue juga gak bilang kalau hidup sedang baik-baik saja. Gue hanya sedang... bingung dan sedikit kewalahan.
Gegara postingan Instagram itu gue akhirnya buka dashboard blog gue lagi. Update beberapa hal yang udah outdated dan gak sengaja skrol ke kolom komentar tulisan terakhir gue (yang gue sendiri gak sadar kalau widget Disqus itu masih bisa dipakai) lalu baca beberapa komentar di sana. Gue gemeter sedikit soalnya komentarnya pada baik-baik banget. Gue kemudian berpikir, 'oh orang tuh masih bisa relate sama tulisan gue ya?'
Gue dipaksa lagi kembali ke prinsip pertama gue bikin blog ini: untuk menulis, bukan untuk dibaca. Tapi sekarang setelah era istilah 'content creator' jadi makin banyak dan sering digunakan, seenggan apa pun gue untuk ikut arus tapi gak kerasa gue ketarik ombak juga. Gue mikir 'apa ini yang pada akhirnya bikin gue stuck?'
Ini yang gue maksud adalah 'keinginan untuk terus selalu dikasih validasi dan lupa dengan prinsip awal bahwa yang penting nulis, gak penting ada yang baca atau nggak'.
Beberapa orang juga muncul di komentar Reels yang gue bikin di Instagram, para pembaca lama blog ini. Sebagai orang yang haus validasi banget (WKWKWKWKWKK I KNOW I'M SORRY, I'M STILL ON THERAPY OK, GO EASY ON ME) itu bikin perasaan gue jadi tenang sedikit, lega sedikit. Ternyata masih ada yang ingat identitas blog ini dan siapa orang yang nulis, terlepas dari banyaknya tulisan yang mungkin sangat self-centred dan blunder. Tapi ya, jejak digital gue sebenarnya gampang banget dicari. Kalau lo cek tulisan di blog ini dari 10 tahun yang lalu, pasti akan ada banyak yang bisa jadi amunisi buat menyerang dari segala sisi.
The only thing I can say is that I changed.
Mungkin ada pemikiran dan pendapat yang tertulis beberapa tahun lalu, yang kalau gue baca lagi sekarang, gue pun akan memperdebatkan itu dengan diri gue sendiri. Dan banyak di antara hal-hal itu adalah soal dinamika fandom (EXO terutama) dan K-Pop. Ngomongin soal EXO, baru-baru ini gue kan liputan konser Kai di Jakarta dan itu juga jadi momen gue balik lagi ke bagaimana blog ini ada di era kejayaan EXO itu.
Itu bikin gue banyak berpikir dan berkontemplasi. Gue ketemu beberapa orang yang kenal gue dari blog ini di venue konser hari itu. Bahkan gue randomly bumped into one of long time EXO fans yang juga pembaca blog gue dan kita malah jadi nonton konsernya bareng. Ternyata kita masih orang-orang yang sama. Masih seheboh itu ngeliat grup ini bahkan setelah banyak sekali perubahan dan badai yang menyerang.
Gue bersyukur pernah jadi bagian dari dinamika fandom EXO dari awal sampai saat ini. Terlepas dari beberapa di antara kita mungkin punya pemikiran yang berbeda mengenai banyak hal (semisal siapa pacaran sama siapa atau ChanBaek is real sementara sebenarnya mungkin enggak juga), kita sama-sama sayang sama grup ini. WKWKWKKWKWKW Gue rasa, rasa sayang itu yang kemudian mendorong gue untuk kembali lagi ke blog ini dan punya pemikiran untuk memulai lagi.
Gue gak tahu sih sebenarnya apa yang harus gue mulai lagi. Tapi trigger-nya belakangan ini banyak banget. Ketika gue baca komentar di postingan terakhir gue itu juga jadi salah satu trigger untuk memulai lagi. At least untuk menumbuhkan semangat buat re-start, re-start, dan re-start.
Kehidupan memang lagi gak baik-baik aja, gue terombang-ambing ke sana ke mari karena banyak hal. Tuntutan hidup yang mungkin exist karena gue bikin sendiri, sementara sebenarnya semesta gak terlalu gimana-gimana banget soal itu.
So... where am I now?
I'm still here.
I will try, and try again.
I might fail again but who cares.
If I fall, I just need to stand up again and try again.
Semoga lancar semuanya wkwkwkwkwkwkkw (mendadak ragu).
***