I dont like change, but... I changed.
Pernah ada teman gue yang datang dari Lombok dan menginap di salah satu hotel di pinggiran Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan dia mengaku diganggu sama makhluk halus. Lampu kamarnya tiba-tiba mati-nyala-mati-nyala, bahkan ketika teman sekamarnya lagi mandi, lampu kamar mandi mendadak mati. Ketika dia cerita ke gue, gue cuma bisa ketawa karena memang ceritanya (atau mungkin cara dia menceritakannya yang membuat itu jadi) lucu (walaupun menurut dia itu teror menyeramkan), di situ gue baru menyadari satu hal: selama hampir 10 tahun gue di Jakarta, gue nggak pernah lagi merasakan takut pada makhluk-makhluk halus atau yang biasa kalian sebut hantu (pakai suara Prilly Latuconsina di trailer Danur 1). Akhirnya gue bilang ke temen gue,
“Saya selama di sini (di Jakarta maksudnya) lebih takut sama manusia daripada sama hantu. Saya lebih takut sama begal, rampok.”
For some reasons apa yang gue bilang itu adalah fakta. Hantu, kalau memang dia hanya iseng, nggak akan menyakiti lo sampai mengeluarkan isi perut lo atau mengobrak-abrik usus lo misalnya hanya karena mereka kesal, tapi manusia bisa melakukan itu. Pandangan gue soal hantu versus manusia ini sangat berbeda dengan ketika gue masih tinggal di Lombok dulu. Sepanjang masa kanak-kanak sampai remaja, gue besar dengar cerita-cerita horor di kampung yang rasanya terlalu nyata untuk tidak dipercaya. Ngerti kan maksud gue? Ada nuansa yang berbeda ketika lo mendengarkan cerita horor di rumah nenek yang ada di pedesaan misalnya dengan ketika lo mendengar cerita horor soal hotel mewah di pusat Jakarta yang hantunya cuma iseng mati-nyalain lampu.
Dulu waktu gue SD sampai SMA, gue nggak pernah berani keluar rumah di atas jam 9 malam. Ada kebun di belakang rumah nenek gue yang berhadapan dengan gerbang rumah gue. Di depan gerbang gue ada dua pohon kelapa yang punya banyak sekali cerita. Di kampung gue ada isu kalau salah satu dari penduduknya melakukan pesugihan dan di malam Jumat mereka akan berubah wujud dari manusia ke entah babi atau kucing jadi-jadian, sampai burung menyeramkan yang biasa kita sebut dengan nama Tengkeyas. Gue nggak pernah lihat bentukan Tengkeyas ini seperti apa, tapi menurut rumor, ini adalah burung besar dengan kepala manusia. Dia hanya keluar di malam hari dan suaranya nyaring kayak “Kyas! Kyas! Kyas!” gitu. Pernah di suatu malam gue lagi asyik main komputer di kamar kakak gue, Tengkeyas ini lewat di atas rumah gue dan suaranya bener-bener jelas banget. Entah itu beneran makhluk dengan badan burung dan kepala manusia atau hanya suara burung hantu. Gue nggak pernah benar-benar memastikannya.
Cerita-cerita seperti ini begitu mendarah daging sampai-sampai setiap kali gue pulang di liburan kuliah, gue akan selalu merasakan aura yang berbeda. Ketika di Depok gue merasa baik-baik saja dan “kebal horor” mengingat gue bisa pulang jam 1 malam dari Detos dan jalan kaki ke kosan setelah nonton film horor misalnya, di rumah gue benar-benar lemah. Tapi ada satu hal yang lebih menakutkan dari hantu menurut gue: tokek.
Makhluk menjijikan itu selalu meneror gue setiap kali gue pulang ke rumah dan gue selalu berisik soal itu ke orang di rumah. Bahkan setelah gue masuk usia 30 tahun, gue masih nggak berani sama sekali sama binatang ini. Gue tahu, mereka hanya nempel di dinding dan nggak melakukan apa-apa. Sesekali mungkin mereka mengeluarkan suara menyebalkan yang terdengar seperti nenek-nenek jompo ambisius yang sedang menirukan suara Mariah Carey. Tapi hanya dengan keberadaan mereka di dinding saja sudah bisa bikin gue teriak dan membangunkan orang satu kampung.
Orang-orang di rumah, termasuk keponakan gue, nggak ada yang takut sama binatang ini. Karena mereka nggak ada yang takut, di mana pun binatang itu merayap nggak akan ada yang peduli. Makanya ketika gue pulang dan gue heboh, mereka selalu bilang “Kemaren-kemaren nggak ada lho dia!” gitu. Padahal menurut gue sebenarnya mereka ada, tapi karena orang-orang nggak takut aja makanya jadi berasa nggak ada. Itulah yang gue rasakan dengan hantu dan makhluk halus di Jakarta.
Tokek ini paling doyan ada di belakang pintu kamar mandi rumah gue. Jadilah setiap kali gue mau ke kamar mandi, gue akan minta tolong nyokap atau kakak perempuan gue buat ngecekin. Gue nggak akan masuk kamar mandi sebelum mereka memastikan kalau benda itu tidak ada di belakang pintu. Malah sekarang, untuk ukuran gue ini bener-bener sebuah perkembangan, gue kalo pipis nggak pernah tutup pintu. Karena kalau pintu terbuka, bagian tempat si tokek itu hinggap nggak akan kelihatan jadi gue nggak perlu tahu ada dia di sana.
Ketakutan gue sama tokek ini sama seperti ketakutan lo sama apapun yang membuat lo takut. Takut gue ini lebih ke jijik melihat tampangnya yang hitam, kulit kasar, dan mata yang melotot nggak kira-kira itu. Sebagai orang yang “visual” (bukan dalam arti ganteng seperti idola K-Pop gitu, tapi dalam arti gampang mengingat secara jelas apa yang barusan gue lihat dan itu akan nempel di kepala gue dalam waktu yang lama sampai gue benar-benar menemukan pengalih perhatiannya) gue akan kebayang terus muka jelek itu dan bikin gue panik sampai takut. Perasaannya mungkin persis kayak orang yang punya indera keenam terus merasa bahwa di lokasi mereka sekarang ada setannya. Gue pun bisa merasakan gesekan tubuh sampai gerakan supercepat si tokek itu merayap di tembok terdekat dengan gue.
Keponakan gue sampai sering nyinyirin gue setiap kali gue mau mandi atau ke kamar mandi.
“Pasti Ommon manggil Mbah buat ngeliatin tokek, kan?”
“WKWKKWKW IYA KOK TAHU?”
“Ya tahulah orang sering kayak gitu kok!”
“Ya kamu bantuin aku dong, lihatin tokeknya ada atau nggak?”
“Oke yaudah tunggu,”
Akhirnya ponakan gue yang belum sekolah itu menyelamatkan hidup gue dari kebelet buang air besar.
Tapi belakangan ini gue bisa berpikir jernih dan merasakan hal yang berbeda soal ketakutan gue itu. Entah apakah ini efek dari obat yang gue minum yang membuat gue bisa mengalihkan pikiran dan perasaan takut itu ke hal lain, atau memang pelan-pelan perasaan takut gue sama tokek ini sudah berkurang. Gue nggak mau kepedean sih sebenarnya tapi ini berasa banget. Semisal di tengah malam gue kebelet banget ke kamar mandi dan nggak mungkin membangunkan nyokap, gue akan tutup pintu kamar mandi dan nunduk sepanjang gue melakukan bisnis gue di sana. Sebisa mungkin gue nggak melihat ke arah dinding pokoknya bagaimana caranya gue nggak tahu dan nggak lihat benda itu, gue aman.
Ada untungnya juga ini obat ya ternyata WKKWKWKWKWKW (YAGITU) (GAK DENG CANDA). Tapi jujur, gue merasakan banyak perubahan setelah gue memutuskan untuk ke dokter dan menangani anxiety gue. Yang paling berasa adalah soal tekanan dan pikiran-pikiran yang tidak penting yang pada akhirnya bisa jauh berkurang dari sebelumnya. Kondisi otak gue yang kosong dengan pikiran buruk ini pada akhirnya membuat gue bisa fokus ke perasaan-perasaan yang lain, ke pikiran-pikiran yang lain, walaupun gue harus akui bahwa masih ada sisi dari diri gue yang selalu berusaha untuk menjatuhkan diri gue dengan hal-hal negatif, tapi serangannya nggak sehebat dulu. Gue bisa lebih mengontrol diri dengan bilang bahwa “ini cuma di pikiran gue, ini nggak nyata, ini nggak benar-benar terjadi, ini bukan realita”. Kalau dulu rasanya mengatakan hal-hal itu sama aja kayak menebar garam di lautan, tapi sekarang gue bisa merasakan efeknya.
Ini perubahan yang baik kan? Menurut gue sih iya.
Kalau mengingat diri gue yang dulu, gue bukan orang yang mudah menerima perubahan. Ada ketakutan-ketakutan yang tiba-tiba muncul dan kadang nggak beralasan atau alasannya dibuat-buat, dibuat seolah-olah masuk akal padahal sebenarnya nggak masuk akal. Memang sih ini agak kompleks dan nggak serta-merta hanya karena satu faktor saja. Ada faktor-faktor lain yang terjadi di saat yang sama tapi kadang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang pada akhirnya ketika sebisa mungkin diutarakan hasilnya hanya kalimat-kalimat yang ambigu.
Let me give you some examples...
Dulu gue pernah punya teman sekamar. Gue nggak akan repot-repot menceritakan kenapa gue bisa punya teman sekamar dan kenapa akhirnya gue yang introverted as fuck ini memilih untuk punya teman sekamar. Yang pasti kita tinggal sekamar satu tahun dan itu adalah tahun paling berat dalam hidup gue. Bukan karena keberadaan dia di sana tapi karena gue sama sekali nggak bisa beradaptasi dengan perubahan.
Awalnya gue pikir gue bisa jadi teman sekamar yang baik dan jujur demi Allah gue selalu berusaha jadi teman sekamar yang baik. Tapi ada kalanya ketika jiwa gue sedang bergejolak dan gue kemudian melakukan sesuatu yang mungkin menyinggung atau apa, lalu dia melakukan sesuatu yang mungkin juga membuat gue tersinggung atau apa, lalu kita nggak berusaha menyelesaikan konflik secara sehat dan semua berujung hanya jadi jerawat. Singkat cerita, teman sekamar gue ini memutuskan untuk pindah.
Gue nangis.
Nggak tahu kenapa gue nangis.
Di situ pikiran gue kacau. Apakah selama ini gue udah jahat? Apakah gue ada salah? Apakah ada tindakan gue yang membuat dia akhirnya memilih untuk keluar? Apakah selama ini komplain-komplain gue ke orang lain yang dia kenal akhirnya ketahuan? Muncul berbagai pertanyaan di kepala gue yang sama sekali nggak terjawab sampai akhirnya dua atau tiga tahun kemudian gue tahu sendiri jawabannya. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, ada satu pertanyaan besar yang sangat-sangat mengganggu: apakah gue siap dengan perubahan lagi?
Punya teman sekamar membuat gue sadar banyak hal dan belajar banyak hal. Tapi sayangnya, gue nggak punya kesempatan untuk memperbaiki diri di tahun-tahun berikutnya atas pelajaran dan hal-hal yang gue sadari di tahun pertama itu. Karena ya nggak ada tahun-tahun berikutnya. Ketakutan gue pada saat itu adalah hubungan kami akan berubah.
Ketika gue memutuskan untuk tinggal bareng dia, gue merasa nyaman dan kami bisa berkomunikasi dengan baik. Gue merasa kami bisa jadi teman sekamar yang baik, yang supportive, yang bisa saling bantu. Ya selama setahun itu gue melihat kami sama-sama berusaha sih, tapi di tengah usaha itu kami juga menyimpan banyak rahasia pribadi yang masih sama-sama nggak nyaman untuk dibagi. Jadinya komunikasi kami terhalang tembok besar dan topeng kami masing-masing. Ini menyangkut permasalahan keluarga, pertemanan, percintaan, dan segala hal yang mungkin nggak nyaman untuk diceritakan karena berbagai alasan yang jujur gue nggak perlu tahu. Tapi FYI aja, gue merasa bukan orang yang jahat dan gue bisa jadi teman cerita kalau gue diberi kesempatan. Tapi mungkin gue saat itu dirasa belum layak untuk berbagi cerita penting itu jadi ya semuanya berakhir sampai di situ.
Ketakutan gue akan perubahan di antara hubungan pertemanan kami itulah yang bikin gue kewalahan dengan perasaan jadi ketika dia bilang dia mau pindah, gue nangis kayak orang gila. Mana nangisnya di Kota Kasablanka lagi pas mau liputan showcase VIXX. Ya kan anjing. Eh ya maaf ngumpat.
Gue ingat banget satu kalimat yang gue katakan saat itu, atau mungkin beberapa hari setelah itu. Gue berusaha untuk menyampaikan kegelisahan gue soal ketakutan akan perubahan itu ke dia. Kalimat gue agak drama memang harap maklum namanya juga jebolan penonton Cinta Fitri 7 season.
“People change. You see it yourself, look at the people around you, they changed. I don’t want that change. I don’t need that change. I don't like change.”
Thinking back about what I said that day, I was so stupid, ya? Rasanya kok kayak... posesif banget? Sounds dramatic? Sounds depressive? Rasanya kayak orangtua yang mendengar keputusan anaknya buat mandiri dan nggak tinggal sama mereka lagi, lalu dia berat buat melepasnya.
Tapi gue jujur saat itu. Gue takut hubungan kami berubah. Gue takut kami jadi jauh. Gue takut kehilangan. Gue takut nggak punya teman.
Gue takut...
Tapi ketakutan itu nggak pernah gue sampaikan ke dia. Gue cuma bilang kalau gue takut perubahan dan itu gue rasa merangkum semuanya.
Kenapa sekarang gue menilai diri gue bodoh pada saat itu?
Karena gue masih dikuasai oleh sebuah ketakutan akan ketidakpastian. Gue bukan orang yang punya banyak teman, jujur aja, dan ketika gue sudah punya beberapa orang yang gue merasa nyaman, gue akan hold them tight and sometimes maybe too tight sehingga gue mulai merasa posesif. Rasa memiliki gue ini berlebihan sampai-sampai gue suka lupa kalau mereka juga punya teman lain selain gue. Dan ketika gue tidak ada di lingkaran pergaulan dia yang lain, gue merasa dikhianati, sakit, FOMO. Gue sedikit nyesel kenapa nggak dari dulu aja ya gue ke dokter. Kenapa baru-baru ini? KWKWKWKWKWWK Tapi ya hikmahnya mungkin adalah karena kedewasaan dan bertambahnya usia juga membuat pola pikir gue berubah.
Penilaian gue soal kebodohan itu tidak terjadi setelah gue minum obat kok. Sebenarnya terjadi jauh sebelumnya. Melihat ke belakang gue mulai sadar bahwa ketakutan-ketakutan gue itu nggak beralasan. Rasa posesif gue ke dia, dan ke semua teman-teman dekat gue, sama sekali tidak beralasan. Meski valid, perasaan-perasaan takut ditinggal sendiri dan sendirian itu sama sekali tidak baik untuk terus dipertahankan. Dan ketika gue sudah bisa mengidentifikasi kesalahan dan kebodohan gue, di situlah gue berusaha untuk berubah. Untuk mengubah pandangan dan cara berpikir gue tentang hal itu. Dan perubahan pola pikir itu nggak akan terjadi kalau gue nggak pernah punya teman sekamar, tbh.
Nggak semua perubahan itu buruk. Ada banyak perubahan yang baik juga. Ya beberapa di antaranya adalah beberapa kalimat terakhir gue di paragraf yang sebelumnya atau bagaimana gue menanggapi cerita hantu atau keberadaan tokek di belakang pintu. Tapi gue harus akui sampai sekarang gue masih merasa bahwa perubahan itu menakutkan. Bahkan setahun terakhir ini, ketika kondisi pandemi bikin segala hal bisa berubah dengan cepat (teman yang tadinya ada bisa jadi nggak ada untuk selamanya, keluarga ada yang meninggal karena COVID-19, kantor nggak lagi dibuka dan kerja harus dari kosan), pikiran-pikiran gue sangat sibuk dengan kekhawatiran akan penyesuaian diri yang harus dilakukan berkali-kali dan untuk banyak hal yang berbeda di saat yang sama.
Hari ini harus masuk kantor, besok harus WFH, minggu depan bisa WFH semingguan, lalu bulan depan bisa masuk kantor dua hari lalu WFH dua hari, bulan depannya lagi peraturannya bisa berubah lagi. Rasanya hal-hal ini terlalu melelahkan buat gue yang nggak pernah olahraga ini. Terlalu melelahkan buat kepala gue yang gak ada tekanan aja selalu merasa tertekan. Terlalu membuat gue kewalahan.
Gue nggak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang harus menyesuaikan diri dan beradaptasi setelah mereka merasa kehilangan orang yang mereka sayangi. Salah satu Bibi gue meninggal karena COVID-19 tapi jujur karena gue memang jarang ketemu sama dia, gue nggak terlalu merasakan kekosongan itu. Iya gue sedih dan merasakan grief tapi semuanya membaik dengan seketika. Tapi gue melihat nyokap gue sangat tegar dan kuat ditinggal adik bungsunya. Dia seperti nggak pernah merasa sedih? Dia sepertinya kuat-kuat aja? Apakah dia menyimpan kesedihannya dan pura-pura kuat? Tapi setiap kali gue tanya, dia selalu memberi jawaban yang bijak. Ya tipikal ibu-ibu gimana sih... Dia mungkin tidak dididik untuk terbuka soal perasaannya dan cenderung memendam, gue rasa.
Tapi gue yakin ada alasan di balik itu. Mungkin dia memang tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya merasa sedih juga dengan kesedihannya. Mungkin dia diam-diam menangis dan gue nggak tahu?
Di situlah gue kemudian kembali merasa takut. Meski ada beberapa perubahan yang bisa gue jalani dan terima untuk saat ini, akan ada satu perubahan yang mungkin akan sulit buat gue hadapi. Ketika perubahan itu datang, gue sudah harus siap dan berbesar hati.
Secara fisik gue mungkin masih lemah dan jadi agak sedikit buncit sekarang (meski ada juga orang-orang yang merasa gue kurusan? Padahal mah gue gini-gini aja nggak sih? Nggak ya? Ya gak tahu WKWKKWKWKW) tapi secara mental hopefully gue agak lebih stabil. Gue pun berubah kan? Gue sekarang jauh lebih kenal diri gue daripada sebelumnya. Gue tahu limit gue, kadar kesukaan gue, ketidaksukaan gue. Gue tidak lagi mau melakukan apa yang nggak suka gue lakukan, gue nggak lagi malu-malu bilang 'nggak', gue nggak lagi mendahulukan perasaan orang lain dan menyakiti diri gue sendiri dengan dalih “nggak enak ah sama dia”.
Ada kok perubahan-perubahan yang baik juga.
Karena kita manusia dan makhluk hidup, kita inevitably pasti berubah, dan (harusnya) nggak perlu takut soal itu (kan?). Sebesar apapun perubahan yang terjadi, kita pun sebenarnya sudah punya insting untuk menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap perubahan itu. Meski kita nggak menyadarinya, tapi kemampuan beradaptasi itu pelan-pelan sudah kita kuasai. Toh selama ini kita juga sudah dibiasakan untuk beradaptasi kan? Dari TK pindah ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah, dari kuliah ke kerja, dari kerja ke kerjaan yang lain, dan begitu seterusnya sampai (merasa) settled.
Semenakutkan apapun perubahan itu, dia pasti terjadi. Dan ketika perubahan itu terjadi, yakin deh, itu pasti buat yang terbaik. Mungkin nggak yang terbaik buat lo, tapi buat orang lain yang terlibat di dalamnya yang pada akhirnya itu juga akan mempengaruhi lo eventually, jadi ya ujung-ujungnya itu juga yang terbaik buat lo.
Gue nggak bisa bilang gue sudah nggak takut lagi pada perubahan tapi gue bisa bilang bahwa hari ini gue sudah siap dengan perubahan apapun yang akan terjadi tanpa perlu mengkhawatirkan skenario-skenario alternatif (yang sering kali buruk) yang muncul di kepala gue.
Ya mungkin besok gue akan berubah pikiran lagi.
Siapa yang tahu.









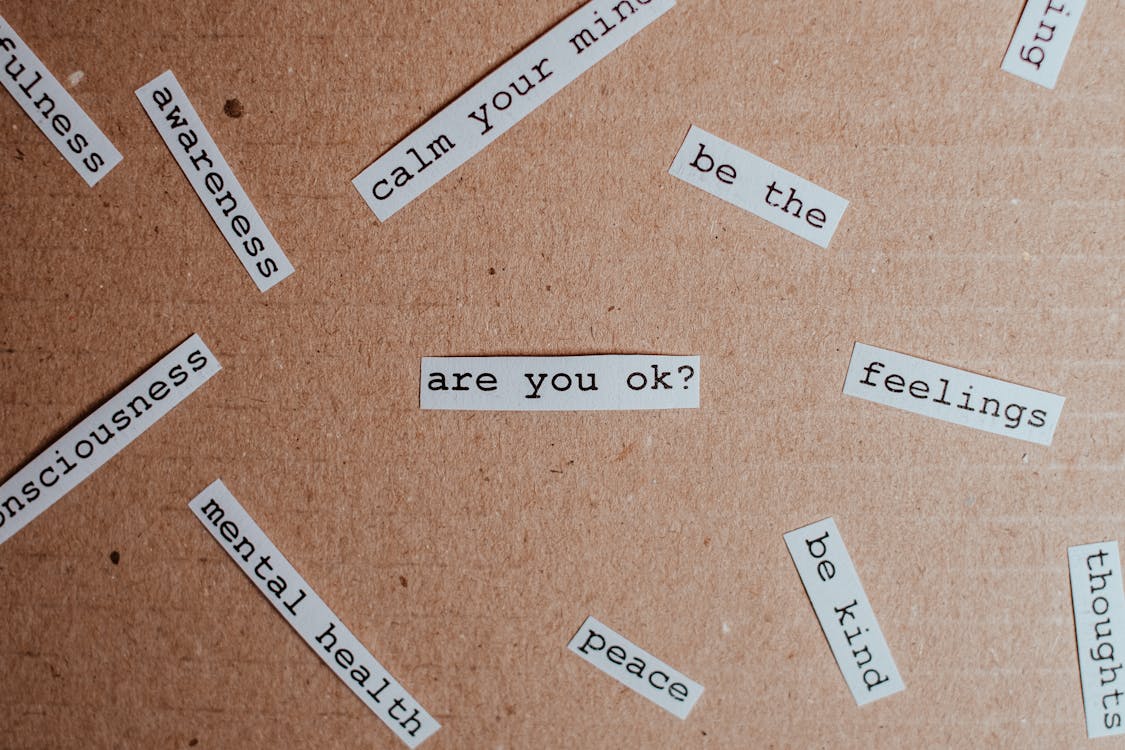









0 comments