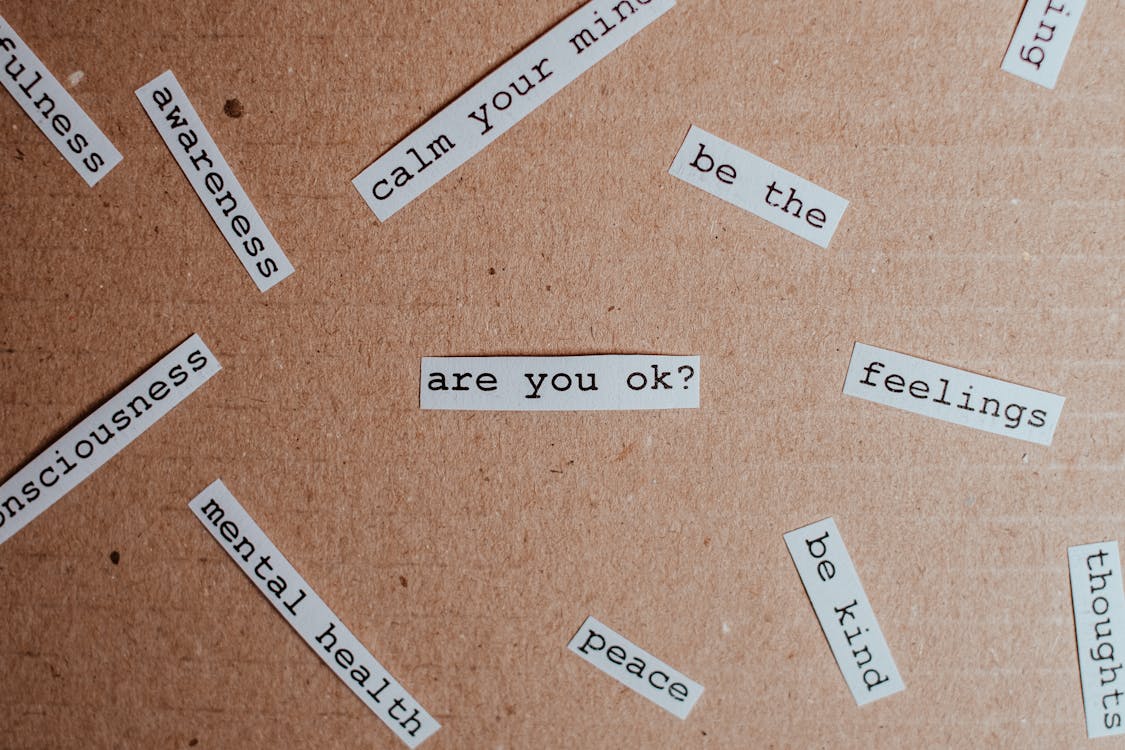Sekitar tahun 2014 atau 2015, ketika gue belum jadi pengendara motor di Jakarta, gue pernah pinjam motor teman gue untuk pergi ke daerah Blok M. Niatnya sore itu di sela-sela jam kerja yang nggak terlalu padat gue mau ke money changer. Kalau nggak salah inget waktu itu gue baru pulang dari liputan di Korea atau New York gitu deh dan ada sisa uang yang perlu gue tuker balik ke Rupiah. Karena gue sedang malas naik Metro Mini ke kawasan Blok M (ya, dulu masih ada Metro Mini) karena jurusan Blok M – Pasar Minggu – Blok M itu Metro Mini-nya luar biasa melelahkan kala itu (kalau nggak salah jalan layang buat TransJakarta dari Tendean ke... mana tuh, Tangsel? Belum jadi dan macetnya di situ minta ampun deh kalo di jam-jam sibuk) gue pun memutuskan untuk pinjem motor aja. Gue awam sama jalanan Jakarta di jalur pemotor kala itu karena memang selama ini selalu menggunakan angkutan umum. Tapi kurang lebih gue tahu jalannya karena sering naik angkutan umum.
Ketika gue pinjem motor itu gue nggak nanya motornya apa (atau sebenarnya gue nanya tapi gue nggak pernah ngeh brand dan bentukan tipe motor tertentu, yang gue tahu cuma Mio, atau Honda Beat, dan semacam itu. Brand di luar itu gue cuma bisa hah heh hoh doang), temen gue ngasih STNK dan gue pikir itu sudah cukup buat memberitahu gue motornya yang mana. Gue toh bisa lihat nomor kendaraannya di STNK dan mencari motor itu di parkiran. Permasalahannya adalah gue nggak pernah parkir motor di situ dan nggak tahu flow parkiran kantor kayak gimana. Maksud gue... kalo parkiran Mal kan udah jelas ya jalan masuknya di mana keluarnya di mana. Kalau di kantor gue waktu itu agak... berantakan.
Sesampainya gue di parkiran, gue agak bingung dan muter-muter selama lima sampai sepuluh menit nyari motor itu. Tapi gue nggak mau menyerah dan gue terus berusaha buat ngecek motor itu di posisi yang temen gue kasih tahu. Tetep aja motor itu nggak ketemu juga. Sampai akhirnya satpam yang nungguin parkiran nyamperin gue, dengan wajah dan nada bicara yang agak kesal.

Jauh sebelum pandemi, ketika gue masih tinggal di kosan yang udah gue tempati selama sekitar empat atau lima tahun di pinggiran Jakarta Selatan (yang sebenarnya nggak ideal-ideal banget buat ditempati tapi cukup membuat gue nyaman karena harganya murah banget), gue nggak pernah melewatkan waktu untuk cari tempat duduk sambil nulis. Gue mungkin udah beberapa kali nyebut soal bagaimana gue sangat suka nongkrong di McDonald’s Kemang dari malam sampai jelang subuh cuma buat nge-blog di sana. Walaupun gue nggak terlalu suka keramaian ketika sedang nulis karena terkadang tempat yang terlalu ramai bisa sangat membuyarkan imajinasi dan pikiran, tapi keramaian di tempat itu terbilang... inspiratif. Biasanya gue akan memutar musik di laptop atau handphone dan mendengarkan lewat headphone sambil nulis supaya gue nggak mendengar berisiknya orang-orang yang ada di sekitar, lalu bisa fokus ke hal yang ingin gue tulis. Tapi kadang-kadang gue pakai headphone tanpa memutar musik sama sekali jadi gue bisa tetap mendengarkan obrolan orang yang ada di meja sebelah gue sambil terus menulis. Kadang-kadang hal ini juga cukup banyak memberikan gue inspirasi. Mungkin nggak langsung bisa gue tulis hari itu, tapi bisa jadi di kemudian hari. Seperti hari ini misalnya.
Gue sedang menunggu Lola, Ayu dan suaminya, Awent, di suatu sore jelang buka puasa di sebuah hotel di Mataram. Kami hari ini berencana buat buka puasa bareng setelah beberapa tahun nggak ketemu dan melakukan ini. Sebenarnya ada dua orang lagi di geng ini tapi mereka berhalangan hadir jadilah kami hanya bertiga plus Awent sebagai penggembira. Mengatur sebuah acara buka puasa memang bukan perkara mudah, gue tahu. Tapi gue kira itu hanya terjadi buat orang-orang yang mengurus buka puasa buat 40 orang atau satu angkatan SMA atau kuliah. Tapi ternyata ngurus geng yang isinya lima orang ini aja ribet banget. Dan gue kira, dramanya sudah selesai sehabis dua orang tidak bisa datang dan hanya tiga orang yang konfirmasi. Ternyata sesampainya di lokasi, masih ada drama lain: meja kami nggak ada.