Being Denial
Jauh sebelum pandemi, ketika gue masih tinggal di kosan yang udah gue tempati selama sekitar empat atau lima tahun di pinggiran Jakarta Selatan (yang sebenarnya nggak ideal-ideal banget buat ditempati tapi cukup membuat gue nyaman karena harganya murah banget), gue nggak pernah melewatkan waktu untuk cari tempat duduk sambil nulis. Gue mungkin udah beberapa kali nyebut soal bagaimana gue sangat suka nongkrong di McDonald’s Kemang dari malam sampai jelang subuh cuma buat nge-blog di sana. Walaupun gue nggak terlalu suka keramaian ketika sedang nulis karena terkadang tempat yang terlalu ramai bisa sangat membuyarkan imajinasi dan pikiran, tapi keramaian di tempat itu terbilang... inspiratif. Biasanya gue akan memutar musik di laptop atau handphone dan mendengarkan lewat headphone sambil nulis supaya gue nggak mendengar berisiknya orang-orang yang ada di sekitar, lalu bisa fokus ke hal yang ingin gue tulis. Tapi kadang-kadang gue pakai headphone tanpa memutar musik sama sekali jadi gue bisa tetap mendengarkan obrolan orang yang ada di meja sebelah gue sambil terus menulis. Kadang-kadang hal ini juga cukup banyak memberikan gue inspirasi. Mungkin nggak langsung bisa gue tulis hari itu, tapi bisa jadi di kemudian hari. Seperti hari ini misalnya.
Gue sangat suka mendengarkan cerita orang lain. Tapi permasalahan terbesar gue (yang sekarang sedang berusaha gue atasi) adalah setiap kali mendengarkan cerita orang gue punya kecenderungan untuk memotong, mengomentari, dan berujung jadi menilai mereka. Sebagian orang mungkin cerita untuk meminta pendapat atau komentar, tapi sebagian lagi ada yang hanya ingin cerita tanpa perlu dikomentari. Jadi sekarang setiap kali ada orang yang ingin cerita ke gue atau memulai sebuah pembicaraan, gue akan selalu mengawalinya dengan “Apakah gue perlu komentar atau lo hanya ingin cerita dan mengeluarkan isi hati dan pikiran lo?” Dan gue hanya akan komentar kalau mereka membolehkan gue berkomentar. Kalau mereka nggak membolehkan, ya gue hanya akan memberi respons seadanya tanpa memberikan judgement berlebihan pada cerita itu.
Ketika duduk di tempat umum seperti kafe atau McDonald’s Kemang, lo akan mendengarkan berbagai macam cerita seru yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Lo akan semakin sadar bahwa permasalahan lo ternyata mungkin nggak jauh lebih besar atau rumit dari permasalahan orang lain, atau bahkan mungkin merasa lo nggak sendirian menghadapi permasalahan yang sedang lo hadapi sekarang karena ada orang lain juga yang sedang berusaha menghadapi urusan yang sama. Nguping mungkin sebuah kata yang konotasinya negatif tapi, well, mereka bicara di tempat umum dan gue nggak bisa nggak mendengarkan cerita mereka karena posisi meja kami yang bersebelahan. Tentu saja gue ada pilihan untuk menyumbat telinga gue dengan headphone (dan mereka ada pilihan untuk cari tempat yang lebih private misalnya) tapi rasa kepo gue terlalu berlebih dan kadang-kadang, meski gue sudah kurang-kurangin, gue tetap ingin tahu apa yang terjadi pada kehidupan orang juga. WKWKWKWK YA ALLAH MAAFIN AKU SUKA GHIBAH DAN MENCURI DENGAR.
Dalam semalam bisa ada dua atau tiga orang berbeda yang duduk bergantian di meja yang sama dan mereka datang dengan cerita berbeda. Suatu malam gue mendengarkan cerita seorang perempuan yang diselingkuhi pacarnya dan bingung bagaimana dia harus minta putus, di malam yang berbeda gue mendengar cerita dari mahasiswa yang sedang berusaha untuk mendapatkan surat rekomendasi dosen untuk melanjutkan pendidikan, di malam yang sama dari meja yang sama gue mendengarkan bagaimana orang ini berusaha move on dari pacarnya yang lama dan ingin memulai kehidupan yang baru.
Alih-alih merasa bahwa gue butuh memberikan judgement pada cerita mereka (meski mereka nggak cerita ke gue dan gue nggak ada urusan dengan kehidupan mereka anyway), gue merasa orang-orang ini sedang berusaha terbuka tentang diri mereka, masalah mereka, dan sedang berada dalam situasi yang sangat rentan. Pasti ada alasan kenapa mereka datang ke tempat ramai itu untuk menceritakan permasalahan mereka ke seseorang yang mereka percaya, tanpa harus takut ada orang lain yang menguping pembicaraan mereka dari meja lain. Menurut gue apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat berani. Nggak semua orang bisa sangat open dan being vulnerable, menjadi diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Butuh waktu lama untuk sampai di titik itu dan orang-orang ini mungkin sudah ada di sana. Itulah kenapa gue menyebut hal ini begitu menginspirasi.
Suatu hari gue memutuskan untuk cari tempat baru untuk nulis. Kali ini mood gue sedang nggak ingin berada di keramaian. Ada satu hotel di seputaran Thamrin, Jakarta Pusat, yang selalu gue lewati dan selalu menarik perhatian gue karena desain eksteriornya yang unik. Gue nggak tahu apakah makanan yang mereka sajikan di restoran terjangkau atau tidak (maafin tapi dulu masih kere, ya sekarang juga masih kere sih, tapi sekarang sudah lebih cukup daripada waktu itu) tapi gue pikir secangkir kopi di sini nggak mungkin lebih mahal dari Starbucks. Malam itu sekitar jam delapan malam gue sudah ada di sana, memesan satu gelas es kopi dan pasta (yang ternyata enak banget meski porsinya sedikit), gue membuka laptop di kursi pojok dekat colokan, lalu mulai memasang headphone tanpa memutar lagu sama sekali. Nggak lama setelah itu ada dua orang laki-laki datang dan duduk di meja sebelah gue.
Gue nggak datang untuk nguping, obviously, tapi gue nggak bisa menahan diri gue untuk tidak nguping (OBVIOUSLY).
Restoran di hotel itu nggak memutar musik sama sekali dan suasananya cukup tenang. Pencahayaannya juga kalem, malah terlalu gelap gue rasa. Tapi mungkin mood-nya emang cocok buat ketemuan dan cerita hal-hal personal. Konsentrasi gue benar-benar buyar karena dua orang ini. Gue yang tadinya berniat buat nulis jadi hanya meletakkan tangan di keyboard dan nggak mengetik apa-apa tapi malah jadi fokus mendengarkan obrolan mereka berdua.
Dari ujung mata kiri gue, gue bisa melihat sosok dua orang itu. Mereka berdua berperawakan sama-sama kecil, mungkin tingginya sepantaran gue. Dua-duanya pakai kaca mata. Gue lupa siapa yang datang lebih dulu yang pasti gue baru sadar ada orang di sebelah gue ketika dua kursinya sudah terisi dan mereka memulai obrolan dengan berjabatan tangan.
Mungkin itu adalah pertemuan pertama mereka?
Gue membatin.
Melihat mereka sangat akrab bahkan di (allegedly) pertemuan pertama bikin gue sedikit banyak iri. Iri karena gue bukan orang yang lihai dalam berkata-kata di pertemuan pertama. Gue jadi berandai-andai kalau gue yang ada di posisi mereka, mungkin gue nggak akan banyak bicara dan jadi orang yang hanya mendengarkan. Salah satu dari dua laki-laki itu memang lebih banyak diam dan mendengarkan sementara yang lain lebih jago bicara. Si jago bicara ini punya peran yang sangat penting buat mengarahkan pembicaraan dan bikin lawan bicaranya mau ngomong lebih banyak. Entah bagaimana dia berhasil dan akhirnya dua orang ini mulai ngobrol seru.
Gue sebisa mungkin berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan detail obrolan mereka malam itu, juga berusaha untuk tidak ketahuan nguping. Ketika gue sudah mulai merasa “terlalu ikut campur”, gue mengalihkan perhatian gue ke laptop dan mulai berusaha fokus menulis lagi. Dalam usaha gue untuk menyelesaikan paragraf yang sedang gue ketik itu, sialnya, obrolan seru mereka selalu berhasil mengalihkan perhatian gue.
Si jago ngobrol, gue sebut aja namanya Jacob, cerita bagaimana dia kenal dengan seorang cowok di Tinder dan cocok satu sama lain. Cocok dalam artian mereka nggak cuma nyambung dalam hal obrolan tapi juga dalam hal seks. Jujur aja gue malu banget mendengarkan pembicaraan ini tapi, anjirlah, gue kepo banget? Maafin gue. Obrolan Jacob bener-bener mencuri perhatian gue sampai-sampai jari gue yang tadinya menari di atas keyboard jadi mendadak diam. Mata gue melihat ke layar tapi pikiran, perhatian, dan telinga gue terbuka buat semua yang Jacob ceritakan.
“Banyak dramanya!” kata Jacob. “Gue sebenarnya suka sama dia tapi dia bohong sama gue. Dia bilang dia ada acara voluntary Asian Games, tapi tahunya itu cuma alasan dia karena dia ada naksir cowok lain di sana. Ya kan anjing?” lanjut dia.
Teman Jacob malam itu, kita sebut saja dia Keenan. Gue nggak bisa melihat ekspresinya dengan jelas ketika Jacob cerita karena posisi Keenan persis di samping gue. Keenan cukup aktif mendengarkan dan mengajukan pertanyaan ketika dia merasa ada bagian dari cerita itu yang dia tidak mengerti. Tapi mostly Keenan hanya mendengarkan perjalanan hubungan beberapa hari antara Jacob dengan si cowok volunteer Asian Games ini.
“Ya tapi dia berusaha minta maaf sama gue, dia ngaku bohong, dan kita baikan. Jadi malam itu dia datang ke kosan gue dan we’re having sex,” kata Jacob lagi.
Gue mulai gemeter karena lagi-lagi gue sudah mendengarkan terlalu banyak. Gue mau memulai menyalakan musik supaya gue nggak merasa bersalah lebih lanjut karena mendengarkan cerita yang tidak seharusnya gue dengar. Tapi asli, nggak kepo soal kehidupan orang lain itu emang susah, persis seperti apa yang gue tulis di posting-an sebelumnya. Gue mengalihkan perhatian gue sejenak dengan menyesap kopi dan pura-pura membereskan colokan di bawah meja. Cerita Jacob dan Keenan masih berlanjut.
“Jadi sebenarnya waktu kami dekat dan having fun together, kami belum resmi pacaran atau apa. Ya kami cuma pasangan yang kenal dari Tinder lalu senang-senang. Sebatas itu. Tapi gue merasa cocok aja sama dia dan we’re having a very passionate sex that night. And right before the climax, he said he loves me and asked me to be his boyfriend!” Jacob agak teriak di akhir. Gue nggak paham kenapa dia harus teriak karena tempat itu sangat sepi dan nggak perlu teriak juga gue rasa Keenan bisa mendengarkan dengan jelas.
“HAH?” itu adalah pertama kalinya gue mendengar Keenan komentar dengan suara keras. “Terus lo bilang apa?”
Apa yang Keenan katakan kayak persis seperti apa yang akan gue katakan kalo Jacob ceritanya ke gue.
“Yeah well, we’re having fun. Jadi nggak ada alasan buat gue untuk nolak, kan? But then he started to make me feel like shit right after I agreed to be his boyfriend. Kita jalan beberapa minggu sampai akhirnya banyak drama. Jadi gue putusin aja,” lanjut Jacob.
Sudut mata gue melihat ada pergerakan dari meja sebelah. Mungkin mereka mutusin buat makan makanan yang sudah dingin karena mereka terlalu asik cerita. Di situlah kemudian Jacob melempar pertanyaan ke Keenan soal kehidupan pribadi Keenan.
Jujur gue sebenarnya lebih ingin tahu kenapa mereka berdua bisa kenal dan duduk di meja sebelah gue malam ini daripada mendengarkan cerita Keenan soal kehidupan dia. Tapi setelah gue (ASLI MAAF YA KEENAN) nguping, gue malah jadi tertarik mendengar cerita Keenan lebih lanjut. Daripada cerita Jacob dan kehidupan seks bebas dia, cerita Keenan lebih membumi dan lebih memasyarakat menurut gue. In a way gue bisa relate dengan cerita dia meski nggak seratus persen sama.
“Jadi gue suka sama orang ini,” kata Keenan. Dia mengawali ceritanya dengan memilih untuk menggunakan kata ganti ‘orang ini’ alih-alih menyebutnya sebagai ‘cowok ini’ atau ‘cewek ini’. “Gue suka dia udah lama, udah empat atau lima tahun,” lanjut Keenan.
Kopi gue udah mau abis dan gue memutuskan untuk memesan kopi lagi supaya gue bisa mendengarkan cerita Keenan sambil ngemil. Gue juga memutuskan untuk memesan makanan lain karena pasta gue sudah habis. Di titik ini gue sama sekali nggak mengingkari bahwa gue ke situ sudah bukan lagi buat nulis, tapi buat nguping dan mendengarkan cerita Keenan soal kehidupan pribadi dia yang sebenarnya gue nggak berhak tahu. Gue bisa aja pergi dari situ dan membiarkan mereka berdua menikmati waktu curhat mereka tapi gue terlalu malas untuk beranjak, dan sudah terlalu tertarik untuk tahu lebih banyak.
Mungkin gue bisa dapat hikmah dari cerita ini, siapa yang tahu, kan?
“Gue sesuka itu sama orang ini sampai-sampai bahkan ketika gue nggak sedang memikirkan dia pun, dia seperti ada di kepala gue, ngerti kan? Even when I’m not trying to think about them, this person was always there in the back of my head! That’s so annoying, actually. Dalam fase gue suka sama dia sih mungkin ya nggak semenyebalkan itu karena kan gue lagi, ya bisa dibilang, mabuk asmara. Tapi ketika gue sudah mencoba untuk move on, dia masih ada di sana dan itu membuat gue sulit untuk ngelupain dia,” Keenan berhenti bicara buat menarik napas. Sebelum dia memulai bicara lagi, Jacob mengajukan sebuah pertanyaan.
“Kenapa lo mau ngelupain dia? Apakah lo suka dia lalu dia nggak suka lo, apakah dia menyakiti lo sampai akhirnya lo mau move on atau gimana?”
Di situlah kemudian Keenan mulai mengubah kata ganti subjek yang dia ceritakan dari ‘orang ini’ jadi ‘dia’.
Dari ‘this person’ ke ‘he/his/him’.
“He doesn’t liked me back! Ya sebenarnya sih nggak sesimpel itu. Agak rumit kalau mau dijelaskan dari awal tapi gue paham banget kalau dia sedang berusaha untuk figuring everything out, tapi gue merasa dia terlalu judgemental ke gue dan itu bikin gue merasa kayak gue orang paling jahat di muka bumi ini. Oke gue akui mungkin gue juga memberikan judgement ke dia soal seksualitas dia sebelum bahkan dia tahu dirinya sendiri, but the way he’s react to everything I did, makes me feel like he’s definitely not straight. Itu yang memberikan gue keyakinan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Untuk memberikan perhatian yang lebih. In a way, gue merasa dia menikmati perhatian itu. Gue pun merasa nggak masalah memberikan perhatian itu ke dia. But then when I tell him about how I feel towards him, he resents me,” berapi-apinya Keenan terasa banget sampai kursi sebelah. Gue jadi agak deg-degan mereka akan mulai curiga gue nguping. Gue memastikan headphone gue terpasang dengan baik.
“Like, how?” tanya Jacob.
“Dia bilang dia straight dan...” Keenan tertawa kecil. “...dia bilang gue ada di jalan yang salah dan dia mau membantu gue kembali ke jalan kebenaran!” kali ini Keenan benar-benar tertawa tapi ada suara yang aneh di tawanya itu. Kayak ada kebencian, kekesalan, dan segala emosi yang bercampur aduk.
Reaksi Jacob lebih epik lagi.
“THAT SON OF A BITCH!”
“I KNOW, RIGHT?!”
“THEN WHAT HAPPENED?!”
YA, TERUS GIMANA?!
Gue pengin juga teriak kayak gitu. Tapi untungnya mas-mas restoran datang mengantar pesanan gue dan perhatian gue teralih sejenak. Sekarang posisinya gue sudah membuka headphone, memindahkan laptop gue agak ke depan supaya piring makanan gue bisa lebih dekat, lalu mulai menikmati hidangan sambil membuka kuping lebar-lebar. Di situ gue udah bodo amat apakah mereka tahu gue nguping atau nggak karena kayaknya dari tadi mereka juga nggak peduli dengan volume suara mereka sendiri. Lagipula, tempat sepi kayak gini, semua orang pasti bisa mendengar cerita mereka, bahkan mungkin chef yang bertugas malam ini juga mendengar umpatan Jacob tadi dari dalam dapur.
“Jadi itu udah terjadi dua tahun lalu atau setahun lalu gue lupa. Nah sejak itu, gue sumpah demi Tuhan gue mau ngelupain dia banget tapi gue nggak bisa sama sekali. Gue memilih buat memutuskan kontak dari dia, block semua nomor dia, akun sosmed dia, dan bener-bener nggak mau berhubungan lagi. Gue pikir itu adalah salah satu cara supaya gue beneran bisa lupa?”
KEENAN! KOK KITA SAMA?!
“Tapi lalu mutual kami mulai merasa ada yang aneh dengan interaksi kami setiap kali ada di acara yang sama dan kumpul-kumpul sama teman gitu. Mutual kami merasa kami saling menghindar satu sama lain, which is true karena buat gue nggak ada lagi hal yang harus kami bahas gitu lho! Meski ya gue belom totally moved on, tapi gue rasa udahlah gue nggak perlu manjang-manjangin cerita ini. Tapi si mutual gue ini merasa gue keterlaluan, gue terlalu egois karena memutuskan hubungan gitu aja,”
NGGAK KOK, KEENAN! PADAHAL MAH YA UDAH KALO DIA BRENGSEK YA PUTUSIN AJA?!
“Akhirnya di satu sore, gue mutusin buat kirim pesan teks ke dia atas permintaan temen gue ini. Di situlah dia ngetik panjang lebar dan baru ngaku kalau dia nggak straight. Dia bilang dia bi tapi for fuck’s sake dia nggak bi sama sekali menurut gue itu cuma alesan supaya dia masih bisa dibilang suka sama cewek karena menurut gue dia totally gay!”
Jacob ketawa.
“He sounds like totally gay to me. That son of a bitch,” kata Jacob.
“Iya kan?! Maksud gue, oke, gue paham sekali lagi ketika gue confess ke dia, dia masih belum tahu jati dirinya. Tapi nggak usah sampai lo mau bawa gue ke jalan kebenaran seolah-olah gue ada di jalan yang menyimpang dan bentar lagi terjun ke neraka dan lo satu-satunya orang yang benar gitu lho? Kalo pada akhirnya lo juga ada di jalur yang sama dengan gue, kenapa lo malah membuat gue merasa sepertinya gue yang paling berdosa dan lo yang paling benar? Kayak gue nggak tahu ya masalah dia apa, tapi gue rasa selama ini dia denial-nya parah banget sampai-sampai dia merasa bahwa dia bisa lancang bilang gue menyimpang gitu lho! Oke, gue mungkin nggak kayak lo ya Jake, yang lebih berpengalaman. Tapi I can tell since Day-1, he’s not straight! Bisa-bisanya dia bilang dia mau membawa gue ke jalan yang lurus. Hello? Bitch? Seriously?”
“Ya memang paling nggak suka deh gue berurusan sama orang denial,” Jacob mengomentari sambil tertawa. “Menurut gue mereka tuh ras manusia paling ngeselin,” lanjut dia.
Kalo di sinetron, Jacob mengucapkan kalimat itu diakhiri dengan efek petir menyambar. Nyambarnya ke jantung gue langsung dan membuat gue terbakar sampai mati. Kalimat itu bener dan bener-bener nusuk.
Gue akhirnya sadar bahwa gue sudah terlalu jauh mendengarkan cerita Jacob dan Keenan yang seharusnya mungkin gue nggak tahu. Di momen itu, gue memutuskan untuk memasang headphone lagi dan kali ini memastikan musik yang gue putar membuat gue nggak bisa mendengarkan suara apapun dari luar.
Sementara itu kepala gue masih terus berusaha memproses semua yang sudah gue dengarkan tadi.
Apa yang dibilang Jacob itu bener banget. Berurusan sama orang yang denial tuh, kalau memang nggak urgent banget, mending gak usah deh. Kalau memang bisa menjauh, mending menjauh deh. Gue yakin, lo pasti pernah berurusan atau ketemu sama orang seperti ini. Atau mungkin sekarang lo juga sedang berada dalam fase itu dan dinilai menyebalkan oleh orang lain.
Pikiran gue melayang jauh banget dari restoran itu, jauh dari tombol keyboard laptop gue yang seharusnya gue pencet-pencetin dari awal alih-alih mendengarkan obrolan pribadi orang lain. Tapi kata-kata Jacob tadi beneran mengganggu pikiran gue banget. Beberapa hal yang Keenan omongin juga cukup membuat gue berkontemplasi.
Keenan sempat menyebut soal “orang ini nggak ingin gue pikirin pun seperti udah nempel di belakang kepala gue” dan saat itu, gue pun kurang lebih sedang merasakan hal yang sama. Dalam kasus gue, hal ini tentu saja berkaitan dengan gue yang basically orangnya ada kecenderungan overthinking dan terlalu berlebihan dalam menganalisa kejadian-kejadian atau interaksi yang sudah gue lakukan dengan orang lain. Terutama dalam kondisi sedang “gagal move on” atau “proses move on”, overthinking ini bisa membunuh. Mungkin nggak menghilangkan nyawa lo, tapi mengaburkan akal sehat lo dan membuat lo jadi berkutat dalam pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu.
Gue sudah tahu gue tipe orang yang gampang kepikiran entah karena kesalahan yang sudah gue buat atau sikap cuek gue ke orang yang tadi gue temui di depan toilet mal misalnya. Padahal mungkin orang itu juga nggak akan kepikiran sampai segitunya tapi gue bisa mikirin ini sampai besok pagi atau minggu depan dan terus merasa nggak enak karena itu. Anehnya, gue bisa bertahan cukup lama tanpa pertolongan. Kalau dipikir-pikir, overthinking gue inilah yang pada akhirnya membuat gue beralih ke tulisan-tulisan di blog ini. Ke teori-teori nggak penting soal K-Pop yang sebenarnya nggak perlu dipikirin tapi toh gue pikiran juga. Ke tulisan-tulisan galau yang gue yakin nggak semuanya nyaman dibaca orang lain. Pernah, memang, gue ada di fase di mana gue merasa bahwa semua yang gue pikirkan ini hanya selewat aja dan nggak perlu gue seriusin. Berhasil untuk sehari dua hari tapi kemudian hari ketiga terjadi lagi. Di situlah gue mulai merenung. Apakah selama ini gue sedang menyangkal sesuatu?
Gue kemudian berpikir, mungkin kadang-kadang gue memang denial soal kegalauan-kegalauan gue di masa-masa itu. Kelihatan semisal ada yang komentarin Instagram Story gue, gue bakal balas “NGGAK KOK!” padahal udah jelas-jelas gue galau.
Overthinking gue juga merembet ke perasaan-perasaan khawatir soal pandangan orang lain tentang gue. Hal itu bikin gue pada akhirnya mengkritisi diri dan perilaku gue secara berlebihan.
Sekarang gue baru sadar bahwa nggak ada gunanya mikirin hal itu dan nggak ada gunanya kita berusaha mengontrol pikiran orang tentang diri kita. Tapi dulu nggak ada orang yang memberitahu itu ke gue.
Sekarang gue akui kalau dulu gue memang sudah bersikap atau bertindak berlebihan soal itu.
Soal gue yang overthinking juga bukan sesuatu yang gue sangkal. Gue merasa ini sudah sepaket dengan kehidupan gue selama ini dan sesuatu yang belum bisa gue kesampingkan. Gue nggak tahu bagaimana pengalaman lo, tapi overthinking gue udah kayak parasit. Persis seperti yang Keenan bilang, overthinking ini kayak ada di belakang kepala gue dan akan selalu ikut serta dalam setiap pikiran-pikiran yang muncul belakangan. Mereka akan nempel di situ dan menghadirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu, ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal, membisikkan suara-suara yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang sedang gue pikirkan saat itu, membuat gue tidak fokus dengan apa yang seharusnya gue lakukan dan malah memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi saat itu.
Gue pernah cerita di Podcast Ronzikologi (yang sekarang sudah gue hapus), kalau gue sedang diam saja, otak gue selalu berisik. Selalu seperti ada suara-suara yang gue nggak tahu apa dan siapa. Selalu seperti ada keributan. Selalu seperti tidak pernah tenang dan nggak pernah kalem. Sekali dua kali mungkin hal ini nggak apa-apa dan gue masih bisa menahannya. Tapi ketika semuanya terjadi di saat yang sama, menyerang bersamaan, gue jadi overwhelming dengan perasaan dan pikiran yang tidak benar-benar terjadi, sampai akhirnya gue jadi berdebar, panik, dan bisa-bisa nangis karena bingung harus ngapain.
Gue mengakui semua itu dan tidak sedikitpun gue menyangkalnya. Tapi anehnya, kenapa gue bisa bertahan selama ini? Sampai kapan otak dan tubuh gue akan kuat menahan semuanya? Apakah selama ini gue sebenarnya butuh pertolongan tetapi gue nggak benar-benar yakin?
Nggak ada yang pernah menjelaskan ke gue bahwa emosi dan perasaan manusia adalah dua hal yang sangat kompleks, sampai akhirnya gue mengerti sendiri dan merasakan emosi-emosi berbeda dan perasaan-perasaan berbeda sepanjang perjalanan hidup gue selama 31 tahun ini. Dari situ kemudian gue berpikir, kalau aja dari dulu setiap perasaan yang muncul gue tanggapi dengan baik tanpa harus bertindak terlalu keras terhadap diri gue sendiri, dalam artian gue nggak terus berusaha mengabaikan perasaan-perasaannya dengan menganggap perasaan itu tidak ada, mungkin semuanya nggak akan menumpuk jadi sesuatu yang pada akhirnya menuntut untuk ditanggapi dan diselesaikan. Kalau aja dari dulu perasaan dan emosi itu tidak gue hadapi dengan penyangkalan...
Tentu saja kita nggak ingin merasakan sakit hati atau kesedihan yang berlebihan. Tapi dalam hidup, suatu saat sakit hati dan kesedihan yang berlebihan pasti akan datang juga. Dulu perasaan sakit hati gue sering gue pendam dan simpan, kesedihan berlebihan yang gue rasakan seringkali gue tutupi dengan cari pelarian. Gue pikir itu akan membuat gue lebih baik dan membuat perasaan sakit hati dan kesedihannya menguap begitu saja. Padahal sebenarnya itu hanya menahannya buat sesaat dan kalau ada trigger yang tepat, perasaan itu akan datang lagi bahkan mungkin jadi dua kali lipat ditambah dengan trigger yang muncul belakangan itu. Gue sadar kalau gue terus melakukan hal itu gue akan capek sendiri.
Kalimat Jacob soal “orang denial” itu cukup menjadi tamparan buat gue supaya gue nggak lagi mengabaikan emosi dan perasaan yang sedang gue alami dan rasakan. Kalau memang sedang sedih, yaudah bersedih saja tanpa dilebih-lebihkan atau dikuat-kuatkan. Kalau sedang patah hati, ya lo juga berhak untuk menggelar pity party for yourself and figuring out how to make yourself better after this.
But in my case, sometimes that doesn’t help.
Jadi gue mengumpulkan keberanian dan niat buat akhirnya pergi ke psikiater.
“Saya butuh pertolongan.”
Itu jadi kalimat pertama gue ke dokter gue yang sekarang.
Yang Jacob bilang soal orang denial itu benar. Tapi sebesar itu ketidakinginan gue untuk bertemu dan berurusan dengan orang denial, gue pun pada akhirnya harus berkaca bahwa mungkin selama ini gue yang denial. Sebelum gue pada akhirnya bisa menghindari orang lain dengan permasalahan penyangkalan itu, ada baiknya gue menyelesaikan penyangkalan-penyangkalan yang gue rasakan dulu.
Yang jelas ada satu hal yang gue nggak bisa sangkal saat ini: gue sedang suka banget ELEVEN by IVE.









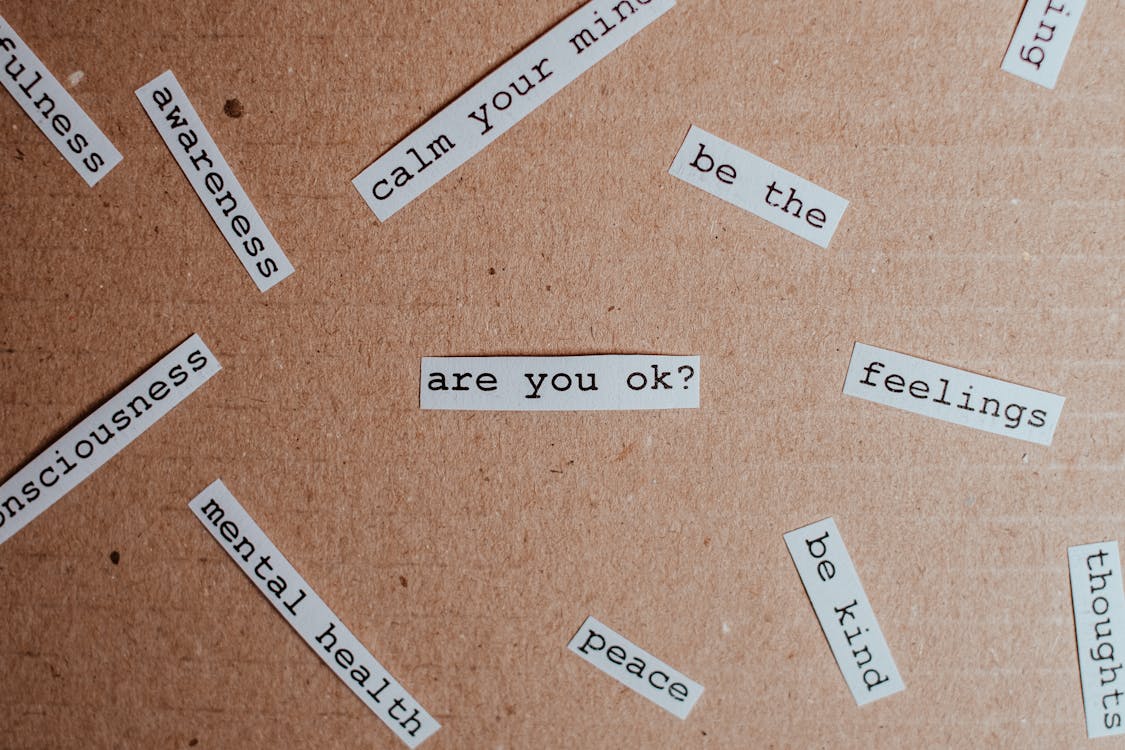









0 comments