Butuh Pertolongan
Sekitar tahun 2014 atau 2015, ketika gue belum jadi pengendara motor di Jakarta, gue pernah pinjam motor teman gue untuk pergi ke daerah Blok M. Niatnya sore itu di sela-sela jam kerja yang nggak terlalu padat gue mau ke money changer. Kalau nggak salah inget waktu itu gue baru pulang dari liputan di Korea atau New York gitu deh dan ada sisa uang yang perlu gue tuker balik ke Rupiah. Karena gue sedang malas naik Metro Mini ke kawasan Blok M (ya, dulu masih ada Metro Mini) karena jurusan Blok M – Pasar Minggu – Blok M itu Metro Mini-nya luar biasa melelahkan kala itu (kalau nggak salah jalan layang buat TransJakarta dari Tendean ke... mana tuh, Tangsel? Belum jadi dan macetnya di situ minta ampun deh kalo di jam-jam sibuk) gue pun memutuskan untuk pinjem motor aja. Gue awam sama jalanan Jakarta di jalur pemotor kala itu karena memang selama ini selalu menggunakan angkutan umum. Tapi kurang lebih gue tahu jalannya karena sering naik angkutan umum.
Ketika gue pinjem motor itu gue nggak nanya motornya apa (atau sebenarnya gue nanya tapi gue nggak pernah ngeh brand dan bentukan tipe motor tertentu, yang gue tahu cuma Mio, atau Honda Beat, dan semacam itu. Brand di luar itu gue cuma bisa hah heh hoh doang), temen gue ngasih STNK dan gue pikir itu sudah cukup buat memberitahu gue motornya yang mana. Gue toh bisa lihat nomor kendaraannya di STNK dan mencari motor itu di parkiran. Permasalahannya adalah gue nggak pernah parkir motor di situ dan nggak tahu flow parkiran kantor kayak gimana. Maksud gue... kalo parkiran Mal kan udah jelas ya jalan masuknya di mana keluarnya di mana. Kalau di kantor gue waktu itu agak... berantakan.
Sesampainya gue di parkiran, gue agak bingung dan muter-muter selama lima sampai sepuluh menit nyari motor itu. Tapi gue nggak mau menyerah dan gue terus berusaha buat ngecek motor itu di posisi yang temen gue kasih tahu. Tetep aja motor itu nggak ketemu juga. Sampai akhirnya satpam yang nungguin parkiran nyamperin gue, dengan wajah dan nada bicara yang agak kesal.
“Ini,” gue kasih lihat STNK-nya.
Satpam itu langsung jalan menuju motor temen gue yang ternyata beneran ada di tempat gue muter-muter dari tadi cuma gue nggak lihat aja.
“Di situ tuh ada orang yang nungguin tempat parkir,” dia me-refer ke dirinya sendiri. “Jangan dianggap patung! Tanya aja!” kata dia dengan nada agak tinggi.
Gue, meski sudah dibantu buat nemuin motor itu, merasa agak tersinggung dengan nada bicara dan cara dia menyampaikan kalimat itu.
“Ya saya kan cuma nggak mau ngerepotin. Apa salahnya saya usaha dulu buat cari sendiri?” gue balas aja kayak gitu.
Agak dongkol gue cabut dari sana dan sukses kembali lagi ke sana. Untungnya gue nggak ketemu lagi sama dia pas gue udah balik.
Jujur aja pada saat itu gue kesal sama satpam itu. Kalau memang dia mau bantu, kenapa dia nggak menawarkan bantuan dengan baik-baik? Kenapa dia harus pakai nada tinggi dan mengakhiri bantuan itu dengan nyinyirin tindakan gue? Gue nggak habis pikir. Kalau memang dia niat baik, kenapa harus ada “ujungnya” gitu lho. Kenapa nggak yaudah niat baik aja nggak usah pake “Makanya kalau...”.
Tapi ketika gue duduk dan menulis blogpost ini lalu mengingat kejadian itu lagi, gue baru sadar kalo gue sekarang menanggapi hal itu dengan berbeda. Melihat lagi ke belakang, gue jadi berusaha menempatkan diri gue di posisi satpam itu. Ketika dia ada di sana, DIA ADA DI SANA, tapi orang nggak consider buat minta pertolongan dia, wajar aja dia merasa terluka. Saat itu gue tidak mempertimbangkan hal itu sama sekali dan sibuk dengan keterburu-buruan gue, kepanikan gue karena susah menemukan sepeda motor itu, dan keinginan gue untuk “jadi mandiri” dan bisa menemukan benda itu sendirian tanpa bantuan orang lain. Di situ gue sadar bahwa ketika gue bilang “saya nggak mau ngerepotin” justru menjadi beban. Karena kalau gue nanya dan minta tolong dia buat cari, itu bukan ngerepotin. Itu bagian dari pekerjaan dia.
Di usia remaja awal sampai remaja akhir, seinget gue, gue memang tipe orang yang selalu bisa melakukan semuanya sendiri. Kadang-kadang memang enak kalau orang lain melakukan sesuatu buat kita dalam konteks tertentu. Tapi kalau hal itu bisa dilakukan sendiri, gue akan senang hati melakukannya. Gue belajar naik motor pas kelas 6 SD kalau nggak salah dan ketika gue SMP gue udah bisa bawa motor sendiri dan mulai curi-curi pakai motor nyokap. Beberapa kali nabrakin sampai mecahin spion dan gue selalu berusaha mencari solusinya sendirian. Gue akan diam-diam ke bengkel buat beli spion baru tanpa nyokap tahu.
Pas SMP, gue pernah secara sukarela mengajukan diri untuk bikin kue ulang tahun buat perayaan Hari Guru. Anak-anak di kelas ngeluarin duit, gue yang belanja dan bikin kuenya.
Pas SMA, waktu sedang ngurusin pendaftaran buat PPKB (semacem PMDK jalur undangan gitu kalo sekarang?) UI, gue sama sekali nggak bilang ke orang tua gue soal itu dan gue pakai duit bulanan untuk urus form, fotokopi ijazah, sampai bikin pas foto. Bahkan pas fotonya pun gue nggak pergi ke studio foto tapi motret sendiri pake kamera digital. Karena gue nggak punya baju kemeja yang bagus, akhirnya gue Photoshop kepala gue ke badan Daniel Radcliffe yang pake kemeja warna ungu waktu promosi Goblet of Fire. WKWKWKKWWK INI SERIUS TAPI GUE NGGAK BOHONG. Meski kayaknya badannya jadi kayak kegedean dan kepala gue jadi aneh proporsinya, tapi kayaknya foto itu yang bikin gue keterima di UI. LMAO. INI UNIVERSITAS INDONESIA APA CASTING PENONTON BAYARAN DAHSYAT?!
Waktu kuliah, secara sukarela juga gue menawarkan diri buat jadi editor untuk tugas Produksi Video di kelas. Meski basic, tapi itu cukup membantu di awal-awal kuliah kami karena kurikulum pada saat itu agak random. Produksi Video-nya mengharuskan editing sementara mata kuliah editing-nya baru diajarin dua atau tiga semester setelahnya. WWKWKWKKWKW. Untuk yang satu ini kayaknya emang gue bakat sih, tapi nggak gue lanjutin karena pengalaman ini agak traumatis.
Ada banyak hal yang gue prefer lakukan sendiri dan sebisa mungkin tidak bergantung pada orang lain. Sampai ketika gue masuk ke usia 20-an, ke kejadian di tempat parkir itu, pola pikir gue soal ini kemudian banyak berubah. Nggak instan sih memang, tapi banyak sekali hal-hal yang gue temui dari kejadian-kejadian sehari-hari yang semakin meyakinkan gue bahwa nggak semua hal harus dilakukan sendiri. Bahwa nggak semua hal harus ditanggung sendiri. Bahwa nggak apa-apa kalau misalnya kita minta tolong ke orang lain. Bahwa sah-sah aja kalau kita merasa tidak berdaya dan kemudian bergantung sejenak pada orang lain untuk satu masalah tertentu. Di situ gue mulai sadar bahwa minta tolong juga adalah bagian dari usaha.
Ada beberapa orang yang gue kenal akan langsung minta tolong sejak awal bahkan sebelum mereka mulai tanpa repot-repot untuk mencoba, karena mereka tahu mereka nggak akan bisa melakukan itu sendiri.
Ada juga sebagian yang lain yang harus mencoba dulu melakukan semuanya sendiri sebelum akhirnya menyerah dan minta tolong orang lain sebagai bagian dari usaha mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.
Gue pribadi mungkin butuh sekitar empat atau lima tahun untuk benar-benar sadar dan punya pemikiran untuk mau minta bantuan kalau udah mentok. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang gue pun merasa enggan buat merepotkan orang-orang tertentu. Lebih-lebih orang yang gue kenal cuma lewat satu atau dua kali obrolan lepas di Instagram misalnya. Beda kasus kalau orang ini adalah teman dekat. Atau mungkin nggak dekat, tapi statusnya teman. Biasanya kalau mereka memang orangnya baik, mereka nggak akan keberatan untuk direpotin. Dan kalau mereka memang sedang nggak mau repot, kalau mereka orang baik, mereka akan menjelaskan juga alasan kenapa mereka menolak untuk membantu.
Saat ini gue bisa bilang gue beruntung karena gue punya beberapa teman yang mau dan dengan senang hati meluangkan waktu hanya untuk mendengarkan keluhan gue soal... orang yang gue taksir, misalnya. Tapi menjadi terbuka ke mereka dan menceritakan apa yang sedang gue alami dan gue rasakan juga bukan hal yang instan. Butuh rasa percaya dan keyakinan bahwa apa yang akan lo ceritakan ke mereka nggak akan didengar oleh orang lain, atau sekadar rasa percaya dan keyakinan bahwa setelah ini mereka nggak akan memberikan judgement ke lo tentang apapun yang lo ceritakan itu. Gue yakin kalau gue membuka obrolan ke mereka soal sesuatu, kalau gue menceritakan tentang sesuatu, atau semisal gue sedang ingin minta saran mengenai sesuatu, orang-orang ini akan mendengarkan dan dengan senang hati memberi masukan. Tapi terkadang sisi “gue yang di tempat parkir” itu suka muncul dengan sendirinya dan bilang ke gue “temen-temen lo juga pasti punya masalah yang lain juga jadi mungkin lo nggak perlu menghubungi mereka untuk masalah ini?”
Di satu sisi gue setuju dengan itu. Tapi di sisi lain gue merasa itu sangat judgemental dan nggak adil.
Lo nggak bisa menyimpulkan bahwa mereka juga sedang disibukkan dengan memikirkan masalah lain dan nggak mau direpotkan dengan masalah lo sebelum lo benar-benar reach out ke mereka dan mencoba untuk bicara. Kecuali ketika lo sudah mulai bicara dan mereka tidak menunjukkan itikad baik dengan merespons sekenanya atau bahkan nggak respons sama sekali, baru lo bisa ambil kesimpulan “oh mereka sibuk” atau parah-parahnya “oh mereka nggak peduli”.
Kenapa gue bilang nggak adil? Karena kalau lo menganggap mereka teman (dan perasaan ini mutual) tapi lo nggak consider untuk sharing cerita lo ke mereka, itu akan membuat mereka tersakiti. Lo mungkin nggak begitu. Lo mungkin nggak apa-apa kalo mereka tidak memilih untuk cerita ke lo. Tapi mereka mungkin nggak kayak lo dan mereka mungkin lebih appreciate kalau lo cerita ke mereka.
Ya tentu saja mereka juga punya masalah sendiri-sendiri, tapi bukan berarti masalah itu menghalangi mereka untuk meluangkan waktu untuk membantu lo. Again, kalau mereka memang nggak punya waktu, mereka pasti akan bilang dengan baik-baik. Apalagi kalau hubungan kalian selama ini selalu baik.
Tapi ketika “gue yang di tempat parkir” ini sedang menguasai emosi gue, biasanya gue akan beralih ke metode-metode self-help kayak journaling, atau dulu bikin podcast pribadi. Menulis sangat membantu gue untuk mengurai benang kusut di kepala gue, meski nggak selalu menemukan solusi untuk permasalahannya, tapi paling nggak gue bisa mengidentifikasi apa yang harus dan perlu dilakukan dan mana yang nggak penting buat dipikirkan. Tapi meski metode ini sangat membantu, kadang-kadang gue kewalahan juga. Ketika terlalu banyak perasaan yang muncul dan menyerang lalu berkecamuk dan campur aduk, lo jadi bingung sendiri. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya pasti gue down.
Gue bukan orang yang malu-malu buat nangis dan kalau gue lagi mood untuk ngeluarin air mata ya gue akan nangis. Biasanya pas lagi naik motor dari kantor menuju kosan tuh gue suka nangis soalnya nggak berasa karena air matanya ketiup angin WKWKKWKWKWKW.
Cuma setahun terakhir gue merasa hal ini terlalu sering terjadi dan gue terlalu sering merasa overwhelmed with feelings and emotions. Kepala gue dipenuhi dengan suara-suara yang gue nggak tahu datang dari mana. Random. Loncat-loncat. Topiknya berubah-ubah dan nggak pernah fokus. Journaling nggak lagi selalu bisa membantu. Cerita ke orang terasa semakin membebani. Menangis rasanya seperti buang-buang waktu dan udah sering dilakukan sehingga perasaan leganya jadi hampa. Seringkali gue nguat-nguatin diri dan bilang ke diri gue sendiri kalau gue pasti bisa melewati semuanya dengan baik-baik saja. “Gue bisa kok melewati ini! Gue biasa kok melakukan ini sendiri!” Tapi pada akhirnya kalimat itu jadi meaningless. Setiap kali gue mengatakannya dan meyakinkan diri gue sendiri, entah kenapa rasanya semakin nggak yakin.
Gue pernah kena panic attack di salah satu perjalanan pulang dari kantor (dan itu karena Delta—gue pernah cerita soal orang ini di posting-an terdahulu), lalu hampir kena panic attack lagi karena orang yang sama ketika gue datang ke sebuah acara di bulan Desember 2021. Di situ kemudian gue meyakinkan diri gue bahwa gue nggak bisa lagi menghadapi ini sendirian. Gue butuh bantuan. Kali ini bukan cuma dengan self-help atau cerita ke teman, tapi gue butuh bantuan profesional. Januari 2022 akhirnya gue memutuskan untuk ke psikiater.
Dan ini adalah keputusan terbaik yang pernah gue ambil sepanjang pandemi COVID-19 selain pindah kosan dan beli PlayStation 4.
“Saya butuh pertolongan.”
Itu kalimat pertama gue ketika gue duduk di depan dokter. Sepanjang pekan sebelum kunjungan itu, gue sudah menyusun kalimat-kalimat yang akan gue keluarkan, gue udah menyusun skenario cerita yang ingin gue sampaikan. Tapi pada akhirnya semua yang gue rencanakan nggak keluar sama sekali dari mulut gue. Gue malah menceritakan hal lain yang nggak ada dalam naskah yang sudah gue susun selama seminggu terakhir. Tapi yang keluar dari mulut gue hari itu adalah hal yang paling tepat gue rasa dan hal yang sudah lama ingin gue katakan, ceritakan, cari solusinya. Hal yang paling menyakiti gue dan defining my whole life sampai akhirnya gue duduk di kursi konsultasi pagi itu.
Hari itu juga pertama kalinya gue mengkonsumsi obat anti-depresan. Percaya atau nggak, hari itu juga pertama kalinya gue merasa suara-suara di kepala gue udah nggak ada lagi. Rasanya tenang sekali.
Tenang banget.
TENANG BANGET.
Butuh beberapa hari untuk bisa terbiasa dengan kondisi ini. Terbiasa dengan tidak adanya suara-suara yang berisik itu. Terbiasa dengan ketenangan pikiran dan bisa fokus. Yang lucu dari ketenangan ini adalah semua perasaan yang datang bisa lo rasakan seutuhnya tanpa distraksi. In my case, gue jadi bucin. Oke, mungkin ini bukan penggambaran yang pas tapi ada fase di mana gue merasa buciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin banget sama orang ini dan gue bisa geregetan banget karena dia.
Tapi kalau mau lebih serius, ya perasaan-perasaan yang lumrah kayak kecewa dan marah juga akan tetap bisa lo rasakan hanya saja dalam intensitas yang terkontrol. Ketika lo kecewa lo jadi nggak nge-drag diri lo lebih jauh lagi sampai jatuh sejatuh-jatuhnya, ketika lo marah lo jadi bisa menyalurkan emosi lo dengan lebih tepat (kalau gue misalnya dengan tidak lagi terlalu marah-marah di Twitter misalnya; meski kadang-kadang masih sih tapi itu dilakukan dengan sadar dan bijaksana dalam versi gue). Hal yang paling berasa sebenarnya adalah ketika lo berhadapan dengan sesuatu yang selama ini triggering, lo jadi nggak kewalahan dengan perasaan-perasaan yang berkecamuk. Lo bisa lebih tenang dan menghadapinya tanpa meledak-ledak.
Tenang.
Tenang banget.
TENANG BANGET.
Semua kejadian di akhir usia belasan gue, sepanjang usia 20-an, dan di awal usia 30 ini membuat gue sadar bahwa nggak selamanya semua bisa dikerjakan sendiri karena suatu saat kita pasti butuh orang lain. Gue mungkin bisa survive dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari tanpa bantuan orang lain, tapi toh untuk bisa menyelesaikan semua itu gue butuh bantuan dokter.
It’s okay to feel weak because sometimes we cannot help it.
It’s okay to seek help, it’s not gonna make you look weak, on the contrary, that is a sign of strength because you fight for yourself.









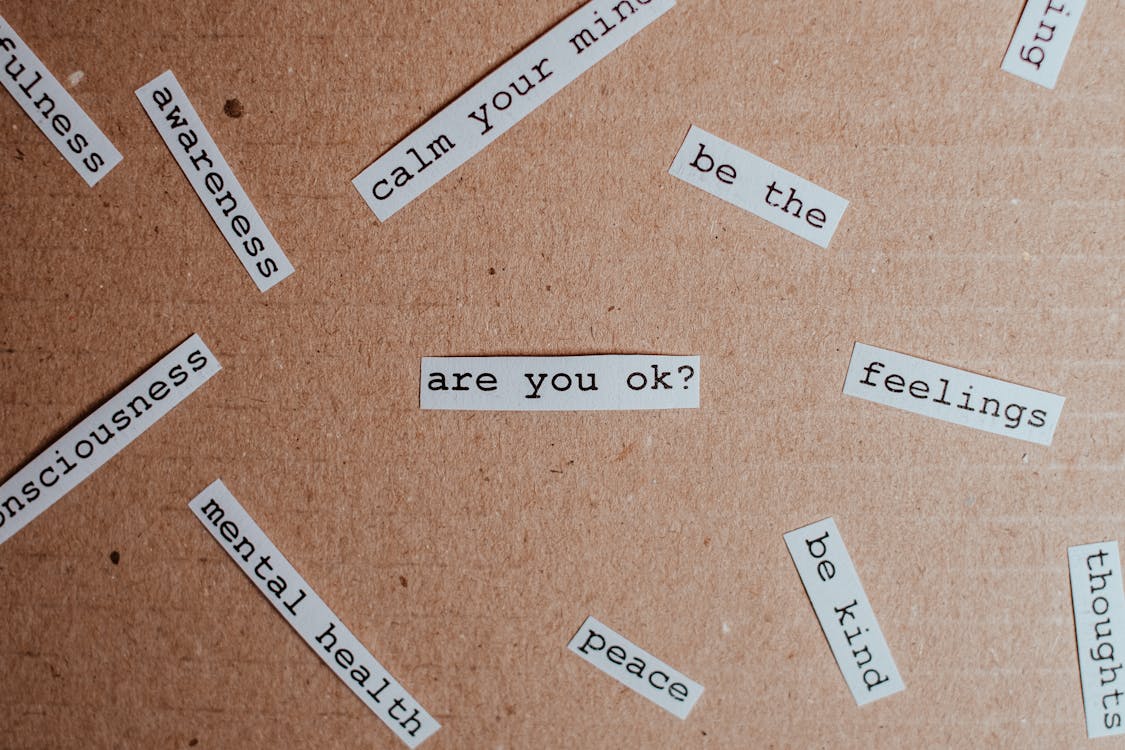









0 comments