Menjadi Dewasa yang Sebenarnya
Kalimat di atas sebenarnya bukan gue tulis untuk merepresentasikan perasaan atau kondisi gue saat ini. Tulisan itu datang dan terinspirasi dari pengalaman pribadi crush gue (subjek atau orang lain yang terlibat dalam cerita ini) yang ketika ketemu gue, dia sedang dalam masa-masa susah move on dari past relationship-nya. Ketika pertama kali gue ketemu dia, wajah ramah dan ceria itu tidak terlihat seperti sedang menyimpan beban orang dewasa yang teramat rumit. Sebagai orang dewasa, dia jago menembunyikannya. Sementara gue, nggak lama sebelum kenal, chat, dan ketemu sama dia, gue juga menghadapi pahitnya putus cinta. Anehnya buat gue, rasa pahitnya nggak lama-lama. Dari sisi gue, mungkin itu adalah salah satu sikap sebagai orang dewasa yang paling dewasa yang bisa gue lakukan.
Tapi gue dan dia adalah dua orang dewasa yang berbeda, ada di situasi berbeda, dan bereaksi terhadap sesuatu dengan cara yang berbeda juga. Satu-satunya hal yang klop di antara kita pada akhirnya adalah sama-sama bersikap dewasa dan berbesar hati untuk mengakhiri hubungan ini.
Jujur ketika gue mengawali tulisan ini, gue nggak pernah mengkhususkan tema besarnya sebagai 'adulting'. Tapi setelah gue sampai di paragraf terakhir, gue sadar bahwa semua yang gue tulis itu (terlebih dalam konteks usia gue menulisnya) adalah aksi dan reaksi, serta cerminan (ANJIR PPKN BANGET BAHASA GUE) dari sebuah kedewasaan.
Ya... adulting nggak cuma soal bayar tagihan yang datangnya selalu di tanggal yang sama. Nggak melulu soal mikirin gimana caranya supaya bulan depan internet gue tetap nyala supaya kewarasan gue tetap terjaga; walaupun pada akhirnya gue cuma menggunakan internet itu untuk melihat social media yang berujung bikin ngebanding-bandingin diri dengan orang lain dan akhirnya malah membuat tidak waras. Menjadi dewasa nggak selalu tentang menghitung pengeluaran bulan ini agar semuanya tetap dalam keteraturan, kecukupan, dan nggak merepotkan orang dewasa lain yang ada di lingkaran lo karena mereka juga sibuk ngurusin permasalahan adulting mereka masing-masing.
Ada kalanya adulting juga soal menghadapi perasaan yang paling enggan dirasakan. Menghadapi kenyataan yang sebisa mungkin nggak jadi pilihan.
***
Gue udah di Johor Bahru, Malaysia, ketika gue menulis bagian postingan ini dan ini adalah hari pertama puasa. Gue sempat teraweh di salah satu masjid di dekat hotel gue semalam (yang nggak deket-deket banget sebenernya) dan lega rasanya akhirnya bisa memulai Ramadan 2024 dengan sepantasnya, meski mungkin emang nggak maksimal. Sebelumnya gue agak takut nggak akan bisa mulai puasa di hari pertama Ramadan karena perjalanan ini. Gue nggak tahu sama sekali kalau plan solo traveling gue bakal bentrok sama hari pertama puasa. Tapi ternyata perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah sama Pemerintah bisa jadi blessing in disguise juga. Pemerintah di Singapura dan Malaysia, seperti pemerintah Indonesia, memutuskan 1 Ramadan di tanggal 12 Maret. Means, gue totally aman karena dalam jadwal gue, 11 Maret itu gue udah ada di Johor Bahru dan tinggal nunggu buat balik ke Jakarta (nginep semalem).
Low key sebenarnya perjalanan ini juga gue lakukan untuk berdialog dengan diri gue sendiri atas hal-hal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Di postingan yang sebelumnya gue udah sempat membahas ini. Soal pesan yang tinggal gue copy-paste itu.
Pesan itu akhirnya gue kirim.
Pesan itu gue tulis di pesawat dari Jakarta menuju KL, yang gue niatkan memang akan gue kirim setelah gue mendarat nanti. Dengan harapan, setelah pesan itu sampai ke orangnya, kita berdua bisa sama-sama beranjak dari sebuah hubungan yang nggak jelas ini. Terutama gue sih, karena kayaknya di antara dia dan gue, yang banyak bapernya adalah gue. Gue meromantisasi momen perjalanan ini dan momen mengirim pesan itu dengan "pas nanti keluar dari Indonesia sebentar, langsung kirim, langsung lepaskan".
Tapi akhirnya rencana itu tertunda sampai beberapa hari.
Sejujurnya dalam beberapa hari gue away from home, gue nggak mikirin dia sama sekali. Well, nggak sepenuhnya jujur sih itu, tapi nggak yang dalam artian spiralling thoughts gitu. Tetep kepikiran, tapi yaudah nggak dalam tahap yang mengganggu. Gue seneng dan bersyukur karena pada akhirnya gue bisa menikmati perjalanan gue dengan maksimal, menikmati konsernya dengan maksimal, menikmati kesasarnya dengan maksimal juga. Udah lama banget gue nggak bergumul dengan diri sendiri dan bermonolog buat sekadar menentukan arah atau sekarang mau makan apa. Gue kangen diri gue yang ini.
Pesan itu gue lupakan sampai akhirnya gue tiba di Johor Baru, bangun sahur, dan lihat ada satu notifikasi di WhatsApp.
Dari dia.
Sebelum pesan panjang yang dia kirim subuh hari itu, ada beberapa pesan sebelumnya yang gue cuekin karena nyebelin (HAHAHAHAH). Dan ketika gue baca pesan panjang itu, perut gue rasanya kayak dibolak-balik tanpa berhenti. Isinya persis sama dengan apa yang gue tulis (PLIS GUE NGGAK MAU MEROMANTISASI APA PUN TAPI KOK BISA?!): perpisahan dan melepaskan.
Harusnya gue lega.
Gue bilang gitu ke diri gue sendiri.
Harusnya gue lega. Karena pada akhirnya dia mengakui kalau selama ini dia udah menggiring gue ke perasaan-perasaan yang salah.
Harusnya gue lega. Karena pada akhirnya dia yang memulai duluan untuk say goodbye, bukan gue (meski gue bisa tapi gue gak mau). Meski gue ingin banget beranjak, tapi hati gue udah tertambat dan kalau orang itu nggak memulai, rasanya gue nggak akan punya hati untuk pergi.
Tapi entah kenapa kelegaan itu diliputi oleh perasaan lain. Sesuatu yang campur aduk antara nggak mau kehilangan, sedih, bingung, kecewa, takut, rindu, aku harus apa, ya Allah lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk, dan laper dan butuh kopi.
Gue baca chat dia berkali-kali dan... (dalam hati ngebatin, dia ada waktu nulis sepanjang itu berarti dia bener-bener mikirin gue ya? MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH GAK INI NGAREP AJA. INGET RON DIA NGGAK SUKA SAMA LO).
Yah, harus gue akui, di luar cangkang nyebelin itu, dia adalah orang baik. Decent. Dia dibesarkan dengan kasih sayang yang pada akhirnya tercermin dalam setiap kalimatnya. Dia bukan tipe orang yang kaya dari lahir yang kadang sulit untuk relate dengan hal-hal kecil. Dia adalah gue, sosok orang dewasa yang tumbuh besar dalam kecukupan dan itu saja sudah cukup.
Kata-kata yang dia pilih benar-benar hati-hati dan berbesar hati. Dalam arti... dia sebenarnya tahu keberadaan dia somehow membebani gue dan bikin gue terpuruk, tapi selama ini dia nggak tahu harus berbuat apa. Gue juga sih yang salah karena gue dari awal terlalu gragas, jujur. Ketika dia mulai menjauh, gue yang akhirnya menarik dia lebih dekat. Dan sekarang dia merasa itu udah nggak baik-baik saja, jadi dia memilih untuk mundur.
Dan isi pesan yang gue ketik beberapa hari lalu itu pun demikian. Gue terbuka ke dia bahwa selama ini gue bingung dan harusnya gue nggak terjebak dalam kebingungan itu, melainkan segera melangkah dan beranjak. Tapi gue, si hopeless romantic ini, nggak bisa dengan mudah melakukan itu tapi malah menyakiti dirinya sendiri.
"Gue harus beranjak dari hubungan yang aneh ini."
Itu salah satu isi chat gue ke dia.
"Tolong tetap jadi humble seperti sekarang."
Itu salah satu isi chat dia ke gue.
"Kita pasti akan ketemu lagi, entah gimana caranya, karena circle ini kecil. Semoga ketika saat itu datang, gue sudah baik-baik saja."
Itu isi chat gue yang lain ke dia.
"Gue mungkin nggak akan secara fisik ada di situ ketika lo mencapai mimpi lo, tapi I'm rooting and pray for you."
Itu isi chat dia yang lain ke gue. Bagian itu juga yang bikin perut gue rasanya kayak dikoyak-koyak siluman di Exhuma.
Di tengah hubungan antara dia dan gue yang kami sama-sama tahu aneh, tapi kita juga sama-sama nggak berani mengambil keputusan itu, gue dan dia akhirnya bisa (mengambil keputusan untuk) melangkah menjauh dari satu sama lain. I don't know about what you think guys, but this is the most adult thing yang pernah gue lakukan tahun ini.
You did great Ron.
Dan kamu juga, you did great. You know who you are.
Ketika dia memberi tanda hati di chat gue, seolah mau mengisyaratkan kalau dia sudah baca, tiba-tiba perasaan gue jadi kosong dan hilang.
Ini kelegaan dari merelakan, melepaskan, dan beranjak yang gue tunggu-tunggu selama ini. Selama hubungan yang singkat ini. Akhirnya perasaan itu datang, lalu pergi begitu saja.
Akhirnya gue bisa melepaskan.
Akhirnya gue bisa merelakan.
Semoga gue akan bisa segera beranjak seratuspersen.
"Gue nggak nyesel ketemu sama lo. I thank you."
Kata gue.
"Gue banyak belajar dari lo."
Kata dia.
"Tapi gue harus beranjak."
Kata gue.
"Dan memang ini udah saatnya kita untuk memutuskan buat nggak saling bicara lagi, walau rasanya itu udah harusnya kita lakukan berminggu-minggu lalu."
Kata dia.
"Good luck always."
Kata gue.
"Jangan lagi minta maaf atas hal-hal yang bukan salah lo."
Kata dia.
"Selamat puasa."
Kata gue.
"Selamat puasa."
Jawab dia.
***
Gue menggenggam tangan sendiri, berusaha untuk menguatkan diri sendiri dalam perjalanan ke Bandara Senai, Johor Bahru. Gue sedang ada di bus menuju airport ketika pikiran gue terbang jauh ke ranah hikmah dari pertemuan dua orang dewasa yang berakhir tidak jadi apa-apa ini. UNTUK APA KITA DIPERTEMUKAN LALU DEKAT TAPI TIDAK JADI APA-APA?! *begitu teriak sisi drama di kepala gue sebelah kiri agak ke kanan dikit*
Gue males sebenarnya untuk terus decoding dan decoding karena bisa melelahkan dan bikin jengah. Tapi kadung pikiran gue udah melayang jauh, gue kemudian bertanya dalam hati: kalau semua pertemuan di dunia ini ada maksudnya, lalu apa maksud dari pertemuan gue dan dia?
Apakah memang gue hanya jadi tempat singgah sementara untuk dia yang saat itu lagi ada di posisi terpuruk dalam hidupnya? Bisa jadi.
Ataukah sebaliknya? Dia adalah tempat persinggahan gue sementara gue menemukan jalan yang sebenarnya menuju orang yang akan jadi end-game gue?
Ini juga masuk akal.
Nggak bisa bohong kalau gue banyak belajar dari pertemuan ini, juga dari orang itu secara personal. Tapi ada sudut di hati gue yang rasanya nggak terima kalau pertemuan kita hikmahnya cuma buat jadi pelajaran satu sama lain.
Tapi bukankah semua hal dalam hidup begitu?
Gue berusaha untuk bisa melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang baik soal pertemuan/perpisahan ini. Soal awal dan akhir dari hubungan ini. Kabar baiknya adalah, kita sebagai dua orang dewasa bisa memulai hubungan ini dengan baik-baik, dan mengakhirinya dengan baik-baik juga.
Chat terakhir antara kita itu, menurut hemat saya ya kak, membuktikan bahwa kita adalah dua orang yang cukup mature, yang paham bahwa nge-ghosting dan di-ghosting itu adalah dua hal yang sama-sama nggak menyenangkan. Instead of melakukan itu, kita bisa mengucapkan selamat tinggal dengan cara masing-masing dan sesuai tempo masing-masing.
"Sebenarnya gue lebih suka ngomong ini langsung, tapi gue takut gue akan break down and cry. So, let me just do this in the most comfortable way: write it," begitu awal chat gue.
Meski berat, tapi pada akhirnya gue harus menerima ini sebagai akhir dari perjalanan kita. Tentu saja itu nggak berarti perjalanan masing-masing juga akan berakhir di sini. Gue dan dia sudah sampai di ujung jalan yang berbeda, yang masing-masing ujungnya punya pintu dengan warna yang berbeda juga. Di balik pintu itu, akan ada banyak hal yang menunggu. Baik dia atau gue, nggak tahu apa yang akan menyambut kami di sana. Jalan ini adalah akhir, tapi pintu itu merupakan awal.
Gue harus jujur kalau gue nggak siap menyambut awal yang baru ini, atau menutup lembaran cerita gue dan dia. Tapi gue nggak punya pilihan.
"Punya. Semua orang punya pilihan, Ron!" kata dia ke gue di pertemuan terakhir kita.
"Nggak. Nggak semua orang. Gue? Gue merasa nggak ada pilihan lain selain... ya... well," gue terbata-bata karena dia benar.
"Ya kan?"
Sial dia emang bener.
"Ya. Lo bener. Gue punya pilihan dan gue memilih untuk terus ketemu sama lo," gue nggak lihat ekspresinya saat gue bilang begitu karena gue jalan di depan dia beberapa langkah lebih cepat.
Gue berusaha untuk bilang ke diri gue sendiri: kalau gue nggak bisa melepaskan, gue akan sangat kewalahan menghadapi apa pun yang nanti akan datang. Gue nggak akan bisa sepenuhnya memulai awal yang baru sebelum benar-benar mengakhiri kisah yang lama. Tuhan baik banget sama gue karena kali ini gue diberi kesempatan untuk belajar menutup cerita ini dengan baik-baik, mengakhiri halaman buku hariannya dengan titik tanpa cliff-hanger, atau halaman yang terpaksa gue sobek. Harusnya gue cukup puas dengan itu. Nggak, harusnya gue puas dan merasa itu cukup.
Di sini kemudian gue menyadari bahwa sebagai orang dewasa pun, mengakhiri atau memulai sesuatu itu masih saja terasa sulit. Walaupun kalau dipikir-pikir ini bukan kali pertama gue mengawali dan mengakhiri sebuah hubungan, tapi gue nggak pernah terbiasa dengan proses itu. Terlebih lagi karena gue terlalu banyak melibatkan perasaan di dalamnya. Tapi sebagai orang dewasa, lagi-lagi semua harus dihadapi meski hati terluka dan rasanya ingin menangis. Ya nangis juga nggak apa-apa sebenarnya, orang dewasa pun kan manusia.
Selama beberapa waktu ke depan mungkin gue akan merasa kesepian dan rindu pada komunikasi yang pernah gue dan dia lakukan. Kata dokter gue, yang perlu gue lakukan adalah merasakan semua perasaan yang muncul tanpa perlu berusaha menghindarinya. Kalau rindu, ya gue akan menikmati kerinduan itu. Memang sebaiknya seperti itu kan? Sampai nanti perasaanny akan pergi juga.
Yang pasti akhir dari cerita ini pun harus gue syukuri. Dengan begitu gue bisa lebih siap dan lebih percaya diri buat menyambut cerita baru di babak hidup gue yang selanjutnya. Kalau pun nantinya jadi drama, ya gue cuma bisa berharap dramanya menarik jadi gue bisa tulis lagi buat chapter selanjutnya dari proyek buku ini.
Gue Ron, tahun ini gue akan memasuki usia 33, dan gue masih terus struggling demi hidup (dan kisah cinta) yang lebih baik.
***








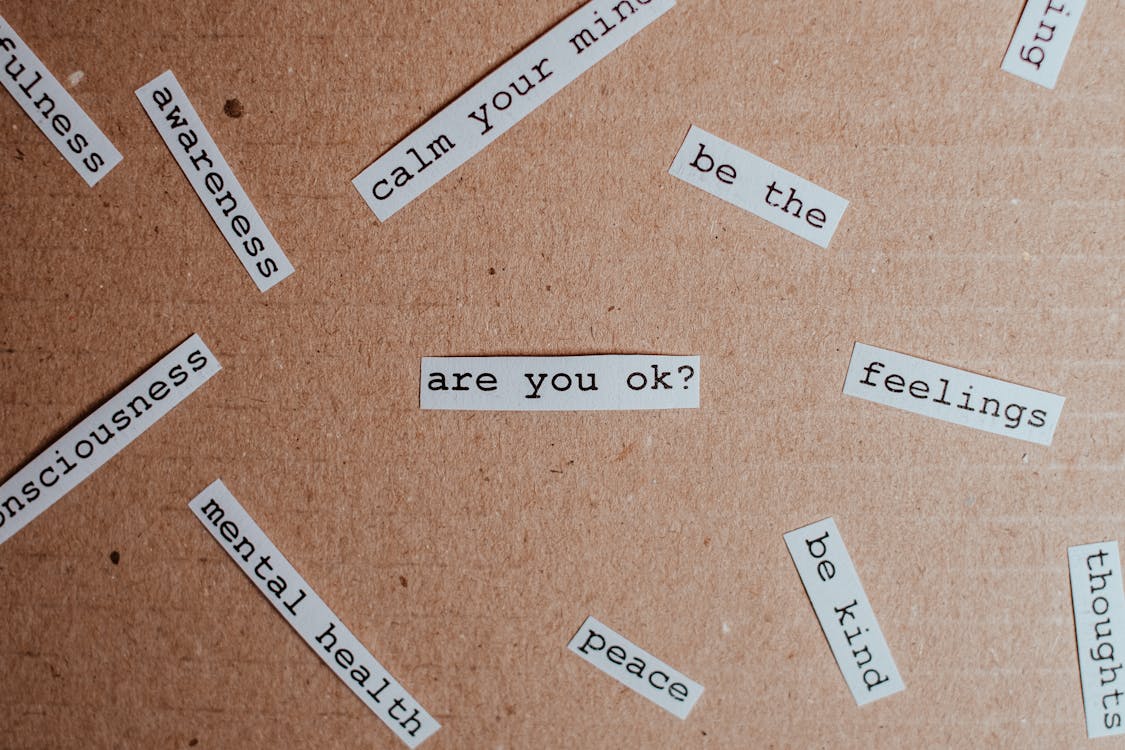









0 comments