Insecure, Insecurity, Insecurities
“Sori, tadi kesasar makanya lama. Sebel banget padahal cuma dari Blok M doang ke sini tuh kayak tinggal belok kanan. Tapi maps-nya kok jadi kayak muter-muter!”
Nggak ada kesan kesal dalam keluhan gue itu. Lebih ke malu sebenarnya. Gue baru beberapa hari naik motor di Jakarta dan sedang senang mengeksplor tujuan-tujuan baru selain kosan ke kantor dan kantor ke kosan. Makanya ketika temen gue, sebut saja namanya Dewa, ngajak gue ke Masjid Agung Al Azhar untuk menghadiri sebuah kajian di suatu hari Rabu beberapa waktu lalu langsung gue iyakan. Bukan hanya karena gue pengen sekali-sekali berkendara dari kantor ke tempat lain untuk memperluas wawasan gue soal jalanan Jakarta, tapi juga karena gue tertarik dengan pembahasan kajiannya hari itu. Dan kebetulan gue butuh ke Blok M untuk beli bubble wrap untuk kirim hadiah giveaway sekaligus mampir ke Gramedia buat beli buku titipan temen. Wah banyak ya alasannya. Dan ketika kita berdua mutusin buat keluar dari masjid di akhir acara lalu melipir untuk makan nasi goreng di pinggiran kampus Al Azhar, gue langsung cerita pengalaman gue naik motor ke daerah ini untuk pertama kalinya.
Sebenarnya acara kajian di masjidnya belum selesai ketika kami keluar. Karena Dewa bilang dia kelaperan, jadi gue juga nggak enak kalau harus menunggu sampai acaranya kelar. Beruntung kita sedang ada di areal kampus jadi pasti ada makanan sampai malam juga. Tadinya gue pengen ngajakin Dewa ngopi-ngopi di daerah Kemang. Karena dia tinggal di sekitaran Cilandak sana dan searah jalan pulang jadi biar sekalian gitu. Tapi rupanya rencana itu gagal karena kita keasyikan ngobrol di meja abang nasi goreng.
“Iya sama, aku juga tadi kesasar. Terus muter-muter karena takut kena ganjil-genap,” jawab Dewa.
“Lho kamu sekarang bawa mobil?” gue agak shock sedikit. Nggak banyak teman sepergaulan gue yang ke mana-mana bawa mobil. Kebanyakan dari kami adalah fakir Gojek dan Uber.
“Nggak mobil. Motor,” kata Dewa.
Ingin rasanya mukul meja keras-keras.
“MANA ADA MOTOR KENA GANJIL-GENAP!” kata gue agak kenceng. “KESEL!”
Gue kenal Dewa dari temen gue. Kita pertama kali ketemu bulan Agustus lalu walaupun gue sendiri sudah sering mendengar nama Dewa dari lingkaran permainan gue yang adalah teman-teman sekolahnya Dewa dulu. Kita sama-sama suka Kpop (obviously; karena selain itu kayaknya gue jarang ketemu orang baru lagi. Apalagi temenan karena kita sama-sama main futsal bareng. Gue main futsal aja nggak bisa. Paling banter main bola ya bekel) dan sama-sama suka SNSD. Mendengar cerita teman-teman tentang Dewa dan ketemu dengan orangnya langsung sangat beda banget. Dewa aslinya sangat pemalu. SANGAT PEMALU. Sampai-sampai gue gemes sendiri. Dan menurut dia, dia sendiri bukan tipe orang yang terbuka soal kehidupannya. Apalagi ke orang-orang baru. Dari beberapa pertemuan gue dengan Dewa, kesan pemalu itu memang ada.
Satu hal lagi soal Dewa: he’s supercool. Cenderung dingin. Yang. Kalau lo cerita sesuatu yang heboh dia akan diem aja. Flat.
Ekspresi flat itu juga yang muncul ketika gue teriak soal ganjil-genap itu.
“Aku kira motor juga lho?”
Gue menghela napas.
“Bodo amat Wa.”
Friendly reminder, gue biasanya ngomong Aku/Saya ke orang yang baru gue kenal. Di rumah sejak kecil sampai SMA, gue biasa berkomunikasi dengan Saya-Kamu. Baru ketika di Jakarta gue menggunakan Gue-Lo supaya kayak orang-orang. Tapi ke beberapa orang, beberapa yang dekat dan beberapa yang memang terlalu jarang gue temui, gue lebih suka menggunakan Aku-Kamu.
“Ngomong-ngomong sejak kapan bawa motor? Bukannya kemaren terakhir kita ketemu masih naik TransJakarta?” tanya gue.
“Ih. Nggak liat Insta-Story aku sih!” kata Dewa yang bikin gue langsung melotot yang bermakna ‘halo!!! Memangnya gue harus banget melihat semua update-an Instagram manusia di dunia ini?’. “Oh iya, kak Ron nggak follow Instagram aku sih ya,” katanya dengan nada sedikit mengejek.
Gue sudah mendengar sindiran seperti itu dari puluhan orang. Dari mereka yang dekat sama gue sampai mereka yang baru ketemu gue dua hari yang lalu dan memaksa minta di-follow. It’s ok. Memang kenyataannya begitu. Gue memang tidak mem-follow banyak orang di Instagram. Sorry not sorry. Gue punya alasan untuk itu. Go on and judge me.
Dan buat Dewa, gue tahu jawaban yang paling pas untuk sindiran itu.
“Kalau mau di-follow, update dulu posting-an Instagram-nya. Nih lihat,” gue nunjukin foto terakhir yang dia upload ke akunnya. “Masa update-an terakhir bulan April? Ngapain aku follow kalau nggak pernah nge-post? Malu sama akun kucing populer di Instagram, Wa!”
Dewa tertawa dan malu. Tapi itu memang kenyataannya.
“Kenapa sih nggak pernah update foto? Selfie atau apa gitu? Kan sering jalan, makan, nongkrong. Masa nggak ada yang bisa di-upload ke IG?”
Oke, gue merasa sudah terlalu jauh dan saat gue mengajukan pertanyaan itu gue merasa sangat bersalah. Ya suka-suka Dewa deh, Ron, mau nggak update Instagram berapa bulan. Bukan urusan lo juga buat tahu alasannya kenapa. Nggak usah sok deket (karena pada kenyataannya kita nggak deket-deket banget).
Gue nggak berharap dapat jawaban dari Dewa. Tapi dia menjawabnya juga.
“Aku malu, kak.”
Dan jawaban itu seperti tonjokan keras ke ulu hati gue.
Kalau boleh jujur, Dewa lebih punya tampang yang Instagram-able dibanding gue. Gue merasa sangat hina ketika mendengar pernyataan Dewa itu. Gue yang tampangnya superbiasa kayak gini aja nggak punya malu buat nampilin foto sendiri ke Instagram. Because, hey, that’s my account. Why can’t I post my own picture in my own account? Pernyataan Dewa itu bikin gue kepo banget. Kok bisa ada orang good looking malu mem-posting fotonya sendiri?
“Kenapa malu deh, Wa? I don’t see anything wrong lho. Secara tampang kamu jauh lebih enak dilihat dibanding aku, and that's obvious,” tanya gue. Perut gue mulai kruyukan karena nasi gorengnya belum juga datang.
“Malu aja kalau dikomentarin sama temen-temenku. Aku itu orangnya bener-bener pemalu. Jalan di depan orang banyak aku nggak berani, walaupun itu di deket rumah misalnya. Aku pernah nih ya, jalan di gang deket rumah terus lagi ada orang-orang ngumpul gitu, suka dipanggilin. Suka disiul-siulin. Orang-orang kalau ngeliat aku kayaknya ada aja yang bikin mereka komentar. Ngejelekin. Kayak misalnya pas aku cukur kumis kemarin, aku dipanggil ‘Neng’ sama tetangga. Kan kesel. Makanya jadi suka malu gitu kalau mau pajang-pajang foto di medsos. Malu aja sama komentarnya.”
Again, that hit me so hard. Because hey, I know how it feels. I’ve been there before.
“Bahkan aku mau ganti profile picture aja mikir-mikir dulu tahu, kak. Saking malunya.”
Gue menghela napas. WHAT IS WRONG WITH THOSE PEOPLE?!
Gue nggak punya banyak teman cowok waktu kecil. Kalau ditanya kenapa, jawabannya sederhana aja, gue nggak bisa main bola. Anak laki-laki di SD kan kalau nggak berantem ya main bola. Sementara gue nggak suka berantem dan nggak suka main bola. Jagonya nangis sama hapalin dialog telenovela. Masa-masa SD gue dihabiskan dengan membaca majalah Bobo dan Aku Anak Soleh. Komik Doraemon, Dragon Ball, Sailor Moon, sampai akhirnya gue masuk ke dunia Harry Potter pas kelas empat SD. I’m not into sports. And that’s the beginning of every humiliating moment in my life.
Gue tinggal dan dibesarkan di lingkungan orang-orang yang kalau lo melakukan hal yang berbeda dari apa yang kebanyakan orang lakukan, maka lo akan diberi label. Entah positif, entah negatif. Ketika gue jadi satu-satunya orang yang pakai kaca mata di SD, orang-orang memberi label “mata empat” atau “profesor” atau membuat gestur jari tangan menirukan bentuk kaca mata dan dengan jempol dan telunjuk lalu meletakkannya di depan mata. Ketika tinggi badan gue nggak seperti anak laki-laki kebanyakan, orang-orang memberi label “kocet” (yang secara harfiah dalam slang Bahasa Sasak berarti kecil tapi terkadang juga berarti pendek) atau “cebol”. Ketika gue nggak punya banyak teman laki-laki dan kebanyakan yang main sama gue adalah teman-teman perempuan, orang-orang memberi label ... ah ... yang satu ini agak mengungkit luka lama. But you got the idea, right?
Bagus kalau misalnya ada orang yang nggak terlalu mikirin perkataan orang dan nganggep itu sebagai sebuah lelucon yang yah besok juga akan dilupain. Tapi bagaimana kalau parahnya justru itu malah jadi sesuatu yang buruk yang bikin mereka malah melihat diri mereka seperti apa yang orang lain katakan? Karena, hey, ada lho orang yang benar-benar mempermasalahkan ini dan memikirkannya sampai pusing. Sampai stres. Ada orang yang sampai nggak berani keluar rumah untuk bergaul hanya karena dia takut orang-orang akan memanggilnya dengan nama-nama itu. Dan gue adalah salah satunya. Itulah kenapa gue berharap cepat-cepat lulus SD waktu itu dan pindah ke SMP. Berharap semua akan beda dan gue akan memasuki sebuah dunia yang baru.
But you know what, that new world didn’t really happened. I faced the exact same shit again in middle-school. They got even more label for me.
Dalam masa-masa puber, gue mulai mengalami perubahan suara. I was that boy with sonorous voice when in elementary school. Sebagai gambaran, gue bisa nyanyi ‘Laksmana Raja di Laut’ dengan nada tinggi yang tinggi banget itu atau niruin nada tinggi lagu-lagu Krisdayanti. FCK. HAHAHAHAHANJERRRRRRR. But then puberty strike and my voice become so weird in middle-school. Karena ketika suara gue pecah, pitch-nya nggak berubah jadi berat banget. Tapi nanggung. Jadinya kalau ngomong terdengar seperti apa yang orang-orang sebut dengan cempreng (walaupun gue rasa ini sebutannya agak gak pas sih). I don’t know how and why but some of these b*st*r*s keep saying that my voice sounds like a girl.
Dude. THAT’S MY PUBERTY, WHAT’S YOUR F***** PROBLEM?!
I wish I could say that back then but I can’t.
Gue cuma anak cupu yang bahkan kalau gerak sedikit aja pasti deh ada orang yang ngatain. Persis seperti apa yang Dewa bilang di ceritanya. Pasti deh ada orang yang ngejek. Pasti deh salah di mata anak-anak SMP yang paling gaul sejagat raya Kota Mataram ini. I don’t even know why was I applied to that school back then. Is it because “Oh! I want to be in this popular school!”? Shit. Besok-besok gue nggak akan encourage orang-orang untuk masuk ke sekolah favorit. Mending masuk ke sekolah yang biasa-biasa aja tapi manusia-manusiaya beradab daripada masuk sekolah favorit tapi jadi bahan caci maki.
#drama
Things became more complicated in high school. Tapi gue terbilang beruntung karena ketika SMA, gue bisa membalas semua label yang orang-orang (mostly mereka yang badung sih dan yaelah, kalau dipikir-pikir, lo dulu pas SMA tuh bisanya apa sih selain bikin rusuh; yagitu jadi suuzon dan sok gini kedengerannya) berikan dengan—sesuatu yang yah bisa dibilang—prestasi. Obviously I was smarter than them and more talented in some ways. FCK. THIS SOUNDS WRONG. HAHAHAHA BUT I WAS A SMART STUDENT BACK THEN!
Di situlah gue mendapat kepercayaan diri lebih untuk nggak mendengarkan apapun yang mereka katakan ke gue. Untuk nggak peduli semua label yang mereka tempel di belakang seragam sekolah gue. Di situlah gue semakin yakin bahwa mereka yang ngatain gue itu sebenarnya nggak lebih keren kok dari gue. Dan itu kelihatan jelas banget. This might sounds like I’m bragging about my high-school year, but this is important and related for the rest of this post. Gue membalas semua label dan ejekan yang mereka berikan dulu dengan jadi penyiar radio swasta paling hits se-pulau Lombok, jadi nomor satu di sekolah (JUARA UMUM SATU SELAMA 4 SEMESTERS IN A ROW BABY! EAT THAT SHIT, YOU A*************!!!!!!!) Nggak berhenti sampai di situ, ketika kita bahkan belum ujian nasional gue sudah diterima di Universitas Indonesia. That’s it. That’s the end of my misery. You can say anything about me. You can say cebol sampai bebusa. You can say I’m a f*cking f** sesuka lo. But guess what, I already win this high school war. Good luck to you all, as*h*l*-deul!
Orang-orang itu, yang memberikan label ke gue, adalah mereka yang berperan besar dalam menumbuhkan rasa nggak aman (atau mungkin lo lebih akrab dengan kata ‘insecurity’) dalam diri gue. Semakin dewasa lo akan semakin belajar untuk nggak memikirkan insecurity lo lagi tapi ketika anak-anak, terlebih ketika nggak ada orang yang menjelaskan ke lo soal apa itu insecurity itu dan bagaimana cara mengatasinya, siapa yang bisa menjamin lo nggak akan kepikiran?
Ada yang disebut critical inner voices buat orang-orang yang merasakan insecurity. Penyebabnya nggak cuma karena orang-orang yang memberikan label ke lo itu, tapi di tingkat yang lebih basic lagi bisa dari bagaimana cara lo dibesarkan. Kalau lo sering mendengarkan kata-kata kayak “Dasar pesek!” atau “Gendut, makan terus ya kerjanya!” atau “Ini lagi si pendek nangis terus!” ya bisa jadi lo akan lebih mudah memikirkan kritik-kritik terhadap diri lo sendiri, oleh diri lo sendiri. Critical inner voices inilah yang kemudian memunculkan rasa nggak aman itu. Lo akan mulai merasakan ada aja yang salah terhadap diri lo. Sesimpel Dewa yang mau upload foto aja.
“Gimana kalo nanti dikomentari kurus? Gimana kalau rambutnya nanti dibilang lepek? Gimana kalau senyumnya dibilang kayak psikopat?”
Bla
Bla
Bla
Gue misalnya, dulu takut berdiri di barisan paling depan ketika upacara bendera (karena bangsa ini entah gimana ceritanya membuat peraturan “yang pendek di depan”) karena itu akan membuat gue terlihat “cebol” seperti yang orang-orang bilang. Gue hanya pakai kaca mata ketika belajar di kelas doang karena gue nggak mau disebut “mata empat” kalau gue pakai kaca mata ketika main-main (walaupun nggak bisa karena ngeliat jalan jadi burem huhuhuhu). Gue nggak mau ngomong sama siapapun di luar kelas pas SMP karena gue takut mengeluarkan suara gue yang cempreng dan dibilang kayak cewek. Bahkan takut keluar kelas untuk makan di kantin ketika SMA (ini sering gue tulis) karena nggak berani ketemu orang banyak. Takut bakalan jadi sasaran tembak. Takut diejek. Karena mereka bisa menemukan 1001 bahan ejeken dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Sederet insecurity itu bikin gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Takut berbuat sesuatu. Takut bergaul. Takut kalau orang-orang akan bilang gini, kalau orang-orang akan bilang gitu. Di satu titik pasti akan membuat gue jadi nggak berkembang sama sekali. Belakangan gue baru ngerti kenapa orang-orang tuh suka banget menjatuhkan orang lain: ya itu sudah tugas mereka. Sudah tugas mereka untuk ngomongin orang. Sudah tugas mereka untuk nge-judge orang. Parahnya, sudah jadi habbit manusia melakukan itu. Orang yang sudah berusaha menjaga diri dan sikapnya pun akan tetap di-judge kok. Karena begitulah mereka dibesarkan. Whatever you’re doing, even if it’s good, people will judge and say something bad about you anyway. Apalagi di media sosial.
Gue nggak munafik juga kadang-kadang ngomongin atau nyindir orang di media sosial. Everyone did. I am that everyone. Well, harus diperbaiki sih dan jangan sampai jadi kebiasaan. Gue bahkan pernah di-bash waktu ngomentarin soal perubahan tubuh bentuk tubuh Kyungsoo.
Soal di-judge dan dikatain jelek sama orang itu yang gue pelajari selama beberapa tahun merantau di Depok/Jakarta. Itu juga yang gue bilang ke Dewa ketika obrolan kita soal malu posting foto diri sendiri di Instagram berujung ke curhat mendalam soal insecurity.
“Accepting is relieving, Wa. Itu kuncinya.” Kata gue sok bijak.
Tapi sepengalaman gue itu benar.
Ketika gue merasa insecure dengan tinggi badan gue, gue melihat ada banyak sekali orang-orang sukses yang punya tinggi badan di bawah rata-rata. Sebutlah Daniel Radcliffe dan Elijah Wood. Dan hey, bodo amat gue pendek, nggak ada ruginya juga buat lo. Badan gue yang pendek, bukan titit lo. #YAGITU Ketika gue merasa insecure dengan rambut gue yang keritingnya aneh dan terlihat seperti jembut gini, banyak juga orang-orang yang nggak punya rambut tapi pede aja. Bahkan ada orang yang rambutnya kribo maksimal juga justru jadi modal penting untuk identitas mereka. Beberapa temen gue pun bahkan sering ngeluh soal rambut mereka yang padahal udah lurus dan rapi dan lebih bagus daripada gue (even Dewa pun sempat mengeluhkan soal rambutnya yang selalu terlihat lepek yang padahal menurut gue nggak sama sekali dan looks supersupergood sampai gue iri). Ketika gue merasa insecure dengan hidung gue yang bagian bawahnya agak ngembang gitu, gue selalu ingat bahwa Voldemort bahkan nggak punya hidung.
Siapa sih yang nggak mau jadi sempurna? Tapi apakah ada orang yang sempurna selain Muhammad SAW? Dan ketika lo sudah menerima ketidaksempurnaan yang ada dalam diri lo itu, tidak menjadikannya sebuah masalah, tidak menyalahkan perkataan orang lain tentang diri lo, maka lo akan baik-baik saja.
Ketakutan Dewa akan komentar-komentar tentang dirinya di media sosial sebenarnya wajar. Tapi sekali lagi, ya begitulah manusia. Begitulah orang-orang. Mereka akan bilang rambut lo nggak bagus, hidung lo gede banget, mata lo berkantung kayak Kanguru, kenapa gigi lo nggak rata, itu kumis lo kenapa tebel sebelah, bibir lo kenapa miring, dan bla bla bla. Dan tugas lo bukan menanggapi semua itu kok. Lo cuma harus bilang “Iya. Memang begitu adanya. Ada masalah?” itu aja. Boleh lah ditambah dengan “Ya kayak rambut lo paling bagus di dunia aja, anjing. Gausah sok-sok nilai rambut gue deh.” kalau lo adalah Awkarin atau kebetulan menjadikan dia sebagai role model. Kalau secara moral lo merasa balasan itu terlalu kasar (dan tidak ada bedanya dengan komentar orang yang kamu balas, anyway) ya jangan. Mending diem aja. Di sini ungkapan “diam itu emas” sangat pas sekali. Bayangkan kalau emasnya emas beneran. Sudah kaya raya kamu sekarang.
Tapi kalau nggak kaya raya sekarang, nanti aja kaya raya di surga ya. Aamiin.
Kalau masuk.
Kita semua punya rasa insecurity. Bahkan kalau gue pikir-pikir, mereka yang dulu sering ngatain gue pas SMA itu sebenarnya juga punya insecurity yang lebih besar dari gue. Masalah hidup mereka mungkin lebih menantang dari gue. Dan saat itu mereka memang butuh pelampiasan instan. Dan sialnya aja gue selalu ada ketika mereka butuh pelampiasan itu. Hidup kadang-kadang selucu itu. Tapi in the end of the day itu memberikan banyak pelajaran kok. Kan sekarang jadi lebih wise dan jadi lebih mengerti gimana menghadapi permasalahan macem ini. Semoga juga jadi bisa membantu mereka yang masih berkutat dengan segala insecurities-nya.
Ketika lo mulai merasa "gue kok jelek banget sih dibandingkan dengan orang lain", cepat-cepat sadar bahwa lo nggak boleh berada dalam kondisi kayak gitu terus-terusan. Dan lo juga nggak bisa membandingkan diri lo sama siapapun. Karena lo bukan orang lain. Lo ya lo. Inget juga kalau mereka yang ngatain lo belum tentu lebih baik dari lo. Mereka cuma orang yang justru memiliki rasa insecure lebih besar dari lo. Yakin!
“As weird as this sounds, Wa, but you’re good looking. Nothing to worry about your face or appearance. You’re better than me, kok. Bedanya mungkin aku lebih nggak peduli aja sama omongan orang. Karena aku sudah terlalu banyak mendengarkan pendapat dan omongan orang sampai-sampai aku jadi nggak mendengarkan dan menghargai pendapatku sendiri. Jangan biarin apa yang orang bilang tentang kamu mendefinisikan diri kamu. Dan ini kenapa perkara foto Instagram aja jadi serius gini ya omongannya?”
Kita berdua tertawa.
Gue sebenarnya ngerasa nggak enak sama Dewa hari itu. Karena kok kesannya gue kayak sok-sok nguliahin dia banget sih? Sok dewasa banget sih? Sok paling iye banget sih? Gue juga tanya ke dia apakah obrolan ini sebenarnya penting atau nggak, soalnya kalau nggak penting mending jangan dilanjutkan daripada panjang. Juga apakah dia merasa diceramahi atau nggak. Dan menurut dia, obrolan ini terbilang oke dan bisa memberikan insight. Jadi gue merasa tenang.
Nggak kerasa nasi goreng kita udah abis dan sudah jam 10 malam juga. Akhirnya kita mutusin buat pulang karena besok masih hari Kamis dan masih harus kerja.
Sepanjang jalan gue mengutuk diri gue karena kayaknya terlalu banyak omong ke Dewa hari itu. Kebiasaan gue kalau lagi ngobrol sama orang tuh memang suka gitu. Suka terlalu jauh dan merembet ke mana-mana. Terus ujung-ujungnya jadi kayak menasihati. Padahal kan sebenarnya mungkin mereka nggak perlu nasihat cuma perlu didengarkan. Dewa pun sempat bilang sebelum kita bertolak ke motor masing-masing kalau dia sebenarnya nggak pernah seterbuka itu ke orang lain. “Aku juga bingung kenapa aku jadi banyak omong gini ya ke kak Ron? Aku sebelumnya nggak pernah cerita ini sama siapapun.” Tapi sebelum kita berpisah jalan di sebuah persimpangan di Ampera, Dewa berterima kasih atas obrolan tadi “Membantu banget, kak.” katanya.
Itu bikin gue sedkit lebih ringan untuk tidur malam ini.
Ketika gue bangun keesokan harinya dan ngecek Instagram, perhatian gue langsung tertuju ke deretan lingkaran di bagian atas aplikasi itu. Lingkaran kedua dari kiri, di sebelah lingkaran avatar gue, ada satu avatar yang belum pernah gue lihat selama beberapa bulan terakhir.
Gue tersenyum lebar.
Dewa mengganti avatar Instagram-nya.
Follow Me/KaosKakiBau in everywhere!
Watch my #vlog on YouTube: KaosKakiBauTV (#vron #vlognyaron)
Twitter: ronzzykevin
Twitter: ronzzykevin
Facebook: fb.com/kaoskakibau
Instagram: ronzstagram
LIVE SETIAP SENIN JAM 8 MALAM 'GLOOMY MONDAY!'
Instagram lain: kaoskakibaudotcom
LIVE SETIAP SENIN JAM 8 MALAM 'GLOOMY MONDAY!'
Instagram lain: kaoskakibaudotcom
Line@: @kaoskakibau (di search pake @ jangan lupa)
photos on this post is from pexels.com
photos on this post is from pexels.com












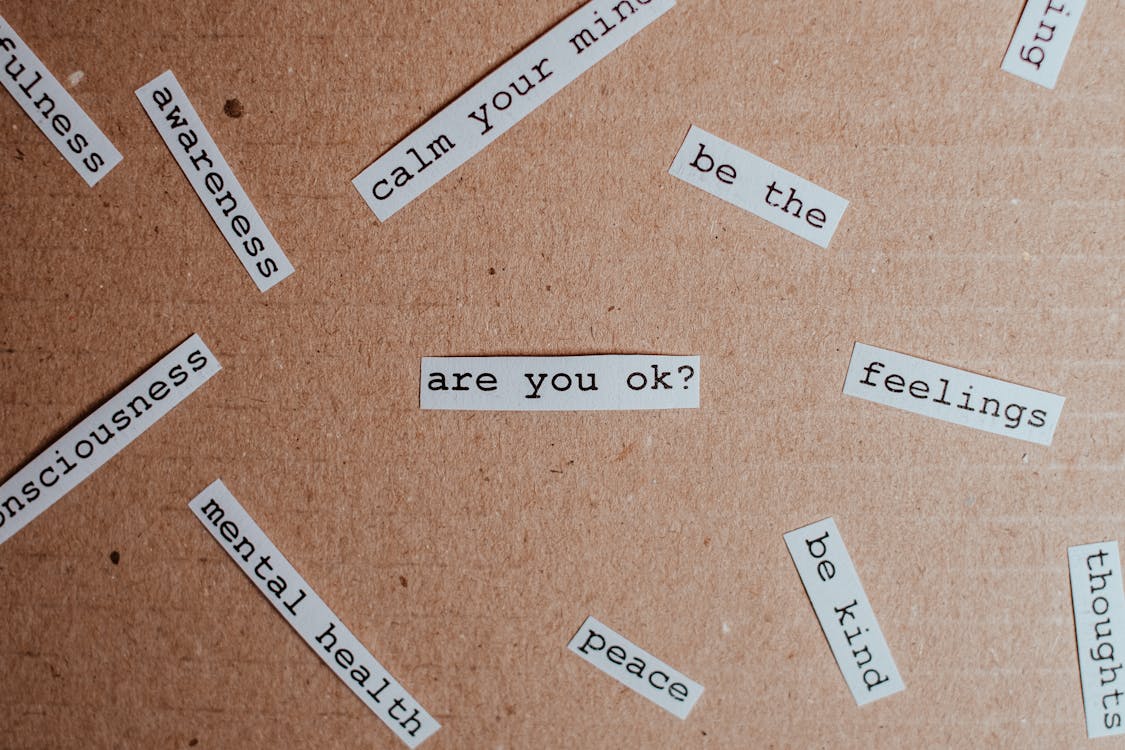









0 comments