Musim Semi dan Sungai Thames [Part 4]: Welcome to London!
Ssamziegil, Insadong, Seoul, Korea Selatan
Desember 2017
Gue nggak heran kalau tempat ini jadi favorit semua orang, terutama mereka yang sudah punya pasangan, karena gue sendiri sebagai turis yang baru tiga kali berkunjung ke Seoul merasa tempat ini adalah lokasi yang harus dikunjungi. Entah ketika lo jalan-jalan sendiri atau sedang sama pasangan. Atau yah, sama temen deh paling enggak. Gue bukan orang yang against the idea of traveling alone. Not at all. Hahah. Gimana bisa orang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian kayak gue against that idea? Kocak. Ketika nggak ada orang yang bisa lo ajak buat jalan ke sebuah tempat yang belum pernah lo eksplor sebelumnya, atau sesimpel misalnya nggak ada orang yang mau ketika lo ngajak mereka buat nonton satu film yang sangat ingin lo saksikan sejak sekian lama, ya pergilah sendiri. Lakukan sendiri. Buat kebahagiaan lo sendiri. Untuk beberapa hal lo nggak perlu bergantung sama orang lain. In fact, lo nggak (selalu) perlu orang lain untuk membuat diri lo bahagia. Happiness is a state of mind. Gue memang belum expert untuk hal yang satu itu tapi setidaknya gue mencoba. Well, ketika lo sudah terbiasa tidak bergantung dengan orang lain, lo akan lebih berani untuk do something by yourself. Bahkan sesuatu yang awalnya mengerikan kayak jalan-jalan sendiri.
Sebentar, tempat yang gue maksud di awal paragraf di atas adalah Ssamziegil. Oke, mungkin realitanya, tempat ini adalah lokasi membosankan buat para Seoul citizen. Mungkin juga buat lo yang sudah sering ke Korea (yang ke Korea-nya udah kayak ke Bandung gitu ya bisa tiap akhir bulan), lo juga akan bilang “Hah, apa serunya sih ke situ?” Ya, tidak apa-apa. Namanya beda orang kan beda kepala. Beda pendapat tentang sesuatu.
Kesan pertama gue tentang tempat ini mungkin hampir sama dengan semua tempat yang pertama kali gue kunjungi ketika gue ke Seoul: menyenangkan. Insadong sejatinya adalah sebuah jalan rapi yang di kiri dan kanannya banyak toko-toko souvenir, toko-toko tas, kosmetik, dan juga street food stalls. Ada satu toko teh yang aroma green tea-nya sangat membuat kalem yang gue masuki juga waktu itu tapi gue nggak beli apa-apa karena saking kerenya. Suasana Insadong di siang hari yang mendung dengan jalan-jalan yang basah entah gimana memberikan kesan romantis. Yang menarik perhatian gue di Insadong hari itu adalah Ssamziegil. Sebuah kompleks pertokoan yang waktu itu sudah berhiaskan ornamen natal dengan lampu warna-warni. Kompleks pertokoan ini ada di salah satu sudut jalan di Insadong. Sepetak gitu dan nggak terlalu luas, tapi ada beberapa lantai menjulang ke atas. Lo bisa jalan dari lantai satu ke lantai paling atas dan turun pake lift dari lantai atas ke lantai satu. Sepanjang jalan itu lo pasti akan sangat tertarik buat masuk ke toko-toko yang ada di sana. Soalnya banyak toko yang jual handicraft lucu-lucu gitu.
“Serius deh, kalian pasti akan laper mata di sini!” kata gue ke Ambar, Ais dan Rizka, tiga temen yang berangkat bareng gue buat Winter Trip di Seoul tahun lalu, ketika gue meminta mereka memasukkan Ssamziegil ke salah satu lokasi yang harus dikunjungi di Seoul. Kita baru habis dari Bukchon Hanok Village hari itu dan matahari sudah terbenam waktu kita jalan ke Insadong. Udara cukup dingin dan kaki gue udah lumayan pegel. Tapi karena gue udah berniat untuk beli satu atau dua hal dari Ssamziegil hari itu, gue jadi bersemangat. Dari semua toko handicraft dan souvenir yang kami masuki malam itu, sebuah toko bernama Indigo jadi tempat yang menahan kami paling lama. Bukan karena tempat ini rame, tapi karena tempat ini tuh punya banyak banget barang lucu. Mulai dari notes, pouch, buku cerita anak-anak (yang ilustrasinya digambar ulang oleh artists yang bekerja sama dengan toko tersebut), sampai passport case. Yang terakhir gue sebutkan punya cerita tersendiri yang lima bulan kemudian bikin gue senyum-senyum sendiri.
Di kunjungan ketiga gue ke Seoul ini, gue ingin punya sesuatu yang setidaknya bisa gue lihat selalu. Sesuatu yang lucu, menarik, dan worth it buat gue beli. Gue pribadi bukan tipe orang yang belanja-belanja gitu kalo jalan-jalan. Yah, gue masih anggota dari sahabat miskin social club. Tapi kali ini gue merasa kalau gue harus beli sesuatu. Dan nggak nyesel banget masuk Indigo karena ada banyak sekali hal yang bisa jadi pilihan. Gue berdiri lama banget di pojok ruangan yang isinya kotak-kotak berukuran kayak bingkai foto 4R yang isinya adalah puzzle bergambar dari cerita-cerita dongeng seperti Alice in Wonderland dan sejenisnya. Gue memang enggak terlalu mengikuti Alice. Dibandingkan dengan Lion King, film versi Disney-nya nggak mewarnai hari-hari gue waktu kecil. Yah maklum, film itu kan sudah dirilis lama banget, bahkan sebelum Lion King. Versi Tim Burton-nya sih gue tonton. Tapi nggak meninggalkan kesan yang terlalu mendalam juga. But anyway, karena IU pernah punya konsep comeback menggunakan cerita Alice in Wonderland (begitu juga dengan EXO), jadi gue meraih satu kotak puzzle itu dan memasukkannya ke dalam keranjang.
“Aku nggak tahu sih apakah ini akan jadi sesuatu yang worth it, tapi gue pikir, kalau gue sudah menyelesaikan puzzle-nya, gue bisa bingkai dan jadi pajangan di kamar atau di rumah gue nanti,” kata gue ke anak-anak. Ingin rasanya beli buku-buku cerita kecil atau notes lucu yang juga dijual di sana. Hanya saja mengingat benda-benda itu akan makan tempat di koper dan ada banyak banget CD Kpop yang gue beli beberapa hari sebelumnya, gue pun mengurungkan niat itu. Sambil berjalan ke bagian lain dari toko, perhatian gue tertuju ke sudut lain yang lokasinya persis di depan pintu masuk. Sebenarnya dari tadi gue udah ingin berdiri lama di situ tapi agak ragu-ragu. Di sudut itu ada poster peta dunia besar berwarna kecoklatan dengan banyak pin seperti jarum pentul yang ditusuk di beberapa bagian benuanya. Sebuah poster buat orang yang ingin keliling dunia dan bisa ngasih tanda mereka sudah ke mana aja.
Gue butuh ini satu kalau gue udah kaya raya nanti. Gue membatin.
Di rak di bawah poster itu ada sederet traveling related stuff. Salah satunya passport case.
“Ini lucu banget!” kata gue ketika memegang satu case berwarna biru yang di bagian depannya menampilkan peta dunia yang fokus ke Korea Selatan. Rizka datang menghampiri gue dan setuju kalau dia juga merasa dia harus beli passport case itu. “Kalau kita beli yang ini berarti kembar dong ya? Ketuker ntar bahaya juga,” kata gue bercanda. Padahal kan nggak mungkin juga gue sama dia selalu jalan-jalan bareng. Paling setahun sekali dan itu pun nggak akan selalu terjadi. Gue melihat lagi passport case itu dan membatin lagi.
Gue nggak suka warna biru.
Sebenarnya dulu suka. Tapi ada alasan kenapa akhirnya gue nggak suka lagi sama warna itu. Dan gue nggak suka menjelaskan alasannya. Gue nggak suka mengenang memori lama yang “menyakitkan”. Hahaha!
“Yaudah sih kak, kamu ambil yang itu aja. Nggak mungkin ketuker,” kata Rizka.
“Tapi aku nggak mau warna biru. Yaudah kalau gitu kamu ambil yang itu, aku ambil yang ini aja,” kata gue mengambil passport case dengan warna yang berbeda. Yang gue ambil itu warnanya dominan kecoklatan. Gue senyum-senyum sendiri ketika melihat bagian depannya. Kalau yang biru tadi menampilkan peta dunia bagian Korea Selatan (dan Utara dan Jepang), yang coklat ini menampilkan benua Eropa. Termasuk di sebelah kanan tengahnya adalah peta dunia United Kingdom.
“To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.”
Setuju.
Untuk mencapai hal-hal besar, kita tidak hanya perlu bertindak, tapi juga bermimpi; tidak hanya tentang rencana, tapi juga percaya.
Sepulang dari Ssamziegil dan kembali ke hostel kami di Itaweon, gue buru-buru mengganti passport case gue dengan yang baru gue beli itu. Yang lama sudah patah di bagian tengah jadi memang sudah waktunya diganti. Gue inget banget waktu gue upload foto passport case itu ke Instagram Stories, gue sudah langsung nge-set mimpi bahwa tahun 2025 nanti, gue akan bisa ke Inggris.
Tapi siapa sangka ari-ari gue nyangkut di Inggris tujuh tahun lebih cepat daripada rencana.
Jakarta – Singapura – London.
Mei 2018.
Rasanya masih nggak nyata sama sekali. Gue duduk di dalam pesawat menuju ke Singapura sore itu dengan perasaan yang sama sekali nggak bisa gue jelaskan. 99% dari perasaan itu adalah bahagia dan hanya 1% saja yang berisi kekhawatiran-kekhawatiran soal hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan (damn this overthinking habbit!) dan tagihan-tagihan yang akan keluar setelahnya. Gue yang biasanya tidur di dalam perjalanan mau naik mobil, kereta, atau bahkan pesawat, dalam durasi yang singkat sekali pun, hari itu nggak bisa sama sekali tenang. Kepala gue rasanya dipenuhi dengan excitement berlebihan. Ya gimana enggak, gue bakal ke Inggris! Perjalanan gratis lain yang gue sendiri tidak pernah menyangka akan gue dapatkan bahkan sebelum setahun setelah gue pindah ke kantor baru gue. Sebuah hadiah ulang tahun yang nggak akan gue lupakan sepanjang hidup gue. Sebuah cerita yang akan gue tuliskan di blog dan gue harap akan bisa membuat gue bernostalgia kembali ke masa-masa ini setelah gue tua nanti. Gue duduk dekat jendela, seperti biasa setiap kali terbang, tempat ini walaupun agak ribet kalau mau ke toilet, tapi paling enak karena bisa sedikit mengurangi perasaan nervous yang kadang-kadang datang tanpa aba-aba. Ketika gue sudah lelah melihat layar atau sudah terlalu capek karena nggak menemukan posisi kepala yang pas meski kursi sudah gue mundurin beberapa derajat ke belakang, pemandangan langit dan awan bisa membantu membuat tenang sejenak.
“Yang dari Singapura ke London juga mau deket jendela?” kata mbak-mbak yang ada di loket check in Soekarno-Hatta beberapa puluh menit yang lalu. Yang langsung gue jawab dengan mengangguk bersemangat.
“Ya kalau bisa sih mau banget!” kata gue.
“Bisa dong,” katanya sambil senyum.
“Mbak ini kopernya kan ukuran kabin, tapi saya takut beratnya melebihi kapasitas yang dibolehkan masuk kabin mengingat saya juga bawa ransel. Tapi isi ransel saya cuma laptop doang. Jadi apakah saya harus taruh ini ke bagasi pesawat? Boleh ditimbang dulu kali ya?” tanya gue.
Koper itu beratnya sekitar tiga atau empat kilo, gue nggak tahu apa yang bikin berat, nggak mungkin celana dalem gue kan ya. Ransel gue nggak mungkin lebih dari dua kilo karena gue nggak akan betah gendong itu ransel kalau terlalu berat. Tapi kata mbak-mbaknya nggak apa-apa dibawa aja ke kabin jadi yaudah, gue seneng banget, jadi nggak perlu repot-repot nungguin bagasi nanti pas di Heathrow. Sekarang koper merah itu sudah nyaman di bagasi bagasi di atas kepala sementara pikiran gue masih melayang jauh entah ke mana. Nggak lama lagi pesawat itu akan mendarat di Singapura. Melihat cahaya kota yang berpendar di kejauhan dari jendela pesawat itu membuat gue teringat ke perjalanan-perjalanan gue sebelumnya. Gue inget waktu melayang di atas Doha pas ke New York. Pengalaman sekali seumur hidup yang mungkin nggak akan terulang lagi. Gue juga mendadak inget kalau belum lama ini gue mampir ke Singapura buat ketemu sama Queen dan Huaqing. Tangan gue tanpa sadar masuk ke kantong jaket hoodie yang gue beli di Uniqlo pekan lalu. Paspor gue ada di sana. Gue keluarin lalu gue pandangin lama. Kenangan lain sekarang muncul di kepala gue. Kenangan soal Insadong, Ssamziegil, dan apa yang gue katakan sebagai “janji” ke diri sendiri ketika gue membeli passport case itu. Gue tersenyum kecil ketika pesawat itu terbang semakin rendah dan akhirnya mendarat di Changi Airport.
Walaupun sudah berkali-kali ke sini dan mendarat di Terminal 2, gue masih nggak pernah hapal sama tempat ini. Utara dan Selatan selalu ketuker. Barat dan Timur nggak bisa gue bedakan. Ketika gue keluar dari pesawat dan berusaha mencari jalan menuju ke tempat salat yang gue inget ada di dekat tangga turun di belakang toko-toko duty free, gue kesasar ke ujung terminal kedatangan. Gue sempat melihat ke peta lokasi yang ada di pojok ruangan dan cari tahu sekarang gue ada di mana. Tapi tetap aja gue nggak menemukan jawaban. Mungkin ini karena efek terlalu excited makanya gue jadi agak linglung. Dengan wajah kebingungan gue menggeret koper merah itu dan berjalan ke sisi lain dari terminal kedatangan. Di sanalah gue papasan dengan pramugari Singapore Airlines yang tadi sempat ngobrol sama gue di pesawat ketika gue minta kopi.
“May I help you? Are you looking for way out?” katanya.
“Yes, I actually got lost,” gue ketawa.
Dia juga ketawa. Dia cantik juga.
“You should go to the other way. This is the end of the arrival terminal,” katanya lagi.
“Ah, sure, thanks!” gue menjawab sambil lalu.
Waktu Asar sudah mau habis karena kelamaan bingung. Langkah gue juga agak melambat karena gue ternyata nggak bisa connect ke Wi-Fi. SMS kode OTP-nya nggak masuk-masuk jadi gue harus cari mesin registrasi Wi-Fi. Itu juga akhirnya menyita waktu gue. Setelah menemukan pencerahan gue sedang ada di mana dan gue harus pergi ke mana, gue pun mulai familiar dengan apa yang ada di sekitar gue. Biasanya memang gue gampang mengingat lokasi setelah tahu tempat-tempat familiar. Setelah ini pasti ada ini, setelah ini kalau nggak salah ada ini. Gue selalu bicara sendiri kalau sedang jalan. Setidaknya itu membantu gue untuk berkonsentrasi. Beruntung Maghrib di Singapura datangnya nggak secepat di Jakarta. Jadi gue masih sempat salat Asar dulu dan nggak lama menunggu, Maghrib datang, lalu gue salat lagi dan kali ini menggabungkannya dengan Isya. Mengingat gue akan sampai di London subuh waktu setempat jadi gue nggak akan repot salat di pesawat nanti.
Gue harus pindah ke Terminal 1 untuk naik pesawat ke London malam itu. Dan ternyata Gate keberangkatannya lumayan jauh dari tempat naik/turun Skytrain di Terminal 1. Gue sama sekali nggak pernah ke Terminal 1 Changi Airport jadi gue nggak aware sama sekali dengan lokasinya. Walaupun penerbangannya masih sekitar satu jam lagi, tapi gue nggak mau mengambil risiko dengan berlama-lama. Nggak lucu banget kalau gue ketinggalan pesawat padahal gue sudah ada di Terminal keberangkatan, hanya karena gue berlama-lama di jalan.
“This airport is so huge!” kata ibu-ibu asal Filipina yang kebetulan transit di Singapura dan sepertinya akan naik penerbangan yang sama dengan gue ke London. Gue berjalan cepat di samping ibu-ibu yang gue temui di Skytrain itu. Tadi dia terlihat bingung karena kayaknya itu pertama kalinya dia ke Changi dan naik Skytrain dari Terminal 2 ke Terminal 1.
“Yeah, and this is only Terminal 1,” kata gue.
“Are you traveling alone?” dia nanya sambil terus jalan cepet di sebelah gue. Dia nggak banyak bawa barang. Gue menebak dia sudah lama tinggal di London.
“Yes. Work trip. Will be in London for few days,” jawab gue.
“How many days to be exact?”
“Four,”
“What? You should stay longer!” katanya.
Yeah ma’am, I wish I could stay for a month too. Gue membalasnya dengan tersenyum.
“So are you traveling alone too?” gue yang tadinya nggak berniat untuk menyambung obrolan jadi malah mengajukan pertanyaan yang jawabannya bisa jadi panjang itu. Dan beneran aja, jawabannya panjang. Dia menceritakan bagaimana akhirnya dia bisa jadi London citizen sekarang karena katanya dia udah kerja lebih dari tujuh tahun di sana. Dia asli Filipina dan sudah berkeluarga dan semua keluarganya ada di London. Dia sempat mengeluh soal traffic di sana dan bagaimana sibuknya London sementara gue hanya bisa ber “hehe you don’t know Jakarta ma’am” saja dalam hati. Gue makin yakin kalau ibu-ibu ini memang belum pernah terbang via Changi karena dia keliatan buru-buru banget mau naik pesawat ketika kita akhirnya sudah sampai di Gate keberangkatan. Padahal jelas-jelas tulisan di depan Gate itu belum menunjukkan informasi tentang pesawat Singapore Airlines yang ke London. Karena gue merasa benar dan tidak mau repot bolak-balik dan keluar Gate lagi (yang kemudian terjadi pada ibu-ibu itu), gue sudah duduk manis di kursi tunggu di depan Gate keberangkatan.
Oh shit.
Gue mengumpat pelan. Gue lupa kalau di tas gue ada SariRoti yang dibeli nyokap tiga hari yang lalu buat bekal gue di pesawat dari Lombok ke Jakarta dan roti itu kayaknya sudah expired kemarin. Karena takut kualat tidak makan roti pemberian nyokap, dan gue juga sedang agak lapar karena makanan di pesawat dari Jakarta ke Singapura itu sudah hilang dari perut gue, akhirnya roti itu gue makan juga. Untungnya gue tidak apa-apa dan tidak mules-mules. Karena biasanya perut gue sangat sensitif sama roti apalagi kalau dipadu dengan susu. Gue nggak sabar untuk makan lagi di pesawat menuju London malam itu.
“Di lantai dua ada ruangan kelas satu dengan tempat tidur,” katanya.
Entahlah apakah gue akan sempat hidup untuk merasakan bagaimana pesawat kelas satu dengan tempat tidur itu. I mean... kelas ekonominya aja luar biasa keren banget! Gue berjalan masuk dengan langkah yang udah nggak fokus sama sekali karena sibuk jelalatan ngeliatin sekitar. Berkali-kali koper yang gue dorong di depan gue nabrak kaki kursi orang-orang dan nabrak kaki gue sendiri. Sambil mangap dan wow banget ngeliat dalam pesawat itu, gue nyari tempat duduk gue. Berharap yang duduk di dua kursi di sebelah kanan kursi gue adalah jodoh gue nanti. Atau setidaknya orang yang bisa diajak ngobrol seru selama belasan jam di udara. Hahaha. This is a dream that always there in the back of my head since like forever. Di zaman-zamannya gue masih sering nulis cerpen dulu, gue pernah bikin dua cerita yang berbeda tentang orang yang ketemu di pesawat dan kemudian berakhir jatuh cinta. Bahkan gue pernah bikin cerita berjudul ‘Stranger on the Train’ yang gue kumpulin jadi tugas penulisan skenario di semester dua kuliah. Ceritanya tentang cewek yang naik kereta (anggeplah dari Bandung ke Jakarta—tapi di cerita itu setting-nya kota fiktif) dan ketemu sama cowok ganteng yang sangat menarik perhatiannya. Tapi cowok itu ternyata teroris.
Well, sometimes we falling in love with the wrong person.
Right?
Sayangnya itu masih sekedar mimpi. Yang duduk di samping gue malam itu adalah dua perempuan berwajah oriental yang mengeluarkan aura gloomy. Agak nyeremin gitu. Dari auranya gue sudah bisa menebak kalau gue akan sangat kesulitan izin ke toilet nanti. Mengingat gue duduk di paling ujung dekat jendela. Oke, kecuali kalau sudah kebelet banget deh baru izin ke toilet. Sepanjang perjalanan itu mereka benar-benar tidak bicara apapun sama gue. Tapi salah satu dari mereka, yang kelihatan lebih tua dari yang lain, baik banget mau oper-oper nampan makanan dan snack setiap kali pramugarinya lewat. Ngomong-ngomong soal makanan, gue lupa banget pesan Muslim Meals ketika check in di Jakarta sore tadi. Gue jadi khawatir untuk makan di pesawat kalau-kalau menunya nggak halal. Tapi sekali lagi, Singapore Airlines membuat gue sangat wow banget deh. Setelah duduk, setelah dikasih hot towel buat cuci muka, pramugarinya ngasih buku menu makanan hari itu. WAH GILA GUE GAK PERNAH NAIK PESAWAT EKONOMI DAN DIKASIH MENU MAKANAN KAYAK GINI!
Setelah mengecek buku menu yang dikasih malam itu, gue melihat nggak ada satupun dari menu yang menyajikan makanan-makanan yang berpotensi tidak halal. Walaupun, yah, nggak tahu sih pengolahannya gimana. Yaudah bismillah aja. Kalau dosa yaudah dosa. Semoga Allah mengampuni dosa gue. Gue sudah lapar to be honest. Pilihan makanan malam itu ada tiga: Ayam, Ikan, dan Biri-biri. Karena gue tidak terlalu suka Biri-biri dan karena gue sudah bosan makan ayam di kantor setiap hari, gue pilih Ikan aja. Lumayan untuk mengisi perut sampai waktunya sarapan besok. Di antara waktu makan malam dan sarapan sebelum mendarat besok, gue berencana untuk nonton film yang ada di koleksi film mereka. Tapi nggak banyak film yang membuat gue tertarik karena beberapa di antaranya sudah pernah gue tonton dan beberapa yang lain agak membosankan. Tapi gue memilih untuk menyaksikan ‘Justice League’ karena memang gue belom nonton. Tapi belum sampai setengah film gue udah ketiduran. Ketika gue bangun lagi, gue lanjut nonton di bagian yang belum gue tonton berjam-jam kemudian. Setelah itu nggak ada lagi hal menarik yang bisa dilakukan. Gue coba buka-buka koleksi lagu Korea yang mereka punya dan ada beberapa album yang gue suka kayak SNSD ‘Lion Heart, f(x) ‘4 Walls’ dan EXO ‘Lotto’. Gue memilih mendengarkan ‘Lion Heart’ sambil memerhatikan peta dunia yang menampilkan rute pesawat di layar.
Pesawat itu terbang melewati Asia Selatan menuju ke kawasan Kuba dan Eropa. Gue sempat terbangun ketika pesawat melewati Berlin dan berharap suatu saat gue bisa berkunjung ke Jerman dan sekitarnya. Mungkin beneran nanti di tahun 2025 gue bisa melakukan tur Eropa itu meski sendirian, nggak masalah. Mimpi dulu kan sebelum menjadikannya kenyataan. Yang jelas tahun depan harus Umroh dulu mengingat sudah janji sama nyokap. Semoga lancar. Gue tertidur lagi dan bangun ketika sarapan sudah mau disajikan. Setelah selesai makan dan nyaris satu jam lagi sebelum mendarat di London, gue memanfaatkan kekosongan dua kursi di sebelah kanan gue dengan pergi ke toilet. Di depan dan di belakang, toiletnya antre banget. Kayaknya orang-orang memang nahan pipis banget dari tadi ya sampai-sampai antreannya bisa enam atau tujuh orang gitu. Gue awalnya nggak kebelet-kebelet banget tapi lama-lama berdiri gue jadi senewen juga dan akhirnya malah makin kebelet. Ketika akhirnya toilet di bawah tangga menuju kelas satu yang ada tempat tidurnya itu (gue sempat ngintip ke tangga mewahnya) kosong, gue masuk dan melakukan hajat, cuci muka, sikat gigi, menuangkan sepercik dua percik cologne dengan aroma khas yang disediakan pesawat itu ke tangan, menepuk-nepukkannya ke beberapa bagian jaket, leher, dan pipi, lalu keluar dengan penampilan yang sedikit lebih keren dari sebelumnya.
Gue siap mendarat di London.
Pelan-pelan gue membuka sedikit tutup jendela karena penasaran seperti apa pemandangan di luar. Selama beberapa jam tadi gue ketiduran dan nggak sempat menjepret apapun yang kelihatan di luar sana. Biasanya gue sangat menikmati momen-momen memotret dari balik jendela pesawat ini. Makanya setiap kali terbang gue akan membawa sebuah pouch yang isinya semua benda yang kira-kira gue butuhkan sepanjang perjalanan. Paspor sudah pasti ada di situ, pulpen juga untuk mengisi kartu kedatangan, selain itu biasanya ada powerbank sama kabel charger, dan tentu saja Jeno. Gue membuka sedikit penutup jendela karena kalau langsung dibuka penuh, bisa-bisa dua orang yang ada di sebelah kanan gue akan kesilauan. Mereka sekarang sedang nonton jadi gue nggak mau mengganggu. Tapi rupanya matahari pagi itu belum benar-benar terbit. Hanya ada sedikit cahaya oranye yang tampak di langit jadi gue nggak ragu lagi buat membuka penutup jendela lebar-lebar.
Sepanjang perjalanan ini entahlah masih terasa enggak nyata. Akan tetap terasa tidak nyata sampai gue itu pesawat mendarat di London nanti. Karena masih merasa itu mimpi, gue pun kebanyakan bengong. Pikiran melayang jauh entah ke mana dan entah bagaimana juga mendadak gue inget sama Jari. Jari adalah pramugara kelas bisnis Qatar Airways yang membawa gue ke New York waktu itu. Baik banget dia, semua yang gue minta dia kasih, terutama yang menyangkut soal makanan. Dia juga sempat memperbaiki posisi selimut gue waktu gue ketiduran di kursi kelas bisnis yang nyaman luar biasa itu. Dia juga nggak pernah lupa buat nanyain apakah gue butuh sesuatu selama perjalanan itu. Pikiran soal Jari langsung buyar dan mendadak kepala gue memikirkan seseorang. Seseorang yang nggak seharusnya gue pikirin. Seseorang yang memang selama beberapa bulan terakhir sangat mengganggu pikiran gue dan sering bikin gue ngedumel sendiri dan ngumpat sambil ngebatin. “Gue harus cari cara buat ngelupain orang ini sih. Ah sial,” gue bergumam mungkin terlalu keras sampai-sampai orang yang ada di sebelah gue menoleh dan ngeliatin agak lama. Gue bisa merasakan dia memperhatikan gue selama beberapa detik dari sudut mata gue. Dari situ pikiran gue melayang jauh lagi ke hal-hal enggak penting lainnya yang berusaha gue halau dengan pikiran-pikiran menyenangkan yang sekiranya akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Gue akan mendarat di Heathrow. Gue akan mendarat di London. The city of my dream. Kota yang selama ini hanya berani disebut tanpa pernah berpikir akan benar-benar mengunjunginya sampai di Itaewon tahun lalu. Inggris. Negara asal Harry Potter. Semoga empat hari ke depan akan menyenangkan. Pastinya akan sangat menyenangkan.
Gue memejamkan mata sejenak. Berusaha menghilangkan pikiran-pikiran nggak penting soal apapun dan fokus untuk bersenang-senang (dan bekerja) di London selama beberapa hari ke depan. Matahari sekarang sudah terlihat terbit dan memancarkan cahaya hangat yang menyelinap masuk dari jendela pesawat. Gue bisa merasakan pesawat berguncang sedikit dan mendengar sayup-sayup seperti suara roda yang keluar dari tempat penyimpanannya. Pesawat itu akan mendarat. Gue melirik ke luar jendela dan bisa melihat rerumputan hijau luas dan bangunan-bangunan perumahan yang tertata rapi yang dari atas sana terlihat mungil sekali. Pesawat itu sedang terbang di atas kawasan pinggiran kota. Gue juga bisa melihat pantulan langit dan cahaya matahari dari sebuah sungai, entah sungai apa, mungkin Thames tapi mungkin juga bukan, dari atas sana. Langit sekarang menampilkan paduan warna biru dan oranye. Makin dibuat indah dengan awan-awan tipis yang menyelimutinya.
Makin dekat dengan waktu pendaratan pemandangan sekarang berubah jadi lebih kota. Bangunan-bangunannya jadi makin padat dan pemandangan hijau sudah nggak kelihatan lagi. Getaran semakin terasa dan badan gue sekarang terhempas pelan ke sandaran kursi. Suara mesin pesawat makin jelas terdengar dan bising di telinga. Sementara pandangan gue nggak beralih dari jendela. Baru setelah terdengar suara dari speaker pesawat “Selamat datang di London!” perasaan gue jauh lebih lega. Dada gue nggak lagi sesak dan sekarang gue baru benar-benar yakin kalau ini bukan mimpi.
Seperti biasa, penumpang kelas satu dan kelas bisnis dipersilakan keluar lebih dulu. Gue nggak mau terlalu terburu-buru tapi orang-orang kayaknya kelihatan buru-buru. Setelah dua orang di samping gue keluar dari kursi mereka dan menggeret koper mereka ke depan, gue menyusul dan mengambil koper gue di kompartemen di atas kepala, lalu mendorongnya keluar dari pesawat. Untuk terakhir kalinya gue melihat sekeliling pesawat itu dan menyimpannya jauh-jauh ke long term memory gue. Kursi-kursinya yang berwarna abu-abu. Dinding-dinding pesawat dan kompartemen yang berwarna putih seperti mutiara. Lorong-lorong di antara barisan kursi yang terlihat mewah. Senyum orang-orang yang ceria. Ada yang tidak sabar untuk keluar dari pesawat dan melihat London untuk pertama kali seperti gue. Ada yang tidak sabar untuk kembali ke kampung halaman setelah perjalanan panjang yang melelahkan.
Gue nggak berhenti senyum setiap langkah menuju ke sana. Walaupun sebenarnya nggak terlalu fokus sama apa yang ada di sisi kiri dan kanan sepanjang perjalanan menuju ke imigrasi itu. Gue sendiri nggak sempat merekam atau memotret sekitar karena sibuk mengaktifkan internet, menghubungi pihak penyelenggara yang katanya akan mengirimkan sopir untuk menjemput gue dan mengantar ke hotel. Sempat terjadi perubahan orang dua atau tiga kali hari itu. Awalnya pihak penyelenggara bilang yang akan menjemput gue namanya Ivan. Tapi di-cancel dan akhirnya dia bilang lagi yang akan datang menjemput adalah orang lain. Setelah mengirim nomor Ivan (dan setelah gue menghubungi Ivan walaupun tidak dibalas) dia tidak mengirim nomor orang lain lagi. Karena lama, akhirnya gue cuekin aja handphone gue dan fokus antre di imigrasi.
Entahlah selalu ada perasaan deg-degan setiap kali masuk ke imigrasi di negara lain. Parno gitu lho kebanyakan nonton film-film yang ada adegan terciduk di imigrasi dan kemudian disiksa. Wkwkkw. Gue baca doa dalam hati. Semoga semua lancar sampai gue keluar dari antrean imigrasi ini. Gue mengerling seorang petugas imigrasi berhijab yang ada di barisan kedua dari ujung kiri dan berdoa semoga gue dapet dia aja. Setidaknya kita satu agama dan gue nggak terlalu merasa terintimidasi. Eh, bener aja, ketika barisan di depan gue sudah kosong, gue dipersilakan berjalan ke petugas imigrasi dan dapet si mbak-mbak berhijab.
“Assalamualaikum,” sapa gue otomatis. Dia membalas “Wa’alaikumsalam,” tapi tidak tersenyum sama sekali. Mungkin memang sudah peraturannya kali ya kalau orang-orang yang bertugas di imigrasi ini nggak boleh senyum. Gue menyerahkan paspor gue dengan terlebih dahulu membuka case-nya karena bisanya mereka akan minta demikian. Ada juga sih yang nggak. Tapi daripada nanti repot pas di depan loket gue sudah membuka case-nya dari tadi di pesawat. Gue nggak memperhatikan siapa nama mbak-mbak itu. Setelah menyerahkan paspor gue, dia membolak-balik halamannya agak lama. Tumben selama ini? Gue pikir dia sedang mencari halaman yang ada Visanya. Pas gue bilag “Ada di halaman terakhir,” dia langsung memasang wajah ketus dan mengangkat telapak tangan ke arah gue sebagai isyarat “Stop talking I don’t need your explanation.” Gue makin deg-degan karena kayaknya memang dia nggak boleh diajak ngomong atau apa. Harusnya gue juga nggak sok ramah sih sama orang imigrasi. Harusnya cuekin aja.
“Ada urusan apa ke London?” dia bertanya.
“Kerja.” Gue memutuskan untuk menjawab pendek karena takut.
“Berapa hari?”
“Empat.”
“Kerja apa?”
“Liputan peluncuran handphone Honor.”
Dia kemudian memberikan stempel masuk di atas Visa UK gue dan mengembalikan paspor itu lalu bilang “Have a nice trip.” Gue bilang makasih sambil senyum tipis lalu melanjutkan menggeret koper merah menuju pintu kedatangan.
Gue nggak buka WhatsApp lagi setelah pihak penyelenggara nggak membalas perihal sopir yang akan menjemput gue tapi di depan pintu kedatangan, gue mencoba mencari orang yang kira-kira akan membawa kertas bertuliskan nama gue. Biasanya kan gitu ya kalau dijemput sama orang yang di-hire untuk pick up guest di bandara. Walaupun awalnya gue kira gue mengkhayal, tapi ternyata beneran ada yang membawa kertas bertuliskan nama gue. Walaupun typo. Mereka mengetik ATMI jadi ATIM. Sebel sih. Nama ATMI aja sudah membuat gue dikira cewek oleh banyak sekali orang sejak gue SMP sampai kuliah. Sekarang malah dibikin typo jadi ATIM yang gue sama sekali enggak tahu lagi deh sesusah itukah mengeja nama yang cuma empat huruf.
“Hi, thats my name on your paper,” kata gue ke orang itu.
Yang datang menjemput gue posturnya tinggi dan berewokan. Dia pakai jas warna hitam dan rapi banget. Tipikal orang-orang yang ditugaskan untuk menjemput ke bandara. Waktu gue ke Korea juga penampilan penjemputnya kayak gitu. Dari wajahnya gue bisa menyimpulkan kalau orang ini pasti muslim. Tapi gue nggak bisa menebak berapa usianya.
“Ah, you’re Mr. Atim?” katanya.
“No. Actually, you had typo on my name there,” kata gue.
“Really? Can I see your passport? Sorry sir, just to make sure I’m not picking up the wrong person. It happened a lot, you know,” katanya.
OH SHIT. GUE AKHIRNYA BENERAN DENGERIN ORANG NGOMONG PAKE LOGAT BRITISH! HAHAHAHAHA.
“Yeah sure,” gue menyodorkan paspor gue dan dia ngecek foto gue lalu ngeliat muka gue. Lalu dia ngeliat kertas yang dia bawa dan sadar kalau dia memang typo. Untungnya dia nulis nama gue lengkap bagian depan, tengah, belakang. Jadi dia bisa memastikan kalau yang dia jemput ini, yang barusan nyapa dia ini, adalah beneran MR. A. AHSANI YUSRON. Bukan orang lain.
“Alright. Welcome to London, sir. My name is Noor. Follow me,” katanya.
Gue agak kesulitan menyamakan langkah dengan Noor karena posturnya yang tinggi langkahnya jadi lebar-lebar. Berkali-kali koper gue nabrak bagian belakang sepatu gue dan bikin gue nyaris jatuh. Pintu kedatangan bandara terbuka dan gue bisa merasakan angin dingin musim semi di kota London yang, yah, nggak terlalu parah. Nggak separah waktu pertama kali pintu kedatangan bandara Incheon terbuka dan kulit gue merasakan 0 derajat celcius untuk pertama kalinya. Suhu pagi itu sekitar tujuh atau delapan derajat celcius. Belum ada apa-apanya. Gue pernah minus 11 di Korea tahun lalu jadi ini masih hangat lah. Gue membatin.
“It’s still cold, walaupun sudah spring. Tapi sore bisa jadi agak hangat. Langit London memang selalu kayak gini, bisa jadi hujan bisa jadi enggak. Mobil kita ada di parkiran basement, sebentar ya, saya bayar parkir dulu,” katanya.
Setelah itu kami jalan lagi menuju mobil warna hitam yang mewah banget. Dia masuk untuk membuka pintu bagasi belakang lalu keluar lagi dan membantu gue untuk mengangkat koper yang sebenarnya nggak terlalu berat itu lalu memasukkannya ke bagasi mobil.
“Anda masuk saja, biar ini saya yang urus,” katanya. Gue sebenarnya nggak mau terlalu manja gini tapi karena itu sudah bagian dari kerjaan dia jadi yaudah manja dikit nggak apa-apa. Gue masuk dan duduk di kursi belakang, menarik napas panjang dan lega karena gue nggak harus repot-repot naik kereta dari Heathrow ke London. Walaupun sebenarnya naik kereta pasti akan memberikan pengalaman yang berbeda sih. Tapi kalau ada mobil yang nyaman, kenapa nggak disyukuri saja? Hehe. Sebenarnya bisa juga sih gue pesan Uber dan bayar pakai uang kantor. Tapi ya sekali lagi fasilitas dari sponsor ini sebaiknya dimanfaatkan dan disyukuri saja.
“Berapa lama dari bandara ke kota?” tanya gue basa-basi. Gue masih belum terbiasa dengan ngomong Inggris jadi agak lama juga gue mikir untuk mengeluarkan kata-kata itu. Mungkin efek ngantuk.
Mendengar pertanyaan itu Noor malah tertawa. “To the city?” katanya seolah-olah pertanyaan itu aneh. Gue berpikir bagian mana anehnya tapi nggak nemu. “Well, kalau maksud Anda to the city-nya London, ya sekitar tiga puluh lima menit. Tapi itu kalau nggak ada traffic. Kalau ada traffic mungkin bisa satu jam. Man, di sini traffic-nya parah banget. Ini hari Senin dan orang-orang sudah hectic sejak pagi. Jadi mungkin kita akan terjebak macet di jalan dekat-dekat hotel,” katanya.
“Yah, macet-macetnya di sini nggak semacet Jakarta lah. Jakarta macetnya parah banget, kamu harus lihat,” kata gue.
“Oh ya?”
“Ya. Jakarta itu kota termacet di dunia. Yah paling enggak salah satunya deh,” kata gue lagi. “Oh ya, are you muslim?” gue akhirnya mengajukan pertanyaan yang dari tadi gue pikirin itu. Alasannya sebenarnya karena gue sedang memikirkan bagaimana puasa di London. Karena bisa jadi di tengah-tengah perjalanan ini nanti gue akan menjalani puasa hari pertama di sini.
“Yes, I’m a muslim. I’m from Pakistan,” katanya.
“Glad to know! I’m also a muslim. So Noor, tell me about fasting in London,” kata gue to the point.
“Oh man, fasting in here is hard,”
Wah anjir gue jadi makin deg-degan. Tadinya gue berharap jawaban yang tidak membuat gue takut melewati hari pertama di sini. Tapi jawaban dia malah bikin gue jadi jiper. Sebel.
“Really? Separah apa? Denger-denger di sini puasanya 17 jam?”
“17? Ahahaha,” dia ketawa kenceng. “Not 17 man, its 19 freaking hours! Subhanallah...” lanjutnya. Dia lalu melanjutkan bagaimana awalnya dia pindah ke London dan sudah berapa lama dia tinggal di sana. Dia juga bilang sejak dia tiba di London puasanya belum pernah kurang dari 19 jam. “Mungkin yah nanti tiga puluh tahun lagi kita di London bisa merasakan puasa 17 jam itu,” katanya penuh harap.
Dia kemudian cerita soal istrinya yang adalah orang Hungaria. Mereka ketemu beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah punya satu anak. “Dia bukan muslim tapi saya nggak pernah mencoba untuk memaksanya masuk Islam,” kata Noor. Dia cerita nama anak pertamanya Adam dan dia sempat juga nunjukkin foto anaknya. Lucu banget sih paduan antara Eropa sama Pakistan gitu. Gemes banget! Dia cerita lagi kalau anaknya sekarang lagi bawel-bawelnya. Terus kemudian dia bilang kalau punya pasangan dan punya anaklah yang bikin dia jadi bisa survive di London dan semangat buat kerja.
“Cari kerja di sini susah. Apalagi yang gajinya lumayan. Saya pernah kerja jadi tukang delivery makanan tapi cuma betah beberapa bulan aja. Soalnya gajinya kecil dan capek banget. Itungan gajinya kan tergantung sebanyak apa kita antar makanan. Jadi bisa dapat lebih kalau antar makanannya juga sering. Tapi kondisi jalanan kadang-kadang bikin sebel dan malah buang-buang waktu,” cerita dia. Kelanjutan cerita itu berujung ke akhirnya dia ngasih tahu umurnya berapa.
“SERIUS?!” kata gue nggak percaya ketika dia bilang usianya 27 tahun. ANJIR GUE JUGA 27 TAHUN TAPI KOK GUE MERASA NOOR TUA BANGET SIH?! APAKAH KARENA PENAMPILAN DAN JENGGOTNYA? BUKAN MAKSUD RASIS TAPI BENERAN KELIHATANNYA KAYAK 35!
“Ya! Memangnya Anda pikir usia saya berapa?”
“35!”
“Haha! Enak aja! Saya masih 27 kok,”
“Terus, kamu menikah usia berapa?”
“25 kalau nggak salah. Ya dua tahun yang lalu lah. Anda sudah menikah?”
“Not yet,” kata gue tegas dan cepat. Gue nggak mau membahas pernikahan dengan orang asing yang baru gue temui dan mungkin nggak akan gue temui lagi. Apalagi membahasnya dalam bahasa Inggris dengan logat British yang kental.
“Anda harus menikah karena sudah 27. Serius deh, menikahlah, semua akan jadi lebih gampang setelah menikah,” kata dia.
YA OKE BAIK.
“Pray for me, ok?” gue ketawa getir. Bahkan orang asing ini aja menyuruh gue untuk segera menikah. Gue jadi inget Afif yang selalu ingin cepat menikah dan encourage people to get married early too. Gue jadi ingat obrolan gue dengan mantan teman sekamar gue di tempat makan soto di depan kantor lama gue. Dia pernah bilang dia mau nikah muda karena ingin punya anak sebelum dia berusia 25 atau 30 gue nggak inget. Gue sendiri sebenarnya dulu punya target menikah di usia 25. Dulu... sebelum gue tahu bagaimana dunia yang sebenarnya. Gue dulu ingin punya anak sebelum usia 27. Dulu... sebelum gue tahu bagaimana dunia yang sebenarnya. Dan sekarang, target-target itu berubah. Dan gue sama sekali nggak tertarik untuk membicarakan pernikahan untuk saat ini. Mungkin nanti setelah 35 seperti kata gue ke nyokap beberapa waktu lalu. Mungkin nanti setelah semua mimpi gue sudah terwujud dan gue sudah siap untuk pulang kampung dan settled di sana.
“Rumah-rumah di sekitar sini dijual murah banget. Tapi tetap enggak laku,” katanya.
“Lho kenapa?”
“Ya karena lokasinya deket banget sama Bandara,” katanya lagi.
Aneh, biasanya rumah yang deket Bandara kalo di Jakarta atau Lombok at least jadi salah satu nilai jual.
“Saya pernah ditawari satu rumah di dekat sini tapi saya tolak. Soalnya berisik banget. Setiap hari harus mendengarkan suara pesawat datang dan pergi, naik dan turun di Bandara. Stres banget! Gimana bisa hidup dengan suara berisik kayak gitu?” kata dia.
“Really?”
“Berisik banget deh!”
Mungkin karena efek gue lagi di dalam mobil jadi nggak terlalu mendengarkan suara pesawat dari kita keluar kompleks Bandara tadi. Makanya gue agak tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Noor. Hahaha. Aneh juga kalau gue nggak percaya sama orang yang tinggal bertahun-tahun di London. Sementara gue baru tiba di sana belum juga sejam setengah. Nggak lama setelah Noor menjelaskan perihal rumah-rumah kosong itu, gue kebetulan sedang meng-Instagram Stories-kan perjalanan gue di mobil saat itu, sebuah pesawat melintas di atas kami.
“Lihat itu! Lihat!” katanya menunjuk ke atas. Kebetulan bagian atap mobil itu transparan karena ada kacanya dan bisa dibuka. Tadi dia sempat menawarkan gue untuk membuka atap itu tapi gue bilang nggak usah repot-repot. Dan pas dia menunjuk ke atas, gue mendongak dan mengerti apa yang dia omongin sejak tadi. Pesawat yang turun ke Heathrow jaraknya deket banget sama kepala. Pantesan orang-orang ngerasa di sini bising banget.
“Saya nggak pernah ngeliat pesawat terbang serendah itu di atas kepala,” kata gue sambil ketawa.
“Itulah kenapa orang-orang nggak mau tinggal di deket Bandara,” katanya. “Ah, kita sudah sampai di lokasi macet,” lanjut Noor. Gue melihat ke depan dan memang sudah ada barisan mobil-mobil di jalanan yang nggak selebar jalanan di Jakarta. Waktu berhenti di persimpangan yang ada lampu lalu lintasnya, dia sempat menunjuk sebuah tiang lampu lalu lintas yang dipenuhi oleh bunga-bunga. “Biasanya di sini kalau ada yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, lokasinya akan dikasih bunga-bunga kayak gitu. Sepertinya ada yang baru kecelakaan dan meninggal di sini. Itu lihat bunganya masih segar,” kata dia.
Gue hanya menanggapi dengan “Oh.” Saja sampai akhirnya dia minta maaf kalau-kalau dia terlalu banyak bicara. Gue bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang lagi kalau mau tidur nggak apa-apa karena masih lama juga ini sampai ke hotel. Tidur aja kalau capek. Gue menerima tawaran itu dan menyandarkan kepala gue ke sandaran kursi. Tapi pemandangan di luar bener-bener bikin gue nggak bisa tidur. Walaupun cuma gedung-gedung aja, tapi gedung-gedungnya sangat menarik untuk dilihat dan dipotret. Gue nggak mau repot-repot memotret dengan kamera digital yang ada di ransel di sebelah gue dan cuma memotret lewat Jeno saja. Karena gue lupa men-setting Jeno dalam mode diam, suara jepretan kameranya terdengar keras di dalam mobil.
“I will take 2 pounds for every picture you taken,” katanya bercanda.
Gue ketawa dan terus memotret.
“Kalau Anda nggak jadi tidur, saya mau menjelaskan lokasi yang kita lalui,” kata dia.
“Yeah, sure, go on!” jawab gue.
Sebenarnya semua yang dia omongin nggak juga gue ngerti. Efek ngantuk beneran tapi nggak bisa tidur juga. Mungkin juga karena gue agak susah menangkap logatnya dan belum terbiasa dengan orang-orang yang bicara dengan logat Inggris kayak gitu. Tapi Noor menjelaskan setiap persimpangan dan setiap gedung. Terutama ketika kita melewati sebuah pusat perbelanjaan yang katanya paling mahal di Inggris.
“Beli kaca mata di situ bisa 500 pound! Gila aja! Kaca mata saya aja harganya cuma 30 atau 35 pound! Saya kalau ke situ cuma lihat-lihat aja terus nanti cari yang mau di beli di tempat lain. Lebih murah. Di mall itu mahal banget amit-amit,” kata dia.
Hampir semua bangunan besar di sepanjang jalan yang mobil kami lewati punya arsitektur khas Inggris yang mirip seperti bangunan-bangunan dari masa lalu. Termasuk mall yang dimaksud oleh Noor tadi. Apartemen-apartemen dan toko-toko yang ditunjukkannya (“Ini adalah daerah mahal juga. Jangan makan di sini karena beneran bikin bangkrut!”) juga punya desain arsitektur yang serupa. Beginikah London? Semua bangunannya seindah ini? Nggak heran banyak artis Kpop ke sini cuma buat pemotretan majalah dan pemotretannya pun cuma di pinggir jalan. Ternyata memang pinggir jalannya sebagus itu. Semua tempat kayaknya Instagram-able deh! Semua persimpangan sangat indah untuk difoto.
“Sebel nggak sih sama macetnya?” kata dia. Padahal itu sama sekali nggak macet lho menurut gue. Mampang Prapatan tuh baru macet!
“Nggak apa-apalah, jadi bisa lihat-lihat lebih lama,” kata gue.
“Hotel tempat Anda tinggal ini, wah, bagus banget lho! Lokasinya strategis banget. Persis di pinggir sungai Thames dan di sebelah Tower Bridge! Ini hotel mahal karena strategis. Kawasan ramai juga karena banyak kantor. Anda beruntung sekali,” katanya. Gue balas dengan senyum yang di lihat dari cermin dasbor. Ketika adegan itu terjadi, mobil kami sedang melewati sisi lain dari Sungai Thames dan gue bisa melihat London Eye dari kejauhan. Gue senyum-senyum sendiri karena akhirnya bisa melihat landmark yang biasanya gue lihat di internet dan salah satu film India yang diperankan Hritik Roshan sama Rani Mukherjee.
Gue menyandarkan kepala lagi dan memejamkan mata sebentar. Sepuluh menit aja nggak apa-apa deh yang penting tidur.
Entah apakah gue beneran tertidur atau tidak, tapi ketika gue membuka mata, Noor sudah parkir di depan The Tower Hotel.
“Anda sudah sampai, sir,” katanya.
Gue membuka mata dan menggeliat. Melihat ke sebelah kanan dan kiri lalu pintu terbuka lebar. Gue tersenyum.
Petualangan dimulai.

Follow Me/KaosKakiBau in everywhere!
Watch my #vlog on YouTube: KaosKakiBauTV (#vron #vlognyaron)
Twitter: ronzzykevin
Twitter: ronzzykevin
Facebook: fb.com/kaoskakibau
Instagram: ronzstagram / roninredconverse / roningrayscale
Line@: @kaoskakibau (di search pake @ jangan lupa)
Photos from personal library.
Photos from personal library.
Tags:
Experience
London





















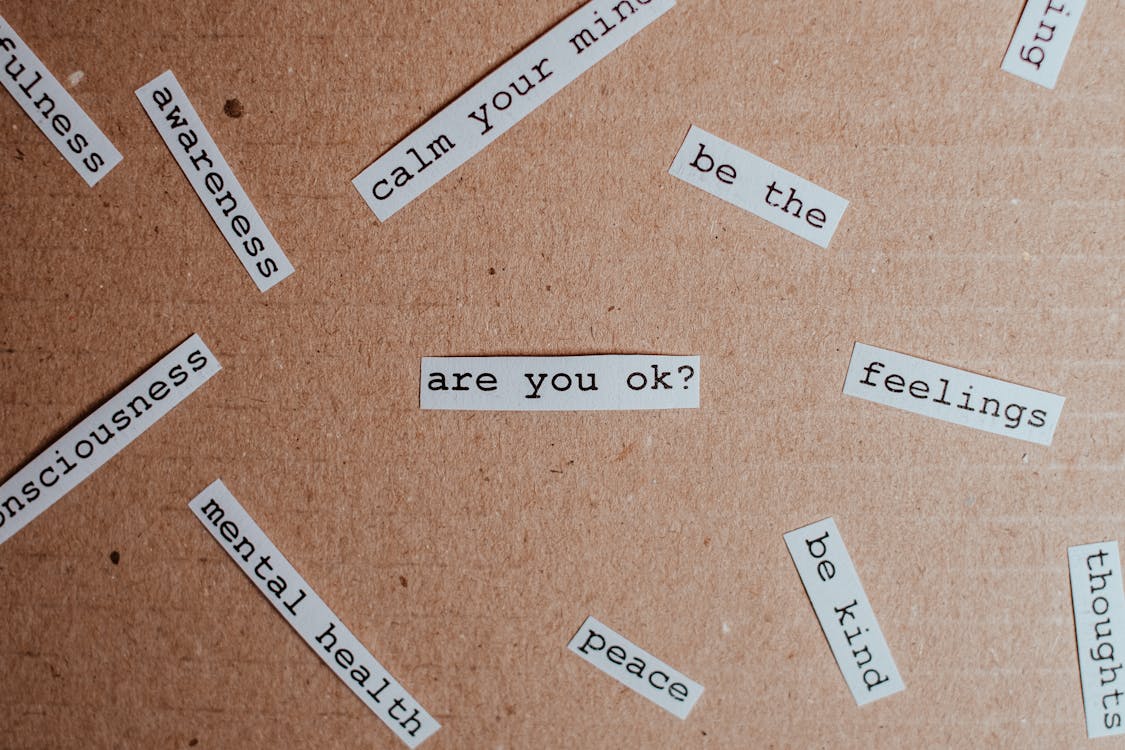









0 comments