Ujian Kemampuan Bersosialisasi
“Malam ini ke mana? Keluar yuk, bosen nih.”
Gue kirim pesan itu ke Lola, teman karib gue sejak SMA. Gue lagi di Lombok by the way, lagi libur Lebaran setelah dua tahun terakhir gue Lebaran di kosan sendirian aja karena pandemi. Sekarang setelah tiga kali vaksin gue rasanya lebih berani pulang-pergi ke kampung halaman. Di 2022 ini aja gue udah tiga kali pulang saking beraninya.
Hari itu Sabtu. Gue sejak beberapa hari terakhir cuma tidur-tiduran saja di rumah karena menikmati waktu kosong tanpa bekerja dan nulis artikel. Ada beberapa artikel yang harus gue kerjakan Sabtu ini tapi gue akan free di malam harinya. Jadi gue pikir sepertinya akan menarik kalau gue ngajak Lola buat pergi-pergi. Dia bukan orang yang ribet buat diajak pergi-pergi dan selalu mau.
Geng SMA gue ada lima orang termasuk gue. Empat yang lainnya perempuan dan tiga di antara mereka sudah nikah. Lola masih sendiri dan gue selalu sendiri karena memang gue tidak ada keinginan sama sekali buat berumah tangga. Jadilah gue sama Lola sering banget main bareng kalau gue lagi pulang kampung. Sudah cukup lama juga kita nggak ketemu karena pandemi. Jadi mumpung gue lagi di rumah, gue jadi agak clingy sama dia dan ngajak-ngajak dia terus seolah-olah dia nggak punya kerjaan lain. WKWKWKWKWKKW. Gue nggak bisa ngajak temen-temen segeng gue yang lain karena sudah berkeluarga. Tahu diri aja gue nggak mungkin ngajak ibu-ibu nongkrong di kafe sementara anaknya dibiarin sama suami kan. Di titik ini gue sedang merasa bahwa gue tidak bisa seperti mereka yang mengemban tanggung jawab sebesar itu. Jadi gue lebih menikmati waktu sendiri gue saja bersama orang-orang yang sendirian juga seperti Lola.
Tapi malam itu rupanya Lola nggak sedang sendirian.
Sial.
“Yah udah ada rencana. Kamu nyusul aja ke Kava? Saya mau ketemu orang,” balas Lola yang anehnya nggak bikin gue jadi kecewa tapi justru bersemangat. Terakhir kali kita ketemu, dia lagi getol-getolnya mencari pasangan soalnya.
“Siapa???? Cowok????” tanya gue dengan nada 100 persen kepo meski dalam tulisan singkat di WhatsApp.
“WKWKWKW iya,” jawab Lola.
“Yah obat nyamuk dong gue!”
“Ya duduk di meja lain aja,”
“Masuk akal juga. Ya sudah sekalian saya mau nyelesein artikel. Masih ada utang satu.”
Normalnya orang-orang di Lombok, di Mataram, ngomongnya pakai Saya-Kamu. Tapi kalau di WhatsApp (dan kadang-kadang juga di kehidupan nyata sih) gue suka keceplosan ngomong Lo-Gue. Dulu waktu SMP, ada temen gue dari Jakarta yang sering banget kalo SMS-an pake Lo-Gue dan gue pun jadi keikutan bahasa SMS itu. Tapi kalau sama orang lain ngomongnya tetap Saya-Kamu (atau dalam bahasa SMS jadi aq-qm).
Biasanya gue malas kalau mau ketemuan sama temen, terus dia lagi ada agenda ketemuan sama orang lain. Alasannya simpel aja: gue orangnya nggak jago basa-basi. Itulah kenapa gue males banget harus pindah-pindah kerja karena harus bersosialisasi dari nol sama orang-orang baru. Harus mulai menempatkan diri di tengah “masyarakat” yang baru dan itu cukup melelahkan buat gue. Ya sebenarnya sih ini nggak bisa juga dibiarin terus-terusan kayak gini karena pada akhirnya gue jadi nggak berkembang dan nggak bergaul. Tapi kalau ada dua pilihan, (1) gue harus bergaul dengan orang baru, dan (2) gue harus diem seminggu di kosan nggak keluar-keluar; gue akan lebih memilih opsi kedua.
Gue suka kenalan sama orang asing tapi gue bukan tipe orang yang jago memulai pembicaraan atau nyari topik obrolan. Kecuali dalam situasi tertentu kayak misalnya lagi backpacker-an atau lagi nginep di hostel di luar negeri itu, kemampuan berkomunikasi gue jadi jauh lebih baik karena mungkin ada kebutuhan buat survive di negara orang kali ya? Kalau areanya Jabodetabek atau Mataram kayaknya gue mending di kosan/rumah aja deh. Bikin kopi item pake es batu terus nonton ulang Heartstopper sampai bego.
Gue kepo sama orang yang bakal ditemui oleh Lola ini. Teman-teman segeng gue yang lain, dulu ketika mereka pacaran pas SMA, gue tahu siapa pacar mereka. Gue tahu mereka baru putus dari siapa dan akhirnya dapat pacar baru yang mana. Setelah beberapa dari mereka menikah, gue cukup tahu siapa suaminya lalu sudah sampai situ saja. Gue nggak lagi ingin tahu apapun yang sedang mereka hadapi atau terjadi dalam hidup mereka kecuali mereka yang memulai cerita. Satu dari tiga temen gue yang sudah nikah itu kebetulan masih sering main juga sama gue dan Lola jadi sedikit banyak gue lebih tahu perkembangan kehidupan dia setelah berumah tangga, gue juga akrab dengan suaminya, dan kita bisa ngobrol santai kalau lagi kumpul-kumpul kayak bukber misalnya.
Dengan alasan kepo inilah gue akhirnya setuju buat ketemu Lola di sebuah kafe bernama Kava, kafe kekinian milik sebuah developer perumahan kenamaan di Mataram. Lokasi kafe ini agak ujung dan jauh dari pusat kota tapi setiap malam Minggu, semua orang dari penjuru kota ini tumpah di sana sekadar ngopi dan mendengarkan live music yang menyanyikan lagu-lagu populer di TikTok yang mana gue sama sekali nggak tahu itu lagu apa. Ketika gue tiba di sana, gue agak shock dengan kebisingan kafe ini, keramaiannya di tengah pandemi, dan antrean di depan kasir yang mengular ketika mau pesan makanan atau minuman. Gue nggak pernah merasakan Mataram yang sehidup ini selama gue pulang tiga bulan terakhir. Ya alasannya karena gue selalu di rumah dan nggak pernah ke mana-mana.
“Saya di belakang.”
Lola mengirim pesan mengisyaratkan supaya gue nyamperin dia di kursi-kursi kayu yang ada di ujung belakang kafe itu.
Meski gue suka cafe-hopping, tapi tempat ramai kayak gini totally not my vibe. Pertama karena gue nggak akan bisa nemu meja kosong yang bisa gue tempati sendiri, kedua karena live music-nya kenceng banget dan gue sama sekali nggak bisa konsentrasi buat melakukan apapun yang ingin gue lakukan sendiri (misalnya nge-blog atau kerja), ketiga karena lagu yang dinyanyiin sama band-nya gue nggak tahu sama sekali, maafin banget. Ketika gue akhirnya menemukan tempat duduk Lola, band-nya sedang memainkan lagu Seperti Mati Lampu dan semua orang ikutan nyanyi dan berteriak kenceng-kenceng menikmati lagu dangdut itu.
Gue melihat Lola duduk dengan dua orang cowok. Cukup kaget karena dua-duanya kelihatan beberapa tahun lebih tua. Gue nggak suuzon. Nggak kok. Gue cukup tahu Lola bukan tipe-tipe sugar baby. Gue lebih pengin jadi peliharaan orang kaya daripada dia. Gue justru suuzon sama diri gue sendiri. Bisa nggak nih gue berinteraksi dengan orang-orang yang baru gue kenal ini dengan baik?
Mungkin kalau gue bilang gue socially awkward banyak orang akan nggak percaya. Tapi serius deh dua tahun pandemi ini bikin kemampuan sosialisasi gue benar-benar jelek. Beberapa bulan yang lalu gue kenalan sama orang lewat aplikasi kencan dan kita sempat tuker-tukeran akun LINE. Sebulan pertama betah banget gue chat dia dan kita balas-balasan hal-hal gak penting di chat. Tapi setelah itu kita seperti kehabisan topik dan gue seperti nggak bisa menemukan topik untuk dibicarakan. Sekarang gue nggak pernah lagi menghubungi dia dan dia pun nggak lagi mengirim pesan ke gue.
Gue berjalan menuju meja tempat Lola dan dua cowok itu duduk. Satu pakai topik hitam duduk di sebelah kanan Lola, satu duduk di sebelah kiri Lola rambutnya ikal agak panjang dan disisir klimis ke belakang.
“Kenalin ini Reno, ini (gue lupa siapa tapi sebut saja) Ari,” kata Lola.
“Halo, Ron,” gue menjabat tangan masing-masing.
“Reno ini kakak iparnya Jaya, temen SMA kita itu,” Lola menjelaskan.
“Oh wow, ternyata bener ya Mataram ini sempit,” gue ketawa kecil.
Sebelum ini gue pernah bilang ke Lola sesuatu tentang Mataram yang sempit. Gue merasa orang-orang yang tinggal di sini selalu ada di sini dan nggak banyak yang pindah ke luar kota atau tiba-tiba menghilang dari peredaran. Orang yang gue temui secara random di satu event bisa jadi adalah orang terdekat teman SMP atau SMA gue. Persis seperti yang terjadi ketika gue ketemu sama Reno malam itu. Tapi, gue bilang juga ke Lola, sesempit-sempitnya Mataram, gue nggak pernah sama sekali ketemu secara tidak sengaja dengan orang-orang yang benar-benar ingin gue temui. Kayak misalnya orang yang gue taksir pas SMP atau kakak kelas gue pas SD yang setiap jam pelajaran olahraga dia gue liatin terus sampai bego.
Gue duduk dan langsung bingung buat memulai obrolan. Kata orang kan go with the flow aja ya? Tapi gue pun tidak tahu sebenarnya ada flow nggak sih di obrolan ini. Sementara itu lagu Seperti Mati Lampu makin kenceng dan makin heboh. Di belakang kita ada satu meja yang isinya tiga cewek berhijab yang sejak gue muter-muter nyari Lola sampai gue duduk terlihat sibuk dengan kamera handphone-nya buat bikin konten TikTok. Kayaknya dia lebih capek dari mas-mas vokalis band.
Gue memutuskan untuk nimbrung antre di depan kasir sebelum mulai nimbrung obrolan Lola, Reno, dan Ari. Gue butuh kopi. Gue lihat ada Irish Coffee di daftar menu digital yang gue lihat setelah scan barcode di meja dan itu adalah menu kopi kesukaan gue. Ketika jalan ke lokasi antrean gue mulai merasa rikuh dan semakin tidak menyukai kafe ini karena keramaiannya. Gue merasa orang-orang seperti ngeliatin gue padahal sebenarnya nggak. Gue merasa rambut gue kayaknya belahannya salah deh. Kayaknya celana gue ada bagian yang tiba-tiba berlubang. Apakah tadi gue duduk di bekas whip cream terus putih-putihnya nempel di bokong celana gue? Kerah gue miring nggak sih? Kaca mata gue kayaknya agak serong ke kiri bawah deh ini. Masker gue mana? Oh iya di sini kan nggak ada pandemi.
“Mau pesan apa?”
Overthinking gue buyar. Terima kasih mbak-mbak kasir.
“Kopinya semua ada, atau ada yang nggak ada?” tanya gue.
Gue selalu mengajukan pertanyaan seperti ini setiap kali pesan makan karena gue tipe yang nggak suka ditolak gitu. Kayak misalnya gue mau pesan kopi A terus kata mbaknya kopi A kosong, lalu gue pesen kopi B, dia bilang kosong juga. Daripada gue kesal dan merasa apa yang gue pengin tidak tersedia, biasanya gue selalu tanya ke mereka dari menu yang ini mana yang sudah abis jadi gue nggak pesan yang itu/
“Semua ada,”
“Asik. Irish coffee satu ya. Bayarnya QRIS,”
Setelah ambil nomor meja dan struk, gue kembali ke Lola tanpa tahu obrolan mereka sudah sejauh apa. Ini adalah momen di mana gue harus memantapkan niat untuk mengikuti obrolan mereka seolah-olah gue paham.
Reno dan Ari orangnya ramah. Reno nggak terlalu banyak bercanda tapi bicara sesuai porsinya sementara Ari adalah tipe mas-mas yang suka lempar jokes nyerempet yang cringe. Gue nggak tahu apakah dia sudah bapak-bapak atau belum tapi jokes-nya jokes bapak-bapak banget. Kalau sekali per setengah jam dia melemparkan jokes seperti itu ya okelah nggak masalah, tapi dalam 10 menit kayaknya ada 5 jokes yang dia lempar dan semuanya tipenya sama. WKWKWKWKWKWKWKKWKWKW. Kalau malam itu gue yang berusia 25 tahun ngobrol sama Ari mungkin gue bakal emosian dan meninggalkan meja itu sesegera mungkin. Tapi gue yang usia 31 merasa, meski melelahkan, gue bisa menanggapi lelucon-lelucon ini seolah-olah gue ngerti.
Dengan segala pengalaman tidak menyenangkan gue pas SMA, gue nggak terlalu suka dengan jokes seperti ini apalagi di pertemuan pertama. Selain karena ada kesan ngenye’ gitu, kayak gimana sih menjelaskannya kayak nyerempet nyindir-nyindir yang cenderung menjelekkan gitu lah ya, entah siapapun objeknya; jokes seperti ini juga agak susah buat ditanggapi. Mau ketawa tapi nggak lucu, mau nggak ketawa tapi nggak sopan. Biasanya gue nggak pernah memaksa diri gue buat ketawa tapi malam itu seolah-olah gue baru lulus S3 jurusan Komunikasi bidang studi Jokes Masyarakat Sekitar jadi gue bisa menanggapi setiap jokes Ari dengan sarkas, tegas, dan bereaksi sesuai yang dia butuhkan.
Gue nggak tahu darimana gue bisa mendapatkan kemampuan ini jujur aja tapi setiap kali dia melempar jokes yang kayaknya agak nyerempet, gue balas lagi dengan hal-hal yang nyerempet. Menyenangkannya dari orang seperti Ari ini, mereka menerima itu sebagai sebuah lelucon juga dan nggak menanggapinya terlalu serius. Mereka tahu konteks dan mereka memang butuh balasan seperti itu sehingga memuaskan ego mereka juga yang sudah berusaha keras melempar jokes bertubi-tubi tadi.
Gue bukan lagi orang yang suka bercanda soal kurus, gemuk, tinggi, pendek, besar, atau kecil. Gue juga nggak pernah lagi bercanda soal umur. Di beberapa lingkaran pergaulan hal ini red flag banget. Tapi yang jadi red flag di satu pergaulan bisa jadi lumrah di pergaulan lain. Nah kurang lebih itu yang bisa menggambarkan situasi obrolan gue sama Ari, Reno, dan Lola malam itu. Meski gue bilang gue bisa menghadapinya dengan sangat baik, tapi jujur aja itu sangat melelahkan!
Contoh obrolan kami malam itu:
Ari ke Reno: Handphone yang rusak kemaren itu gimana tuh kabarnya?
Reno: Akhirnya nemu jeroan dari orang di Lombok Timur. Soalnya kalo servis di Samsung biayanya 3 juta. Mending beli handphone baru kan?
Ron: Handphone apa memangnya tipenya?
Reno: S8+
Ron: Wah saya suka tuh S8+ enak banget digenggamnya. Kecil terus panjang gitu.
Ari: (senyum-senyum genit) Oh yang kecil panjang gitu enak ya? Kalo besar pendek?
Ron: ... (butuh sepersekian detik buat memproses tikungan obrolan ini sebelum akhirnya) Ya beda orang beda kesukaan. Aku sih lebih suka yang kecil panjang kayak pas aja kalo digenggam (dengan menirukan posisi tangan agak jorok yang anehnya langsung bikin Ari ketawa).
Gue nggak terbiasa dengan situasi obrolan seperti ini terutama sama orang yang gue baru kenal. Tapi malam itu gue merasa gue mendadak sudah PhD untuk urusan obrolan-obrolan seperti itu. Biasanya gue akan menghindari topik seperti ini dengan pindah meja atau memisahkan diri dari orang-orang yang terlibat dalam obrolannya. Tapi malam itu gue merasa sudah jago.
Obrolan kami berlanjut sampai live band pamit. Sampai mbak-mbak berhijab yang ada di meja belakang kami sudah lelah dengan konten TikTok yang mereka buat (mulai dari lagu yang gue nggak tahu judulnya apa, Seperti Mati Lampu, sampai Hati-hati di Jalan-nya Tulus, semua mereka TikTok-in. Mereka adalah gue ketika Instagram Story baru dirilis). Sepanjang sisa obrolan itu, Ari nggak lagi terlalu banyak melempar becandaan ala dad jokes-nya mungkin dia sadar kalau dia butuh usaha lebih dan itu melelahkan. Obrolan kita pun berpindah soal Jakarta, pekerjaan, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gue coba buat menyelipkan obrolan soal K-Pop dan Korea (karena Lola yang mulai) tapi topik ini langsung drop karena tanggapan dua cowok-cowok itu seperti halnya cowok-cowok pada umumnya.
“Nggak suka Korea.”
“Padahal film Korea banyak lho yang bagus,” kata gue.
“Sukanya film action,”
“Film Korea ada banyak lho yang action,”
“...”
“...”
“...”
“Di sini nggak ada pandemi ya?”
Gue berkata sambil nyedot Irish Coffee berusaha mengalihkan pembicaraan. Meski masuknya agak kasar, tapi beruntung usaha gue berhasil.









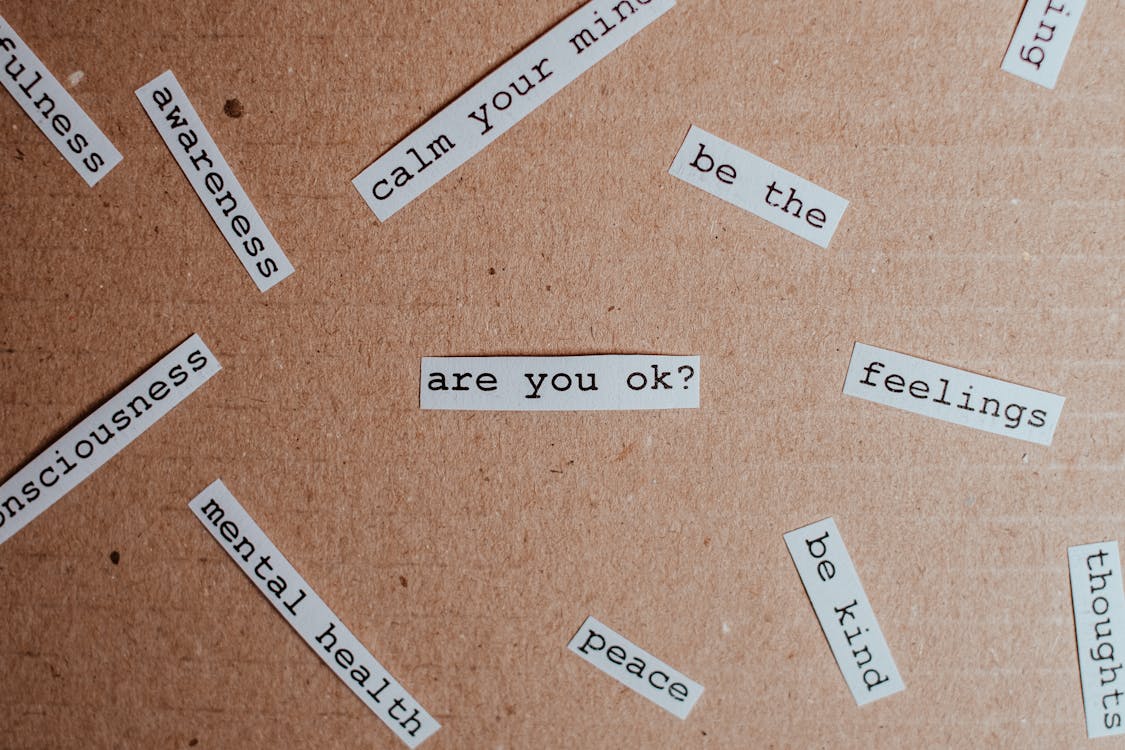









0 comments