Di Braga (Aftermath)
Gue menutup pintu kamar hotel itu dengan perasaan seperti mengambang. Gue tidak merasakan kaki gue menjejak di lantai sama sekali. Tentu saja, aslinya nggak gitu. Aslinya tetap menjejak. Gue kan bukan hantu dan nggak punya kekuatan levitasi sama sekali. Tapi indera perasa yang ada di telapak kaki gue seperti mati sesaat. Tadi lantai itu dingin. Dingin sekali. Tapi sekarang rasanya seperti kosong. Badan gue mendadak terasa sangat lelah. Obrolan yang lebih dari dua jam itu ternyata jauh lebih melelahkan daripada setengah jam yoga. Energi gue seperti terkuras habis, seperti yang gue prediksi, dan kelelahan seperti menguasai diri. Gue seolah nggak bisa lagi berpikir meski sebenarnya masih banyak hal yang harus gue pikirkan. Masih banyak hal dari obrolan gue malam itu yang perlu gue olah dan pilah. Tapi malam ini gue capek. Besok gue harus kembali ke Jakarta dan gue nggak mau membawa pulang perasaan aneh seperti ini.
Gue menjatuhkan tubuh ke kasur dan menyelinap ke dalam selimut. Meringkuk dan memeluk setiap ujung selimut yang bisa tangan gue raih. Kaki gue tertekuk di antara tumpukan kain untuk membuatnya terasa lebih hangat sedikit. Kepala gue setengah tertutup, hanya menyisakan sedikit ruang di jidat supaya napas gue bisa keluar dari sela-sela antara wajah dan kain selimut yang warna putihnya sudah sangat kusam.
Tarik napas. Embuskan.
Mantra gue hari ini nggak berubah. Gue masih lelah. Mungkin gue butuh tidur. Gue tadinya mau mandi supaya besok pagi bisa tinggal bangun siang terus berangkat ke stasiun. Tapi bahkan untuk melangkah ke kamar mandi saja gue udah nggak sanggup. Gue lebih baik tidur.
***
Gue menghabiskan satu jam di kafe di stasiun untuk menulis bagian satu dari cerita ini kemarin. Perasaan gue di siang hari itu sudah jauh lebih baik (setelah tiga gelas kopi; dua pas sarapan dan satu pas di kafe itu). Itu mungkin pertama kalinya gue nge-blog dan posting pakai Pedro. Pedro itu nama iPad gue. Gue tahu bahwa masih ada sisa perasaan semalam yang belum kelar dan di kalimat terakhir di posting-an itu gue bilang kalau mungkin gue akan menemukan jawabannya kalau sudah sampai di Jakarta nanti.
Setelah masuk ke dalam kereta dan duduk di kursi sesuai nomor tiket gue, gue sudah berusaha untuk tidur. Gue lebih baik tidur daripada harus menyibukkan pikiran gue dengan hal-hal yang masih abu-abu. Masih belum tahu jawabannya apa. Tapi entah kenapa sore itu rasanya gue sudah kelamaan tidur sepanjang malam dan pagi jadi seger bugar banget sampai gue sempat googling nama salah satu stasiun yang gue lewati dan gue nggak familier dengan namanya.
“I’m better than that...”
Lagu Destiny’s Child yang Survivor masih gue dengarkan dalam mode repeat-one. Kalau dipikir-pikir, momen di kereta itu sebenarnya sangat pas untuk nangis karena biar ada kesan grande gitu. Tapi sore itu, meski harus gue akui perasaan gue sudah penuh dan dada gue agak sedikit sesak dengan emosi (dan perasaan-perasaan yang gue belum mengerti apa), otak gue memaksa semua organ-organ yang memproduksi air mata untuk tidak bekerja. Mungkin mereka tahu waktu yang tepat. Mungkin bukan di kereta ini.
Tarik napas. Embuskan.
Pelan-pelan gue membuka satu demi satu halaman dari kejadian kemarin di dalam kepala gue. Kejadian satu hari sebelumnya. Kejadian dua hari sebelumnya. Sampai di hari ketika rencana akhir pekan ini dibuat. Apakah mungkin ada sesuatu yang membuat gue pada akhirnya bisa merasakan emosi-emosi dan unexplained feelings kayak gini? Kenapa masih ada hal dari kejadian akhir pekan lalu yang nyisa di sudut kepala gue, mengganggu ketenangan hati gue, dan kenapa gue nggak bisa menerka-nerka apa perasaan itu dan kenapa perasaan itu ada.
Sesampainya gue di Stasiun Gambir pada Minggu petang, gue langsung menggeret koper kecil gue ke halte TransJakarta. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang perjalanan itu karena gue sendiri nggak yakin kalau rute yang berbulan-bulan lalu gue ambil masih beroperasi hari ini. TransJakarta sedang melakukan revitalisasi di beberapa halte mereka sehingga jalur yang dulu biasanya gue ambil sekarang harus berubah, dan malam itu gue nggak tahu apa lagi yang berubah (dan gue nggak mau peduli karena sudah terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup gue belakangan ini dan bodo amat dengan rute lu yang berubah @TJ).
“I’m better than that...”
Sepanjang perjalanan pulang itu gue masih memutar satu lagu, sengaja supaya gue bisa tetap fokus untuk menerjemahkan perasaan yang sedang mengganjal itu. Setelah satu setengah jam perjalanan dari halte TransJakarta Gambir 2 sampai kosan gue, rupanya gue masih belum juga bisa mengerti apa perasaan itu. Gue nggak suka sama sekali merasakan hal ini. Gue hanya ingin semua jadi lebih sederhana. Kalau ini marah, ya sudah gue akan marah. Kalau ini kecewa, bilang aja jadi gue bisa kecewa. Kalau ini emosi yang lain, kasih tahu gue jadi gue bisa mencari cara untuk menanggulanginya.
Kabar baiknya adalah, meski gue sedang ditekan oleh perasaan-perasaan yang nggak bisa gue terjemahkan itu, nggak ada sedikitpun perasaan panik menyerang gue. Dulu biasanya di saat-saat seperti ini gue akan merasakan sensasi yang aneh, kewalahan dengan perasaan, kepala gue kayak muter-muter, ada banyak bisikan-bisikan yang gue dengar tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar mengatakannya kecuali kepala gue sendiri. Alih-alih panik, malam itu gue seperti diberi pilihan: gue bisa tetap mencari jawaban dan menjalani sisa hari itu; atau gue tidak berusaha sama sekali mencari jawaban dan terus menjalani sisa hari itu. Gue memilih yang kedua.
Sesampainya di kosan, gue butuh waktu sekitar satu jam untuk menyamakan frekuensi dengan sekeliling gue lagi setelah beberapa hari tidak tinggal di sana. Mendadak AC gue jadi nggak sedingin ketika gue tinggalin beberapa hari lalu, kasur gue masih nyaman, ada sudut berantakan yang harus gue beresin tapi gue lagi malas unpacking jadi gue memutuskan untuk goler-goler aja di kasur. Meski gue sudah memutuskan untuk tidak mencari jawabannya sama sekali, otak gue tetap memaksa untuk menelisik ke setiap kemungkinan yang mungkin saja merupakan hal yang gue cari dan jawaban dari pertanyaan gue. Mendadak gue rasanya capek banget dan memutuskan untuk mandi.
Mandi malam biasanya sepaket sama wudhu buat salat Isya dan melakukan skincare routine gue. Tapi setelah salat Isya, perasaan begajulan gue mendadak menyerang dengan sangat sangat sangat barbar dan nggak nanggung-nanggung. Sesaat lagi akan terjadi banjir air mata. Tapi untuk membuatnya jadi lebih dramatis, gue butuh backsound yang cocok. Gue meraih Keane, buka Spotify, dan cari satu lagu sedih.
Gue duduk dengan posisi lutut terangkat, siku ada di atas lutut, dan lengan menopang dagu.
Can't promise you the world when all i have is love...
I may not be the one your thinking of,
I may not fit your perfect dreams of love...
Won't you look into my eyes and see beyond the things I'm not, there's love inside of me...
Kemudian jawabannya datang begitu saja. Atau lebih tepatnya, jawabannya sudah ada dari tadi di sana tapi gue hanya belum yakin untuk mengiyakan dan membenarkan. Sejak tadi gue nggak bisa mengatakannya karena gue mungkin nggak terlalu siap, perasaan yang sebenarnya nggak perlu gue deny tapi gue benar-benar nggak mampu untuk menerimanya karena ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Lebih-lebih kemarin hal itu terjadi dua kali. Ternyata di usia 30 tahun ini pun gue masih tidak bisa menanggapi penolakan dengan biasa-biasa saja.
Ternyata penolakan tetap bisa bikin gue bercucuran air mata.
Lebih jauh dari itu, di balik penolakan-penolakan itu ada sebuah harapan dan imajinasi yang kejauhan yang pada akhirnya membawa gue terpuruk ke dalam lubang yang lebih dalam.
Ekspektasi.
Beberapa hari sebelum berangkat ke Bandung, ada banyak skenario-skenario halu nan bahagia di kepala gue yang mungkin bisa saja terjadi di antara pertemuan-pertemuan yang sudah direncanakan. Mungkin akan ada kesempatan buat gue kali ini untuk bisa menemukan seseorang yang cocok untuk berbagi. Mungkin ini adalah waktu yang sudah gue tunggu-tunggu yang pada akhirnya membawa gue ke jalan menuju kebahagiaan yang selama ini dibicarakan orang-orang. Mungkin ini waktunya.
Tapi itu hanya dalam kepala gue. Hanya sebatas ekspektasi dan harapan yang tidak jadi kenyataan. Terlalu banyak berharap memang berujung kekecewaan. Meski bukan berarti kita tidak lantas karena itu kita tidak usah saja berharap lagi. Yang lebih tepat mungkin menerima bahwa terkadang (atau seringkali) apa yang terjadi tidak selalu seperti yang kita harapkan.
Dan kalau mau lebih terdengar relijius lagi (yang mana sebenarnya kalau di blog tuh rasanya kayak gimana gitu kalo gue tulis): ini adalah jalan yang terbaik karena Tuhan tahu yang terbaik.
Belakangan ini gue sedang ada di fase yang bener-bener yakin banget sama rencana Tuhan. Bahwa semuanya tidak terjadi karena sebuah kebetulan. Bahwa kekecewaan itu bukan berarti sepenuhnya kecewa, tetapi hanya mempersiapkan lo untuk jadi lebih bijak, ketika pada akhirnya nanti tiba masa lo bahagia karena semua yang lo mau jadi kenyataan. Kekecewaan itu bikin lo jadi lebih humble dan membumi.
Belakangan ini gue bener-bener AKTF banget kalo kata fans DB5K. Always Keep The Faith. Pikiran dan keyakinan itu yang sejenak hilang dari kepala gue saat mengalami kejadian-kejadian akhir pekan lalu.
In the end gue tetap nangis.
"I'm better than that..." lirik lagu Survivor itu mendadak menyelinap di tengah lagu sedih yang sedang gue dengarkan.
Di satu sisi mungkin gue nangis karena gue merasa gagal. Gue merasa kecewa. Gue merasa bahwa perjalanan kemarin nggak ada gunanya. Tapi lebih dari itu gue nangis karena merasa sendiri. Gue butuh disemangatin. Gue butuh validasi dari orang-orang bahwa apa yang gue lakukan kemarin adalah hal yang paling baik dan gue sudah melakukan yang terbaik.
FYI gue kalo nangis tuh jelek banget. Kalau resting face gue aja udah jelek, kebayang kan nangisnya kayak gimana. Gue bukan tipe orang yang nangis dan berusaha untuk tidak membuat suara. Gue tipe yang drama kalo nangis jadi suaranya harus kenceng banget dan orang harus tahu gue nangis. Tapi malam itu gue memastikan bahwa suara tangis gue tertutup oleh volume lagu yang sedang gue dengerin itu.
Beyond the things I'm not, there's love inside of me...
Just love me for all things I am, love me...
The lighter side, the darkest side...
Try to love me for everything I am...
Jadi di sinilah gue, terduduk dalam balutan piyama SpongeBob SquarePants warna kuning, memangku dagu dengan tangan bertumpu di lutut, nangis kayak bocah nggak kebagian es krim di acara ulang tahun temennya yang tadi sore dia datengin.
Setelah sekitar lima menit mengerang-ngerang, tangan gue secara otomatis meraih handphone dan buka sosmed. Sebuah keputusan yang sangat-sangat tidak sehat dan bodoh. Gue ngetweet satu hal lalu gue hapus. Gue post satu Instagram Story dan tadinya mau gue apus ah tapi gue males biarin aja. Ternyata memang posting apapun di media sosial itu sama sekali nggak membantu.
“Oh gini rasanya jadi Baekhyun waktu berita pacarannya sama Taeyeon heboh di media. Jadi ini maksudnya ‘berkali-kali nulis, tapi gue apus, gue nulis lagi, gue apus’ itu,” gue membatin sambil terus mendramatisasi setiap tetep ais mata.
Akhirnya gue memutuskan untuk buka recent chat gue di WhatsApp dan menelpon salah satu temen gue yang Jumat kemaren gue temui di Bandung.
“Ul, masih bangun? Boleh gue telepon gak? Gue lagi butuh ngomong sama orang,” gue harus tanya dia dulu lewat chat karena gue tahu dia baru balik dari Kepulauan Seribu naik bus dan itu pasti capek banget. Setelah dia balas ‘iya, masih bangun’ dan ‘boleh telepon aja’, gue langsung pencet ‘call’ dan setelah dia angkat, gue mau tidak terdengar sedang menangis tapi nggak bisa. Nangis gue malah jadi lebih kenceng. Tapi cuma bertahan tiga menit karena setelah itu dia bikin gue ketawa kenceng banget dan... suddenly I feel better.
Maul memang ajaib.
Tarik napas. Embuskan. Tarik napas. Embuskan.
Satu hal penting yang gue sadari dari kejadian ini adalah bagaimana tubuh gue bereaksi terhadap penolakan. Apa yang terjadi kemarin adalah usaha tubuh gue untuk pura-pura kuat yang ternyata memang sangat melelahkan. Jadi kuat beneran aja udah melelahkan apalagi pura-pura, maksud gue tuh gitu.
Gue juga sadar bahwa dalam menanggapi dan menerjemahkan perasaan dibutuhkan waktu dan tidak perlu diburu-buru. Salah banget juga sebenarnya menahan diri untuk tidak mengeluarkan emosi yang sehat dengan menangis. Tapi mungkin tubuh gue tahu bahwa kalau gue nangis di kereta mungkin gue akan ribet dan bikin orang jadi bertanya-tanya (yang mana sebenarnya gue gak peduli juga sih tapi mungkin tubuh gue nggak mau gue malu jadi dia memilih untuk menahan diri). Padahal kalau gue nangis di kereta kan kesannya bisa kayak film sedih gitu. Abis ditolak langsung nangis dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Romantis sekali buat adegan film Visinema Pictures tahun depan.
Gue bukan orang yang malu-malu dalam urusan nangis atau berurai air mata. Ini adalah hal paling natural dan paling tidak menyakiti siapapun yang bisa tubuh gue lakukan untuk menyalurkan emosinya. Jadi gak perlu merasa ragu untuk itu.
Setelah menenggak obat tidur malam itu gue tidur nyenyak banget sampai bangun kesiangan. Sampai-sampai paginya gue lupa minum anti-depresan dan berangkat ke kantor dengan harapan hati gue kuat sampai waktunya gue bisa izin pulang.









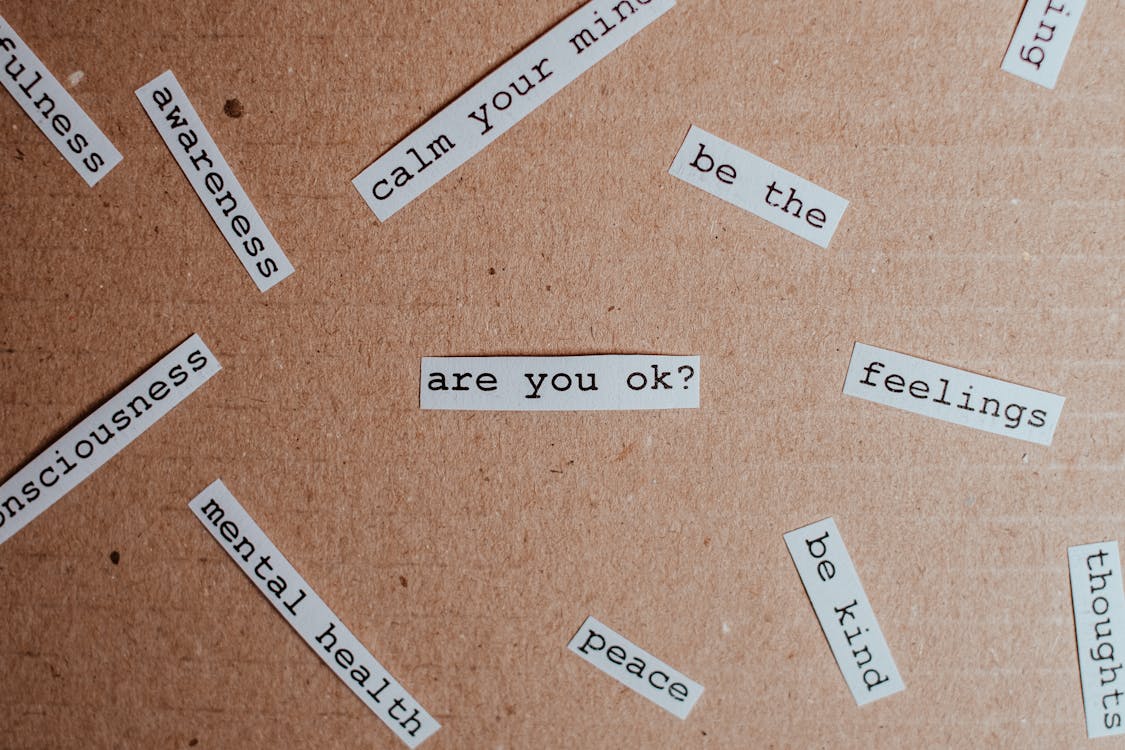









0 comments