Saya Ikut Bahagia
Gue nggak mau kepedean tapi gue harus bangga pada diri gue sendiri: gue udah mulai bisa membentengi hati dari kebucinan. WKWKWKWKKW. Lucu banget rasanya ngomong gini seolah-olah nggak akan ada apapun di dunia ini yang akan bikin gue bucin sepanjang sisa hidup gue. Tapi karena sekarang gue sedang fokus menjalani ‘hari ini’ jadi gue juga akan fokus untuk menghargai pencapaian gue ‘hari ini’. Di beberapa tulisan sebelumnnya, gue pernah cerita soal bagaimana gue bucin di usia 30. Sekarang, dua tahun berselang dari tulisan itu (kayaknya, atau mungkin udah tiga tahun), gue bisa dengan percaya diri bilang kalau gue sudah move on dari perasaan-perasaan bucin itu. Semua berawal dari seonggok daging hidup yang kita sebut saja namanya Max.
Gue sama sekali nggak kenal siapa Max sebelumnya. Tiba-tiba aja sosok ini masuk ke dalam hidup gue dalam kelebatan-kelebatan di lorong, di lift, di antara kubikel-kubikel meja kerja. Bahkan gue sama sekali nggak tahu siapa namanya ketika pertama kali lihat dan tertarik. Gue menyebutnya sebagai ‘si itu’ ketika bicara soal dia ke temen gue lewat chat.
“Hari ini si itu pake baju item.”
“Hari ini dia potong rambut.”
“Kayaknya baru minggu lalu deh dia potong rambut tapi hari ini rambutnya udah potong lagi?”
“Hari ini dia pake sweater coklat.”
“Hari ini dia makan gorengan di meja kayak kocak banget deh.”
Gue bersyukur punya dua orang teman yang mau mendengarkan semua kebucinan gue dalam Fase Max ini. Karena beneran hampir setiap hari gue laporan. Mau si Max telat dateng, atau kebetulan kita ada di satu lift, atau ketika misalnya gue tanpa sengaja (atau dengan sengaja) berinteraksi sama dia, dan hal-hal receh lain yang gue besar-besarkan seolah-olah itu jadi sesuatu yang harus gue anggap sebuah harta berharga.
Tapi masalahnya hanya satu dan itu udah gue sebut sebelumnya: gue nggak tahu siapa dia.
Terlepas dari mana asalnya, berapa umurnya, siapa namanya, minus berapa matanya, tingginya berapa, apa makanan kesukaannya, kenapa dia suka banget makan kerupuk, kenapa kalo diajak ngopi dia suka nolak, dan hal-hal trivia lainnya, hal penting yang gue nggak tahu soal Max adalah apakah dia sudah punya pacar? Atau apakah dia sudah nikah?
Tentu saja pertanyaan ini muncul di kepala gue setiap kali gue sudah merasa kalau aksi bucin gue berlebihan.
“Tau-tau dia udah punya anak tiga,” kata temen gue di salah satu sesi chat kita.
"Gue sih curiga emang dia udah punya anak. Soalnya kalo solat, doanya suka lama," gue menimpali.
Gue nggak mau mikirin itu sebenarnya karena ya gue merasa bahwa ini tuh just another silly crush gitu. Kalau boleh jujur gue juga nggak mau berkomitmen sama siapapun kok. Walaupun kalau Max mau ngajak gue berkomitmen mungkin gue akan mempertimbangkannya.
(((WKWKWKWKWKKWKW BRENGSEK))) (((GELI SENDIRI)))
Hal buruk tentang gue tuh (atau dalam bahasa sosmed my toxic trait) sebenarnya kalau gue udah bucin sama orang, gue bisa melakukan apapun untuk orang itu, bahkan hal-hal yang mungkin akan membuat gue dianggap berlebihan oleh orang lain. Kalo kata lagu-lagu romantis tuh kayak “I’ll cross the sea to find where you are!” Gue beneran kayak lebih fokus ke orang yang gue suka daripada ke diri gue sendiri.
Okelah gue dulu sangat menikmati proses itu karena nggak bisa bohong, naksir orang tuh emang enak banget. Lo jadi punya alasan buat senyum-senyum sendiri, lo jadi punya motivasi buat menuju ke suatu tempat karena lo tahu lo akan ketemu dia, dan selalu ada alasan buat lo happy meski itu hanya sekadar stalking Instagram aja. Tapi tentu saja di sisi lain hal itu memberikan efek negatif karena lo juga akan mulai menginterpretasikan segala tindak-tanduk dia secara berlebihan, apapun reaksi dia atas kebodohan yang tidak sengaja lo lakukan akan membuat lo kepikiran, bahkan lo mungkin akan berada di fase yang “AH DIA KAYAKNYA JIJIK DEH SAMA GUE GEGARA KEJADIAN TADI!” padahal pada kenyataannya dia tahu lo ada di dunia ini juga enggak.
Tapi gue cukup menikmati fase-fase bucin itu. Meski ini berlebihan dan harusnya nggak kayak gini, tapi gue merasa seperti punya semangat hidup yang baru.
Sampai suatu hari gue follow Instagram dia dan gue terjerembab di jurang kekecewaan. Gue tahu sebenarnya kalau udah masuk ke fase stalking sosmed tuh semua hal bisa terjadi. Banyak di antaranya adalah kekecewaan. Entah apakah gue memang overthinking, negative thinking, atau ini emang sebuah keniscayaan, tapi gue semacam tahu kalau gue sudah pencet follow di Instagram itu berarti gue akan berakhir kecewa.
Bener aja.
In a normal, regular, bright day, gue buka Instagram (akun alter) gue dan lihat update-an Instagram Story dia.
Ada foto USG.
Kalau lo pernah naik Hysteria di Dufan, rasanya kayak badan gue dijatuhin dari ketinggian secara mendadak, yang bikin semua organ di dalam tubuh gue kayaknya pindah ke kaki. Kebayang nggak tuh kalo lambung lo sekarang ada di kelingking kaki kiri? Bedanya, kalau naik Hysteria, lo jatuh dengan nyaman dan aman, lalu adrenalin akan membuat lo merasa ingin melakukan itu lagi. Sementara momen gue lihat Instagram Story itu rasanya seperti dijatuhin di Hysteria, tanpa pengaman apapun, dan terus aja jatuh tanpa henti kayak ke pusat Bumi dan nggak ada ujungnya.
Mendadak gue jadi marah.
Kenapa gue marah ya? Gue juga nggak tahu.
Setelah insiden Instagram Story itu, setiap kali gue ngeliat Max sekarang gue kesal.
Kenapa gue kesal ya? Padahal kan dia nggak melakukan apa-apa? Padahal kan nggak ada yang terjadi juga di antara kita selama ini? Padahal kan selama ini juga gue doang yang halu dan memikirkan skenario-skenario fiksi di kepala gue soal gue dan Max? Kenapa gue harus sakit hati mengetahui kenyataan yang seharusnya sudah bisa gue prediksi dari awal? Toh gue kan emang nggak tahu dia siapa sejak awal!
Dua hari pertama sejak insiden itu adalah dua hari paling sulit. Aura gue yang biasanya ceria (karena ini susah payah gue bangun sepanjang pandemi) mendadak diliputi awan hitam dan kepala gue kayak ditumbuhi tanduk. Untungnya di hari ketiga gue sudah mulai sadar dan semua sudah mulai membaik. Di hari ketiga itu, gue memutuskan untuk diam sejenak di meja kerja dan memikirkan semuanya. Memproses emosi yang gue rasakan selama tiga hari terakhir, memilah mana yang harusnya bisa gue anggap wajar dan mana yang tidak.
Naksir Max itu wajar karena dia memang menarik perhatian gue sejak awal. Senang karena interaksi kecil dengan Max tentu saja wajar, namanya juga bucin. Tapi marah ke Max karena kebahagiaan yang sedang dia rasakan? Ini tentu saja salah.
Beberapa tahun terakhir ini gue menyadari bahwa ikut bahagia melihat orang lain bahagia itu nggak segampang mengeluarkan upil di lubang hidung kanan. Demi Allah itu susah banget. Jangankan sama orang yang deket banget sama kita (lebih-lebih lagi orang yang deket sama kita!), orang yang kita nggak kenal pun kadang-kadang masih bikin kita jadi dengki hanya karena dia dapat sesuatu yang kita nggak dapatkan. Padahal seharusnya kan nggak gitu.
Idealnya, meski kita nggak terlalu kenal satu sama lain atau meski sama orang asing sekalipun, kita kan harus tetap ikut senang dan merayakan. Paling nggak, kita nggak bikin mood mereka dalam merayakan kebahagiaan itu jadi down. Jangan jadi party pooper.
Butuh waktu lama untuk belajar membiasakan diri melakukan ini. Dan belajar membiasakan diri untuk ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain ini juga sejalan dengan penerimaan bahwa kita pun harus berbahagia dengan apapun yang kita miliki sekarang. Berbahagia dengan kondisi kita sekarang. Bahwa hal-hal yang ideal menurut kita belum tentu ideal menurut orang lain, dan begitu juga sebaliknya.
Di lingkaran pertemanan gue yang kecil ini, beberapa teman terdekat gue sudah nikah. Kalau boleh jujur, sebelum pada akhirnya gue bisa ikut berbahagia mendengarkan kabar pernikahan itu, gue sempat dilanda ketakutan. Again, karena lingkaran pertemanan gue kecil, teman-teman gue nggak banyak. Kalau dia nikah, nanti gue main sama siapa? Nanti gue nonton sama siapa? Nanti gue mau ke mana-mana sama siapa?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu gue selama beberapa hari setelah salah satu teman gue mengabarkan dia akan menikah. Nggak berselang berapa lama, teman gue yang lain ngasih tahu kalau dia juga mau nikah dan akan mengirimkan undangan ke gue.
Kebiasaan buruk gue dari dulu adalah selalu berusaha memikirkan hal terburuk dari sebuah kejadian. Skeptis juga anaknya. Terlalu fokus ke hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Terlalu memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan. Di situlah kemudian gue berpikir. Kenapa? Kenapa gue harus takut dan sedih kalau teman-teman gue justru sedang berbahagia? Bukannya gue pun harusnya juga bahagia atas kebahagiaan mereka? Apapun itu. Ya pernikahan, ya pencapaian dalam hidup. Apapun itu.
Lalu satu per satu pertanyaan yang tadi muncul gue jawab sendiri.
Kalau dia nikah, nanti gue main sama siapa? Main sendiri pun nggak terlalu ada bedanya sih toh selama ini kan udah biasa ke mana-mana sendiri. Dan kalau nanti dalam perjalanan ketemu teman baru kan bisa jadi cerita yang menarik.
Nanti gue nonton sama siapa? Nonton sendiri pun ternyata nggak masalah. Lagian kalau nonton kan lebih banyak diam di dalam bioskop nggak ngobrol sama siapapun. Kalau ngobrol malah ganggu, toh? Dan, kalau soal teman nonton, masih ada yang lain yang available kok. Jadi nggak perlu khawatir soal ini.
Nanti gue mau ke mana-mana sama siapa? Loh, kalau mau pergi ya nggak perlu bergantung sama orang lain. Kalo lo mau ke mana-mana ya pergi aja. Justru dengan sendiri, lo bisa bebas ngatur semuanya tanpa harus ada bentrok kepentingan.
Nanti gue naksir sama siapa?
Nah kalau yang ini sih… tergantung hati aja.
Sekarang gue masih sering lihat Max, kadang-kadang berinteraksi juga sama Max. Satu teman dekat gue yang udah nikah itu masih tetap berhubungan baik sama gue juga bahkan gue sama pasangannya sering main Genshin Impact bareng. Satu teman gue yang lain udah nggak tahu kabarnya gimana karena selain laporan kalau dia udah bayar YouTube Family, dia nggak akan menghubungi gue. Pada akhirnya semua baik-baik saja, kan?
Dan soal Max… gue turut berbahagia.
Dengan perubahan pola pikir ini gue kemudian nggak lagi merasa marah dan kesal sama dia. Mungkin ya gue kesal karena tidak bisa memiliki dia, tapi lebih dari itu, gue harus berbahagia karena dia akan segera jadi orangtua. Kalau memang perasaan gue ke dia tulus nih misalnya, naksir dengan tulus gitu, gue harusnya juga bisa dengan tulus ikut merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Bukan ruined the happiness yang dia rasakan, kan?
Max masih tetap bisa bikin gue senyum-senyum sendiri, walaupun gue tahu nggak akan ada yang terjadi di antara kita. Bahkan eksistensinya aja bisa bikin gue senyum bahagia. Harusnya gue membalasnya dengan ikut berbahagia atas kebahagiaan dia juga, kan?
Pada akhirnya gue masih bucin. Tapi sekarang gue lebih jago membentengi hati dari hal-hal seperti emosi yang merusak. Biarlah Max jadi salah satu bagian dalam cerita usia 30-an gue yang nggak akan terulang lagi.
Selamat dan berbahagialah, Max!









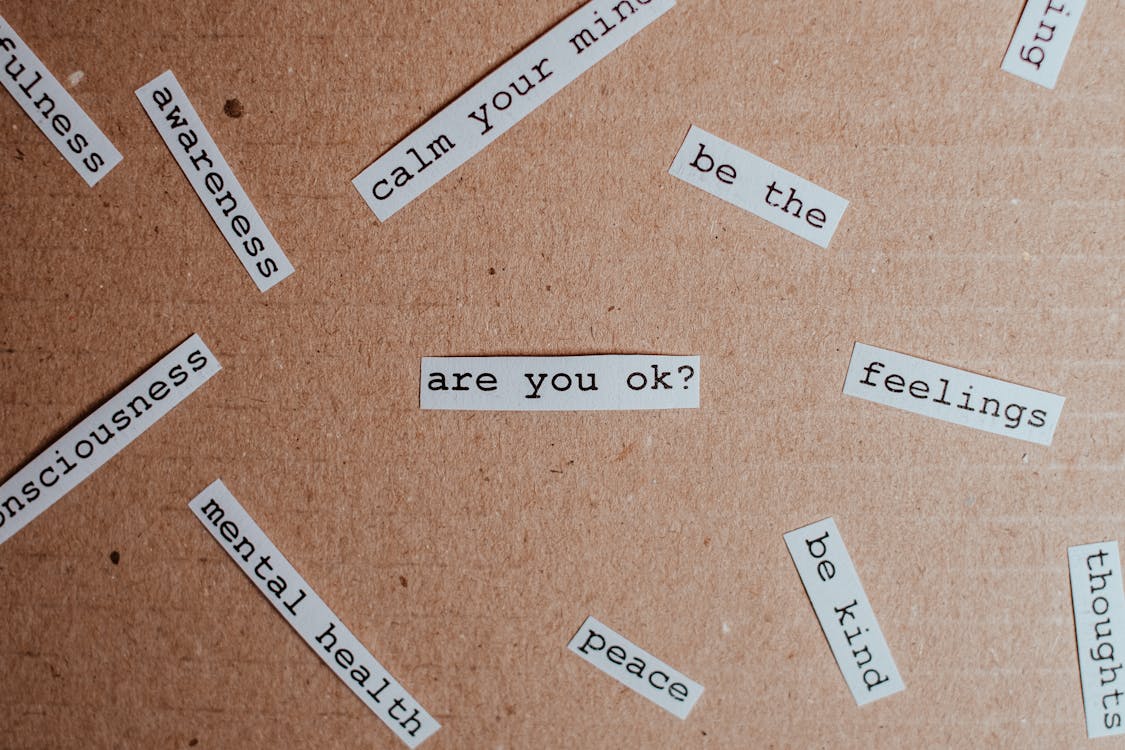









0 comments