Bangkok Bagian 2: Selamat Datang di Sukhumvit
“Can I have two?” kata gue dalam Bahasa Inggris. Mbaknya ngasih dua. Gue sengaja minta dua karena gue tahu pasti yang pertama akan ada kesalahan dalam pengisian. Karena seringkali kejadian kayak gitu jadi gue sudah mengantisipasinya daripada bolak balik minta. Mana lagi gue sedang tidak dalam kondisi mental yang stabil hahahaha dan bener aja, ketika gue melakukan pengisian form pertama ada kesalahan yang gue buat di nama gue sendiri. DI NAMA GUE SENDIRI. Gak paham lagi deh. Setelah mengulang pengisian, gue buru-buru antre dan menuju ke imigrasi. Bersyukur banget keluar imigrasi di negara-negara ASEAN enggak terlalu intimidatif. Beda sama UK atau US. Ngeri banget deh feel-nya beneran kayak tertekan banget. Jarang banget ada petugas imigrasi yang bener-bener ngajakin ngobrol gitu. Tapi terakhir gue ke Korea, gue nemu mbak-mbak petugas imigrasi yang kayaknya suka Kpop juga. Soalnya waktu itu dia nyuruh gue buat ngelepas case paspor gue yang di dalamnya terselip satu tiket konser EXO dan banyak sekali stiker karakter EXO dari album EX’ACT yang gue dapat dari Andi.
“You like Kpop?” dia nanya kayak gitu dalam proses gue nempelin sidik jari.
“Yes. That sticker is EXO,” gue tembak aja, in case she is wondering.
“You like EXO?” dia nanya lagi.
“A lot,” jawab gue.
Walaupun obrolan itu cuma sekedarnya, tapi seenggaknya bisa bikin lo jadi santai dan merasa disambut gitu lho masuk ke negara orang. Ih pas gue di London diketusin sama mbak-mbaknya. Padahal udah gue assalamualaikum gegara dia pakai jilbab. Sebel. Ya intinya harus santai aja. Kalau ditanya ya dijawab. Kalau disenyumin (tapi mostly sih enggak) ya senyum balik. Setelah gue buka kacamata dan buka topi anjing bertelinga yang gue pakai, paspor gue dicap dan gue bisa keluar dengan sentausa.
Sebenarnya gue lapar banget dan ingin cari makan dulu. Tapi gue urungkan niat itu karena gue ingin segera sampai di hostel. Seharusnya gue Jumatan hari itu tapi gue nggak yakin akan keburu untuk keluar dari bandara menuju masjid terdekat, jadi yaudah nanti dzuhur aja di hostel. Sebelumnya gue sudah pesan traveler’s SIM Card di Klook dan harus diambil di loket yang ada di dekat pintu kedatangan. Gue langsung menuju ke sana karena gue butuh WiFi untuk mencari informasi soal bus dan sebagainya. Beruntung gue dapat promo dari Klook cuma sekitar Rp 50 ribuan untuk SIM Card ini. 3GB untuk 4 hari 3 malam gue rasa cukuplah. Enggak semahal di Singapura dan Korea Selatan deh pokoknya. Setelah urusan SIM Card selesai dan terhubung ke internet lagi, gue akhirnya bisa cari informasi soal bus yang harus gue naiki untuk menuju ke hostel.
Sebenarnya rutenya gampang banget sih dari Don Mueang. Cuma harus naik bus A1 sekali dan turun di stasiun BTS Mo Chit (dekat Chatuchak Weekend Market), kemudian dari situ lanjut ke stasiun BTS Phrom Phong dan jalan kaki beberapa menit sampai ke hostel.
Mencari tempat naik bus di Don Mueang juga nggak terlalu susah. Gue sendiri cuma bermodalkan petunjuk jalan yang ada di Bandara aja dan udah nemu deh itu tempat nunggu busnya. Sediakan uang kecil pecahan 50 Baht atau 100 Baht untuk bayar busnya. Soalnya kata temen gue kalau bayarnya pake uang gede kayak 1000 Baht atau 500 Baht suka diketusin. Mana gitu kan kalau mereka ngomel pakai Bahasa Thailand gue juga enggak ngerti ya. Jadi mendingan bayar pake uang kecil aja.
Tapi abis itu mereka nggak langsung nari kok.
Perjalanan dari Bandara Don Mueang ke pusat kota Bangkok tepatnya di Stasiun BTS
Gue lihat ada banyak orang mengantre di loket tapi gue nggak tahu apakah sebenarnya orang-orang ini sedang pesan tiket atau isi ulang kartu transportasi mereka. Karena di dekat loket tiket ada vending machine juga yang setelah gue perhatikan nggak menerima uang kertas. Sementara gue nggak punya koin yang cukup, hanya ada 20 Baht aja kembalian dari bus tadi. Lagipula gue nggak tahu berapa ongkos ke Phrom Phong berapa. Gue muter-muter lama banget di situ. Sambil ngeliatin ada makanan apa aja yang dijual di sana, ada minuman apa aja yang dijual di sana, dan tentu saja orang-orang juga mulai ngeliatin gue karena topi anjing yang gue pakai. Gue malas bertanya. Jadi gue hanya bisa memerhatikan apa yang dilakukan orang-orang (lagi). Gue berdiri di dekat loket tiket dan melihat orang beli tiket di sana barulah gue yakin kalau gue nggak butuh vending machine. Akhirnya gue ikut antre di depan loket dan bilang kalau gue mau ke Phrom Phong. Ongkosnya sekitar 40 Baht dari Mo Chit dan nggak harus transit, untunglah. Kalau udah punya tiket kan tinggal naik aja. Pasti nggak akan jauh beda sama naik Subway dan MRT di Seoul dan Singapura.
“One ticket to Phrom Phong please,” kata gue ke petugas loket.
“Forty Four,” katanya mengisyaratkan harga. Gue kasih uang 100 Baht dan dia balikin sisanya plus kartu yang harus di-tap untuk masuk ke area penumpang BTS. Hari itu Jumat siang, gue kira nggak akan terlalu ramai. Tapi ternyata lumayan juga. Kondisi gue sedang bawa ransel dan koper begini kadang-kadang takut mengganggu penumpang lain. Jadi gue berusaha untuk tidak membuat koper gue menghalangi jalan. Gue agak kesulitan untuk menangkap pengumuman kereta sudah sampai ke stasiun mana karena itu pertama kalinya gue mendengar suara dengan nada bicara seperti itu. Jadi gue sesekali lihat aplikasi BTS di hape untuk memastikan gue sudah berhenti berapa kali sejak naik di Mo Chit. Sesampainya di Phrom Phong, gue sempat salah aksi ketika keluar palang penumpang hihihi. Kalau biasanya di Jakarta di tap, di Bangkok kartunya harus dimasukin kayak masukin kartu ATM. Gue tap berkali-kali enggak bisa! Terus malu sendiri pas ternyata dimasukin. Buru-buru kabur dan geret koper berjalan ke Lamurr 41 Sukhumvit, hostel gue.
Gue menekan bel dan salah satu bule perempuan yang sepertinya adalah tamu membukakan pintu buat gue. Gue bilang terima kasih dan dia balas tersenyum. Gue masih tidak bisa berpikir mantap bahkan sampai ketika Ai, resepsionis hotelnya nyapa gue dan nanya nama gue siapa. Ini nih yang selalu susah dilakukan kalau misalnya lagi check in di hostel kayak gini. Soalnya nama gue agak susah ditangkap mungkin sama pendengaran orang asing. Sebenarnya kan bisa aja gue ngasih paspor gue langsung jadi dia bisa lihat dan baca sendiri ya, tapi dia terlanjut nanya sih.
“ATMI. A-T-M-I,” kata gue. Dia nyari-nyari kertas reservasi dan pas nemu dia heboh sendiri.
“Can I have your passport?” tanya dia.
Tuh kan bener harusnya tadi gue langsung kasih aja nggak usah pake eja nama gue yang orang-orang Indonesia selalu mikir itu nama cewek.
Biasanya kalau tinggal di hostel mereka akan minta yang deposit. Kalau-kalau terjadi kerusakan fasilitas atau kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal yang terjadi sepanjang lo menginap. Uang ini nantinya akan dikembalikan sih setelah check out. Di hotel-hotel besar biasanya minta kartu kredit by the way. Jadi better lo siapkan uang lebih dari budget belanja hari itu. Gue sendiri sebenarnya lupa soal deposit ini, jadi gue harus memotong uang makan dan belanja gue selama di sana. Lumayan juga soalnya deposit-nya THB 500. Anggap aja nabung buat ongkos balik ke Bandara di hari terakhir. Setelah urusan data check in kelar, Ai ngasih kunci kartu yang bisa di-tap buat masuk ke kamar dan juga buat masuk ke hostel (pintu hostel dibuka 24 jam). Sama satu kunci biasa buat loker.
“Your room is on 3rd floor, right door,” kata Ai lagi. Gue senyum terus bilang thank you, sebelum akhirnya dia nyetop gue lagi dan bilang, “Your shoes.”
“Hehe. Mon maap.”
Setelah membuka sepatu gue langsung menuju ke lantai tiga. Dalam perjalanan ke sana gue melewati ruang tamu kecil dengan undakan tinggi tempat tamu-tamu bisa lesehan di situ. Ada meja kecil di tengah-tengah dan satu televisi besar di satu sisinya. Di dekat televisi ada rak-rak kecil yang berisi majalah, buku, brosur, dan berbagai macam kerta informasi wisata di Bangkok. Sementara di sisi berlawanan dengan televisi ada rak tinggi yang di atasnya ada sederet tempat makanan. Mungkin buat sarapan. Pikir gue. Di belakang rak tinggi itu ada wastafel dan di sisi kirinya ada pintu menuju ke kamar.
Gedung ini mungkin sekitar lima lantai. Soalnya gue nggak sampai naik ke lantai empat atau lima, tapi ketika gue sampai di lantai tiga gue bisa melihat tangga untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Gue lupa jenis kamar yang gue pesan tapi yang jelas sih dormitory room. Nggak inget buat berapa orang dan nggak inget apakah itu khusus cowok atau campur. Gue sama sekali nggak berekspektasi lebih soal kamarnya. Gue juga lupa apakah sudah pernah melihat foto hostelnya di apps booking.com jadi ketika gue masuk, gue agak shock karena ternyata ruangannya nyaman meski space di antara kasur satu dan yang lainnya sempit banget. Lumayan cukup buat solat sih untungnya. Cuma kalau misalnya pintu dibuka (posisi solat membelakangi pintu), jelas akan kena ke gue. Semoga pas nanti solat nggak ada yang masuk deh. Nggak enak soalnya.
Kasurnya sendiri nggak bunk bed yang terbuat dari besi gitu. Lebih ke kayak model kapsul/pod gitu dengan segala colokan dan lampu yang ada di dalamnya. Tapi bentuknya enggak seperti hotel kapsul. Lebih ke kubikel berisi kasur dengan atap dan tirai. Untungnya gue dapat kasur di bawah jadi nggak perlu repot buat naik tangga dan manjat kalau mau tidur dan beraktivitas di kasur. Posisi kasur yang gue dapatkan juga terbilang enak karena sebagian tubuh gue ketutupan dinding. Jadi kalaupun gue nggak tutup tirai yang keliatan paling cuma kaki. Jodoh banget deh gue sama tempat ini. Di bawah kasur ada loker yang cukup besar untuk masukin koper. Bahkan koper dan ransel gue muat masuk ke situ. Gue sih rekomendasikan banget hostel ini. Soalnya buat 4 malam 3 hari, cuma THB 800-an atau sekitar Rp 350 ribuan.
“Oke, mending sekarang turun, terus cari-cari informasi lewat booklet yang ada di ruang tamu. Siapa tahu dapat pencerahan,” gue ngomong sendiri. Setelah semua baterai perelektronikan terisi penuh, gue jejelin semuanya ke dalam tas kuning kecil yang gue beli beberapa hari sebelumnya. Cameron (nama kamera Fujifilm XA3 gue) gue bawa di leher aja karena hari ini nggak mau ribet bawa ransel. Setelah pakai kaus kaki, gue turun ke ruang tamu. Gue mulai merasa lapar dan baru ingat kalau memang dari pagi gue belum makan yang proper. Di saat seperti ini gue butuh nasi, tapi gue juga belum tahu harus beli makanan di mana dan mau makan apa. Riset gue soal Bangkok nol besar banget. Yang kebayang sekarang di kepala gue cuma tauge yang tadi sedang digoreng bapak-bapak pedagang kaki lima nggak jauh dari hostel ini. Temen gue bilang tauge goreng ini enak. Tapi gue sendiri masih sangat ragu untuk mencoba makanan apapun. Gue butuh nasi, tbh.
Kalau sudah ada di hostel kayak gini, tubuh gue secara otomatis bergerak lebih lambat dan pelan-pelan, berusaha untuk enggak menciptakan suara terlalu keras. Tidak berisik adalah peraturan nomor satu di tempat kayak gini. Gue membuka pintu menuju ruang tamu pelan-pelan juga dan berjalan pelan menuju ke undakan, mendekat ke salah satu rak yang berisi banyak map dan brosus, mengeksplor halaman demi halaman brosur itu dengan harapan gue dapat inspirasi mau ke mana dan ngapain hari ini. Di ruang tamu itu gue nggak sendirian, ada satu orang laki-laki dengan t-shirt putih dan kaca mata hitam yang sikaitkan ke bagian tengah kerahnya. Wajahnya agak ketutupan bayangan karena ruang tamu itu memang agak remang-remang. Televisi menyala tapi nggak ada yang memperhatikan. Orang ini juga sedang sibuk dengan ponselnya sementara gue sibuk dengan brosur-brosur yang sedang gue lihat. Walaupun pada akhirnya gue nggak dapat inspirasi apapun dari situ karena kebanyakan isinya cuma menawarkan paket tur Bangkok. Tiba-tiba gue mencium aroma kopi dan baru sadar kalau dari tadi aroma itu menggelitik ujung hidung dan juga otak gue. Gue butuh kopi. Gue ngantuk banget. Tapi gue juga lapar banget. Gue melirik ke kiri dan baru sadar kalau aroma kopi itu dari si laki-laki yang sekarang sedang nyender di dinding ruang tamu. Ada tulisan di dinding tempat dia bersandar itu dengan beberapa huruf hilang karena copot dari lemnya.
“Are you local?” tiba-tiba gue mendengar suara memecah keheningan. Suara agak berat dengan aksen yang familiar, tapi gue enggak yakin untuk menebak aksen itu. Laki-laki tadi menyapa gue dan berusaha membuka obrolan. “Are you from Thailand?” tanya dia lagi. Gue bisa memastikan pertanyaan itu untuk gue karena nggak ada orang lain di ruang tamu itu selain kita berdua.
“No, I’m from Indonesia,” jawab gue sambil tersenyum. Orang ini juga tersenyum bahkan nyaris tertawa. Gue tahu kenapa. Dia melihat topi anjing yang gue pakai. Gue pikir ketika gue menjawab gue orang Indonesia obrolan kita akan berakhir di situ. Gue pikir dia cuma basa-basi aja nanya gue dari mana. Tapi ternyata dia malah tertarik untuk mengobrol lebih banyak lagi.
“Indonesia? Great place. Lots of great people. I had an amazing adventure in Bali not too long ago,” katanya.
“Really?”
(dari sini dan selanjutnya gue akan menulis percakapan kami dengan Bahasa Indonesia).
“Ya. Gue pernah stay di Bali beberapa minggu. Bareng sama beberapa teman. Suasananya luar biasa banget. Kita naik mobil dan gue duduk di atap mobil sambil megang papan selancar. Bener-bener pengalaman yang nggak terlupakan,” ceritanya.
Tadinya gue nggak berniat untuk lama-lama di ruang tamu itu, tapi mendadak rasa lapar gue hilang. Mendadak, gue jadi ingin ngobrol lebih banyak dengan orang ini. Gue merasa agak nostalgia sedikit ke perjalanan pertama gue ke Seoul beberapa tahun lalu ketika gue bertemu Ched dan Sacha di hostel.
“Kedengerannya lo sangat bersenang-senang waktu itu,” kata gue.
“Banget. Gue suka banget sama orang Indonesia terutama di Bali. Orang-orangnya semua ramah. Pernah waktu di Bali gue berniat untuk pergi mancing ke tengah laut. Dan orang ini, usianya mungkin sekitar akhir 30an atau pertengahan 40an, dia bilang dia mau mancing ke tengah laut dan gue tertarik untuk ikut perahunya. Gue pengin banget merasakan pengalaman itu, you know, mancing di tengah laut. Jadi gue tanya sama dia apakah gue bisa ikut atau enggak. Dia bilang boleh. Gue excited banget dan sudah siap deh kalaupun harus disuruh bayar. Tapi pas gue tanya dia gue harus bayar berapa, dia bilang enggak usah bayar. Gue kaget, you know. Kita baru ketemu dan seharusnya kan memang ada harga untuk hal-hal seperti itu. Gue kan turis juga, tapi dia bener-bener nggak mau nerima bayaran. Ya gue tanya aja sama dia kenapa dia nggak mau dibayar? Dan jawabannya bener-bener bikin gue terharu sih. Katanya dia anggep gue kayak temen aja. Masa sama temen harus minta bayaran?”
Gue mendengarkan dengan saksama sambil berusaha menerka-nerka aksen itu. Sekalian gue juga mencerna setiap kalimat yang dia ucapkan karena, hey, ini pertama kalinya dalam setahun terakhir gue berkomunikasi lagi sama orang asing tidak dalam bahasa sendiri. Gue agak bingung bagaimana harus merespons cerita dia.
“He really was a nice guy!”
“He was! I love your people, man,” katanya lagi.
Seneng nggak sih lo mendengarkan cerita orang luar negeri tentang Indonesia dan mereka dapat kesan yang positif tentang masyarakat lokal kita? Gue harap orang-orang kayak gini nggak akan ketemu dengan para provokator yang sering nyebar hoax dan rusuh bawa-bawa agama buat jadi alasan ngerusak.
Gue nggak memulai obrolan ini tapi gue terseret masuk dan mulai merasa akrab dengan si mas-mas berewokan ini. Walaupun gue yakin Bahasa Inggris gue nggak sebagus dia (Bahasa Inggris orang ini bagus banget tapi ada aksen yang terdengar jelas. Dia pasti berasal dari somewhere in Europe). Eh tapi ngomong-ngomong nih ya, kita belum kenalan. Apakah gue harus memperkenalkan diri duluan? Tapi kan dia yang mulai ngajak ngomong duluan. Gue nggak jago di bagian ini. Apakah ada peraturan untuk hal-hal seperti ini? Gue mencoba mengingat-ingat ketika pertama kali gue ketemu Ched di Maru Hostel Hongdae beberapa tahun yang lalu. Dia yang pertama ngajak gue ngomong dan dia yang pertama ngenalin diri. Gue pindah posisi duduk dan nyamperin dia ke meja.
“I’m Ron,” gue menyodorkan tangan. Ya akhirnya gue yang ngenalin diri duluan.
“Adrien,” katanya menjabat tangan gue.
Jujur aja, ini bukan rasis ya, tapi dengan aksennya itu gue nggak menangkap dengan jelas waktu dia menyebut namanya. Gue nggak bisa membaca gerakan bibirnya juga soalnya kan berewokan (yahahahahahah) dan juga di situ agak gelap. Selama beberapa menit gue kira namanya Edwin. Beneran, ketika dia memperkenalkan diri itu, namanya terdengar seperti Edwin. Gue nggak bohong. Gue bego nggak sih? Tapi setelah gue tanya dia dari mana, gue baru mikir, masa Edwin?
“Lo dari mana?”
“Perancis.”
Tuh kan! Ada nggak sih orang Perancis namanya Edwin?
Sebelum gue sempat ber-WOW PERANCIS! Dia buru-buru menambahkan kalau sekarang dia sedang tinggal di Yangon, Myanmar.
Gue kayaknya beneran harus ke THT deh ini dalam waktu dekat. Kalau dia nggak ngomong Myanmar, kalau dia cuma ngomong Yangon, gue nggak akan tahu kalau yang dimaksud itu Yangon, Myanmar. WKWKWKKW. Ini perkara gue aja sih yang nggak pernah mendengar orang asing ngomong Yangon. Kalau kita kan pasti nyebutnya akan ‘YANG-ON’ sementara dia ngomongnya jadi ‘YENG-GOON’. Aslik gue malu banget tapi gue stay cool ajalah. Padahal posisi gue udah semeja sama dia tapi tetep aja gue nggak bisa denger dengan jelas apa yang dia omongin. Ahahaha. Gue nggak mau menyalahkan diri gue terlalu lama, ini pasti karena memang gue baru berinteraksi lagi dengan orang yang ngomong Bahasa Inggris. Jadi masih kagok. Oke, kalem aja Ron. Lupain aja kalau lo budeg. Lupain aja kalau Adrien dan Edwin itu jauh banget ya. Lupain aja kalau lo nggak jago Geografi dan Sosiologi. Ini berarti lo harus melupakan ambisi lo untuk jadi guru Geografi atau Sosiologi di SMA.
“Lo udah pernah ke Bangkok sebelumnya, atau ini pertama kali?” gue nanya dia untuk memecah kecanggungan.
“Nggak. Sudah pernah ke sini beberapa kali. Lo?”
“Ini gue perdana banget deh. Makanya tadi gue coba buat nyari-nyari referensi tempat di situ, tapi nggak terlalu nemu banyak. Sebagai orang yang sudah sering ke sini, apa yang lo suka dari Bangkok?” mungkin dari situ gue bisa dapat referensi gue harus ngapain sambil nunggu hari konser.
“Hmm... Gue sebenarnya orang yang suka sama traveling yang ekstrem. Tapi kalau ke Thailand, gue lebih ke yang menikmati kotanya aja. Karena nggak banyak yang bisa dilihat di Myanmar. Yangon itu kota kecil, enggak terlalu maju untuk urusan entertainment misalnya. Sesimpel film, kita selalu telat kayak lebih dari enam bulan. Bahkan banyak banget film Hollywood yang enggak tayang di sana. Jadi orang-orang kayak gue, expat yang tinggal di Yangon, biasanya akan pergi ke Thailand untuk cari hiburan. Sekedar nonton atau shopping. Karena di sini lebih banyak pilihan daripada di sana,” katanya.
Gue mulai membayangkan seperti apa Myanmar dari cerita Adrien. Kok kayaknya Jakarta masih better ya? Mataram malah mungkin lebih update daripada Yangon.
“Ya tapi bukan berarti Yangon nggak nyaman untuk ditinggali. Kota ini buat gue nyaman banget karena orang-orangnya juga baik. Setahun terakhir gue tinggal di sini dan gue seneng aja dengan masyarakatnya. Yah kalau soal macet dan segala macem sih yaudah pasti, tapi di luar itu, banyak makanan enak di Myanmar!” kata dia lagi.
“Gimana ceritanya lo bisa sampai di Myanmar, deh?” nah ini udah masuk ke pertanyaan serius. Gue kepo banget nggak sih kesannya? Tapi dia sendiri enggak jawab pertanyaan gue soal rekomendasi tempat sih. Jadi yaudah gue tanya macem-macem aja.
“Awalnya gue kerja di sebuah perusahaan di Paris. Tapi gue sampai di titik di mana gue berpikir kalau gue kerja di sini terus, gue nggak bisa tahu atau menikmati apa yang ada di belahan dunia lain. Gue anaknya suka bertualang, dari kuliah gue ada temen yang bener-bener deket banget dan kita selalu melakukan petualangan bareng. Gue ada rencana buat sailing sama dia nih beberapa bulan lagi. Tapi anyway, gue resign dari perusahaan gue itu dan akhirnya berpikir untuk mengunjungi satu negara. Tapi waktu itu gue belum menentukan pilihan mau ke mana. Sampai akhirnya ada seorang teman menawarkan pekerjaan di Myanmar. Well, ini sebenarnya bukan bagian dari rencana gue. Gue mau berhenti kerja bukan buat pindah ke perusahaan lain. Gue berhenti kerja justru buat mengeksplor dunia. Tapi setelah gue pikir-pikir, Myanmar kayaknya bakal seru dan daripada gue ke sini nggak ngapa-ngapain, mending gue terima tawaran kerja itu jadi gue ada pemasukan. So yeah, here I am now,” ceritanya.
Lewat cerita yang singkat itu gue udah langsung tertarik dengan perjalanan hidup orang ini. Gue nggak tahu usianya berapa tapi kayaknya sih kita seumuran. Dan di usia kita yang nggak jauh beda kayak sekarang, dia bisa gitu memutuskan untuk berhenti kerja dan berpetualang. Meanwhile.... gue.... hahahahahahahha.
“So what about you? Apa yang bikin lo datang ke Thailand? Lo kerja juga atau?”
“Nggak banyak cerita seru soal gue. Hehe... gue tinggal di Jakarta, tapi gue asli Lombok. Mungkin lo pernah dengar pulau kecil di dekat Bali. Kapan-kapan lo harus ke situ dan lo harus kasih tahu gue jadi gue bisa ajak lo keliling. Gue kerja sebagai content writer di forum online di Jakarta. Kerjaannya nggak seserius lo sih kayaknya, tapi gue suka aja dan they paid me well, so, hahahahah....” gue ketawa kenceng banget anjir. Dia juga ikutan ketawa.
“Bagus dong! But you like the job, right?”
“Yeah, sudah mulai nyaman. Dan untuk kunjungan gue ke Thailand ini sebenarnya buat nonton konser Kpop hari minggu nanti. Gue memang suka banget sama entertainment business dan entertainment world-nya Korea Selatan. Artis yang akan gue tonton nanti ini soalnya enggak ke Indonesia, jadinya gue ke sini aja buat nonton dia,” cerita gue berakhir di situ. Tapi obrolan kita belum selesai. “Lo kerjaannya apa deh?”
“Gue konsultan. Perusahaan gue yang sekarang sama beberapa teman, tapi kerjanya seringkali ya kayak weekend gitu sih. Jadi ke sini juga nanti harus kerja dari jauh,” jawab dia. “Tapi gue ke sini sebenarnya buat ngurus Visa di Embassy Myanmar di sini,” katanya lagi.
Adrien mulai menceritakan detail soal masalah Visa ini dan kenapa dia nggak ngurus Visanya di Myanmar aja. Kenapa harus di Thailand? Tapi gue nggak bisa ingat detail soal itu. Yang pasti sih, dulu waktu pertama kali dia datang ke Myanmar dari Perancis, Visa kerjanya diurus sama kantor lama. Jadi dia punya Visa yang jangka waktunya lama banget. Ketika dia harus ngurus perpanjangan Visa yang sekarang, dia nggak dapat Visa yang dia mau. Jadilah sebenarnya hari itu dia bad mood banget. Ingin punya teman ngobrol buat marah-marah. Kebetulan dia melihat gue, mas-mas berkumis yang kelihatan kayak bocah pake celana pendek dan baju batik plus topi anjing yang ada telinganya, dia ajak ngobrol buat sekalian marah-marah karena Embassy Myanmar-nya rese.
“Gue tuh kan Apply buat Visa yang tahunan gitu, tapi mereka bilang mereka nggak bisa ngeluarin Visa itu di sini buat gue. Gue harus ngurus lagi ke Myanmar. Sementara pas gue ke Myanmar, mereka merekomendasikan gue untuk ngurus ke Bangkok. What the fuck. Tapi mereka lalu menawarkan gue Visa yang tiga bulan aja. Gila nggak sih? Gue tuh tadi mau marah-marah sama orang Embassy-nya tapi ya nggak bisa juga kan gue marah-marah sama dia. Maksud gue, dia bukan orang yang bikin peraturan. Jadi gue nggak tahu mau marah-marah sama siapa. Kesel banget gue! Untungnya gue ketemu lo nih sekarang kan gue jadi bisa cerita,” dia ketawa.
Sementara itu gue masih mikirin, ini serius nama lo Edwin?
“Bilang makasih lo, ke gue!” gue ketawa juga. “Trus gimana? Visanya lo dapet kan?” Soalnya kalau lo nggak dapet berarti lo harus deportasi dong, men.
“Iya dapet. Baru bisa diambil Senin. Gue juga marah-marah tuh tadi kenapa jadinya baru Senin, padahal kan gue udah ngurusin ini kayak dari kemarin. Tadinya mereka nawarin jalur ekspres gitu yang bisa diambil besok (Sabtu, obrolan ini terjadi di hari Jumat). Tapi mahal banget mereka ngasih harganya. Anjir... gue kayak harus bayar ekstra berapa ratus dolar gitu. jMales banget kan? Mending gue nunggu Senin aka. Lagian gue juga di sini masih sampai Senin. Jadi masih ada waktu lah,” katanya lagi.
Kayaknya emang mood dia lagi misuh-misuh sih. Ini memang dia yang banyak ngomong daripada gue. But it’s okay, lagian gue sangat tidak jago dalam mencari topik obrolan. Sama orang yang satu bahasa aja gue kadang susah buat nyari bahan. Ini lagi sama orang Perancis yang gue masih nggak jelas namanya beneran Edwin atau bukan.
“Tempat ini nice banget, kan?” dia melirik ke gue terus ke sekitaran ruang tamu.
“Yeah. And also cheap. Lo suka ngopi?” gue melirik ke mug putih yang dia genggam.
“Very much. Gue selalu minum kopi setiap hari. Gue nggak bisa memulai aktivitas tanpa ngopi dulu,” katanya.
“Sama dong! Kacau sih. Gue bahkan nggak akan bisa mikir kalau nggak ngopi sebelum kerja. Gue kan seringnya nulis, ide tuh nggak bisa muncul kalau nggak ngopi dulu,” gue ketawa.
“Anyway, lo balik ke Indonesia hari apa? Kalau lo nggak punya plan, mungkin kita bisa makan siang bareng besok atau lusa?”
Penawaran menarik.
“Gue balik Senin malam. Boleh sih, since lo udah sering ke sini jadi mungkin lo bisa ngajak gue ke tempat makan yang lo rekomen banget. Gue minta nomor lo, boleh? Ada WhatsApp kan?”
“WhatsApp ada,” katanya. Gue menyodorkan Jeno dan dia kemudian menulis nomornya di situ. Gue minta dia save nomornya dengan nama lengkap supaya gue tahu siapa nama dia yang sebenarnya. Dan bener aja gue meag bego dan budeg. Pas gue lihat kontaknya, dia save namanya ‘Adrien Lorne’.
EDWIN DARI HONG KONG.
Gue bener-bener harus ke THT.
“I eat a lot.” Adrien ngomong sambil ngeliat ke layar hape. Terus dia ketawa.
“Eh?” gue nggak ngeh maksudnya apa. Tapi ketika dia mengarahkan layar hapenya ke gue, gue baru sadar yang dia maksud itu adalah status gue di WhatsApp. “Ah, yeah, ahahahha,” gue ketawa lagi.
“Ada satu tempat makan nggak jauh dari sini, dari kemaren gue lihat rame banget. Pasti makanannya enak deh. Soalnya kalau nggak nggak mungkin kan rame sampai orang pada antre? Kita mungkin bisa ke sana besok atau lusa. Gue akan kabarin lo, ya?”
“Sure! Yaudah kalau gitu gue pergi dulu deh. Takut kesorean. Nggak tahu mau ke mana tapi gue jalan dulu aja. See you, man.”
“Yeah, see you!”
Gue beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke lobi, pakai sepatu dan keluar dari hostel. Gue enggak tahu mau ke mana tapi ke mana pun gue pergi hari ini, gue harap gue akan menikmati perjalanannya. Gue menyusuri jalan yang sama dengan jalan ketika gue datang tadi, mampir sebentar ke Family Mart untuk beli air minum dan di situlah gue baru sadar kalau ternyata gue laper banget. Saat itu gue nggak bisa memikirkan akan makan di mana tapi satu tempat muncul di kepala gue: Siam Square.
Enggak tahu kenapa. Random aja itu tempat muncul di kepala. Gue langsung Googling caranya ke sana dan kebetulan masih satu jalur sama BTS gue di sini. Amanlah. Karena gue sudah jago (WKWKWKKW) naik BTS gue nggak perlu lagi nanya-nanya sama orang gimana caranya beli tiket dan sebagainya. Gue sampai di stasiun BTS Siam enggak terlalu lama karena memang enggak terlalu jauh. Mengikuti langkah kaki gue yang seenaknya aja pokoknya jalan. Tiba-tiba aja gue udah ada di food court dan yah, kayaknya memang badan gue lebih paham kalau mereka butuh makan. Seporsi nasi goreng sepertinya akan membuat mereka lebih baik. Gue juga butuh kopi sepertinya karena gue ngantuk banget.
Selama makan dan mengunyah gue kepikiran banyak hal. Tapi yang paling atas dari segala pikiran-pikiran itu adalah sebuah pertanyaan yang mendadak ingin gue cari jawabannya dengan membuktikannya sendiri. Pertanyaan yang nggak ada hubungannya sama perjalanan ini tapi ada hubungannya dengan orang yang gue chat sebelum gue berangkat dan bikin gue galau sampai mimpi buruk di pesawat.
“Kalau orang udah bilang nggak suka sama lo, tapi lo tetap berusaha menunjukkan perhatian lo ke dia, bisakah perasaannya berubah?”
Kadang gue benci jadi diri gue sendiri.














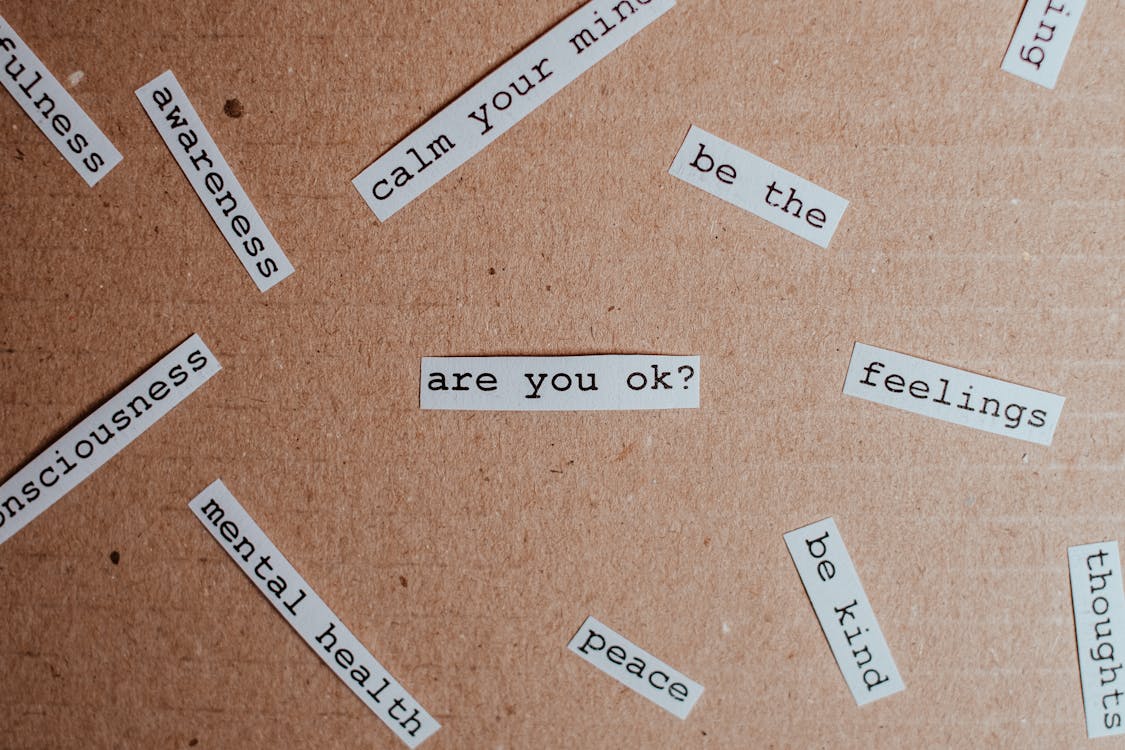









0 comments